Ecobiz.asia – Indonesia merupakan negara megadiversitas yang dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, khususnya dalam sektor kehutanan dan perkebunan. Dua komoditas utama yang mencerminkan kekuatan sumber daya alam tersebut adalah hasil hutan dan kelapa sawit. Keduanya bukan hanya menjadi sumber pendapatan nasional yang signifikan, tetapi juga memiliki pengaruh strategis dalam percaturan perdagangan internasional.

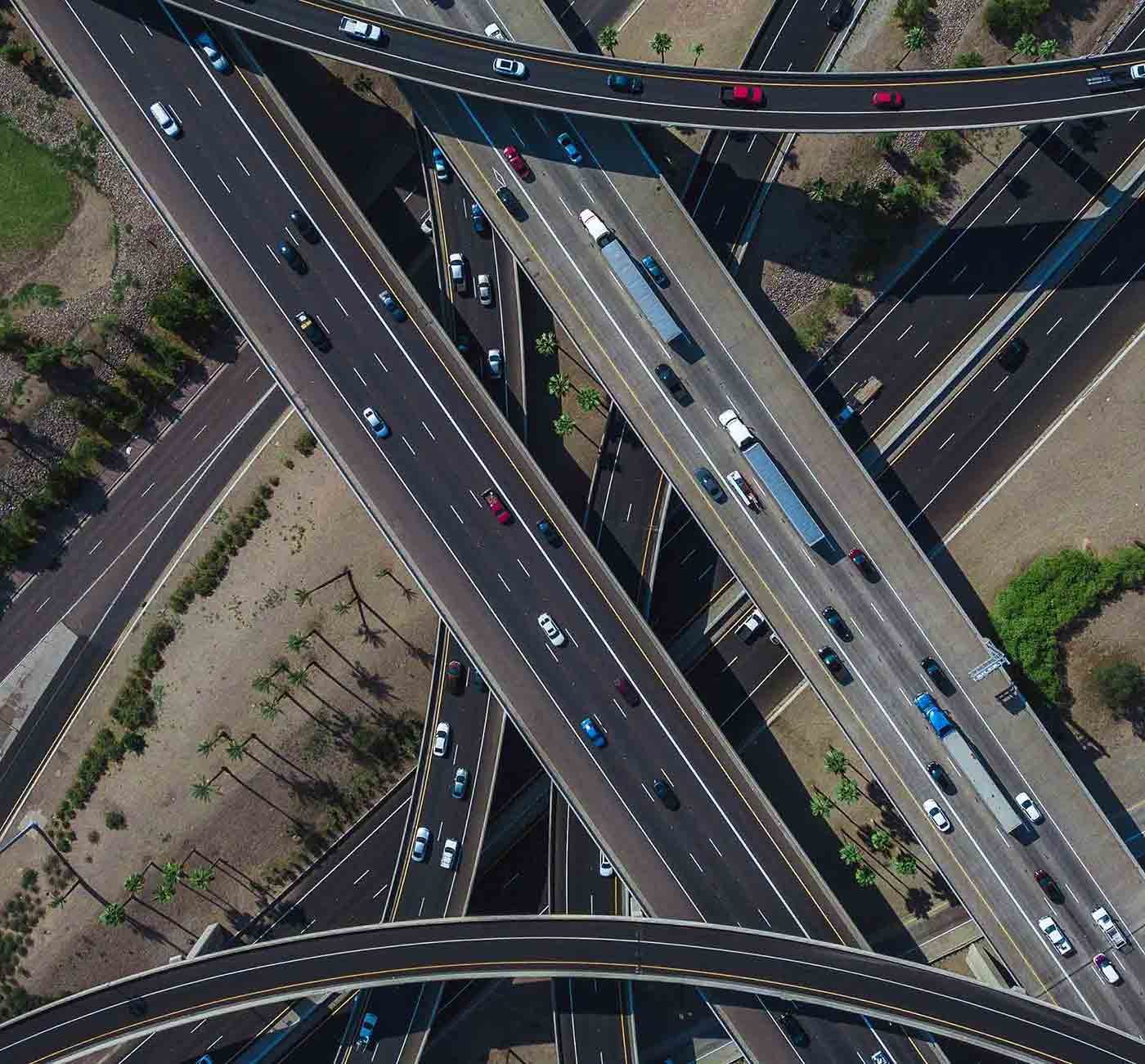
Diah Suradiredja
Ekspor hasil hutan Indonesia—baik berupa kayu olahan, rotan, maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK)—menyasar pasar global seperti Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Sementara itu, kelapa sawit menempatkan Indonesia sebagai eksportir minyak nabati terbesar dunia, dengan kontribusi signifikan terhadap devisa negara dan penghidupan jutaan rumah tangga petani.
Namun, dalam dua dekade terakhir, terjadi pergeseran paradigma dalam tata kelola perdagangan global. Dunia internasional, khususnya negara-negara maju, mulai menuntut agar produk yang masuk ke pasar mereka tidak hanya legal secara administratif, tetapi juga bebas dari praktik-praktik yang merusak lingkungan seperti deforestasi, degradasi hutan, dan pelanggaran hak asasi manusia.
Tuntutan ini diwujudkan dalam kebijakan regulatif yang lebih ketat, salah satunya adalah European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) yang disahkan pada 2023 dan mulai diberlakukan penuh pada akhir 2024.
EUDR merupakan bentuk konkret dari kebijakan berbasis keberlanjutan (sustainability-driven policy) yang mengatur tujuh komoditas utama—termasuk kelapa sawit dan kayu—agar terbebas dari jejak deforestasi. Implikasi dari regulasi ini sangat besar bagi negara-negara penghasil komoditas tropis seperti Indonesia, karena menyangkut perubahan dalam sistem produksi, rantai pasok, hingga mekanisme pembuktian legalitas dan keberlanjutan. Dengan kata lain, perdagangan global tidak lagi hanya soal harga dan volume, melainkan juga soal credibility dan traceability.
Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis ulang posisi strategis hasil hutan dan sawit Indonesia. Di satu sisi, keduanya tetap menjadi tumpuan ekonomi nasional, dengan kontribusi nyata terhadap ekspor, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan di daerah.
Di sisi lain, keduanya juga menjadi sasaran kritik global terkait deforestasi dan perubahan iklim. Ketegangan antara aspek ekonomi dan ekologi ini membutuhkan pendekatan kebijakan yang integratif, adil, dan berbasis bukti. Tulisan ini berupaya menjembatani kedua sisi tersebut dengan menyajikan analisis yang mengaitkan potensi ekonomi hasil hutan dan sawit Indonesia dengan tantangan baru dalam kerangka perdagangan global yang kini semakin didorong oleh prinsip keberlanjutan.
Dunia internasional, khususnya negara-negara maju, mulai menuntut agar produk yang masuk ke pasar mereka tidak hanya legal secara administratif, tetapi juga bebas dari praktik-praktik yang merusak lingkungan
1. Posisi Strategis Hasil Hutan dan Sawit dalam Perdagangan Global
Indonesia merupakan salah satu negara penyangga utama perdagangan global di sektor kehutanan dan perkebunan, terutama melalui ekspor hasil hutan dan minyak kelapa sawit. Kedua komoditas ini tidak hanya menopang struktur ekonomi nasional, tetapi juga membentuk posisi geopolitik Indonesia dalam arsitektur perdagangan internasional.
- • Hasil Hutan: Kontributor Devisa dan Pilar Ekonomi Hijau
Produk hasil hutan Indonesia mencakup berbagai kategori: kayu bulat, kayu olahan (seperti plywood, veneer, particle board), serta hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti rotan, damar, getah, madu, dan bambu. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2023), nilai ekspor hasil hutan mencapai USD 13,42 miliar, menjadikan sektor ini sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar di luar sektor migas.
Pasar utama dari hasil hutan Indonesia antara lain adalah Uni Eropa (26%), Tiongkok (18%), Jepang (13%), dan Amerika Serikat (12%). Dominasi produk Indonesia di pasar global tidak hanya didorong oleh volume dan keanekaragaman produk, tetapi juga oleh sistem legalitas kayu yang telah diakui secara internasional melalui skema Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sejak tahun 2016, SVLK telah memperoleh pengakuan dalam bentuk FLEGT-VPA dari Uni Eropa yang memudahkan akses pasar ke benua tersebut. Namun demikian, tantangan ke depan adalah bahwa EUDR memperluas fokus dari legalitas menuju keberlanjutan yang bebas deforestasi (deforestation-free products)—sebuah standar baru yang mensyaratkan keterlacakan lahan secara presisi.
Lebih dari itu, HHBK memiliki nilai strategis dalam pembangunan ekonomi desa, diversifikasi ekonomi masyarakat sekitar hutan, dan sebagai penyangga bioekonomi masa depan. Misalnya, Indonesia adalah produsen rotan terbesar dunia dan menyuplai lebih dari 80% kebutuhan pasar internasional, namun nilai tambahnya masih terbatas karena rendahnya kapasitas pengolahan lokal.
- • Kelapa Sawit: Komoditas Global, Dilema Lingkungan
Indonesia adalah produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia, dengan luas lahan sawit mencapai 16,38 juta hektare dan produksi sebesar 51,3 juta ton CPO pada 2023 (Kementerian Pertanian, 2024). Komoditas ini menyumbang lebih dari USD 28 miliar devisa dan mencakup 13–15% dari ekspor non-migas nasional. Tidak hanya menyokong industri besar, lebih dari 42% lahan sawit dikelola oleh petani kecil, menjadikannya instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan daerah.
Baca juga: Menteri LH Peringatkan Pengusaha Sawit Jaga Kelestarian Satwa, Dari Gajah hingga Badak
Pasar utama CPO Indonesia adalah India (20%), Tiongkok (15%), Uni Eropa (12%), Pakistan, dan negara-negara Timur Tengah serta Afrika Utara. Namun, ekspansi sawit yang pesat sering dikaitkan dengan deforestasi, kebakaran lahan, dan konflik tenurial, yang menjadikan sawit sebagai subjek kontroversial dalam diplomasi lingkungan global. Kampanye negatif terhadap sawit telah memicu hambatan non-tarif yang semakin ketat, seperti Renewable Energy Directive (RED) II dan EUDR.
Ironisnya, beberapa studi menunjukkan bahwa sawit memiliki efisiensi lahan tertinggi dibandingkan minyak nabati lainnya, seperti minyak kedelai, bunga matahari, dan rapeseed. Produktivitas sawit dapat mencapai 4–6 ton minyak/ha/tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan kedelai (0,4 ton/ha) dan bunga matahari (0,6 ton/ha). Oleh karena itu, dalam konteks global, mengganti sawit dengan minyak nabati lain justru berpotensi memperluas deforestasi global karena kebutuhan lahan yang lebih besar.
- • Perbandingan dan Potensi Integrasi
Dalam konteks global trade, baik hasil hutan maupun sawit memiliki potensi besar sebagai pilar dari “ekspor hijau” (green export) Indonesia. Hasil hutan dapat diposisikan dalam kerangka bioekonomi dan material ramah lingkungan, sementara sawit dapat menjadi andalan dalam bioenergi dan substitusi produk berbasis fosil. Tantangan yang muncul adalah bagaimana memastikan kedua sektor ini tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga inklusif dan patuh terhadap standar keberlanjutan internasional, terutama dalam konteks traceability dan non-deforestation.
Korelasi antara hasil hutan dan sawit juga dapat dijembatani melalui pendekatan agroforestri dan tata kelola lanskap (landscape governance) yang memungkinkan koeksistensi sawit dengan tanaman kehutanan dan HHBK di wilayah yang sama. Model ini mendukung keberlanjutan ekologis dan sosial, serta merespons tekanan internasional yang menginginkan transisi menuju rantai pasok yang hijau dan adil.
Gambar 1. Perbandingan Nilai Ekspor Hasil Hutan Dan Sawit Indonesia Ke Pasar Utama Tahun 2023.

Grafik di atas menunjukkan perbandingan nilai ekspor hasil hutan dan minyak sawit Indonesia ke beberapa pasar utama dunia pada tahun 2023. Terlihat bahwa:
- 1. Minyak sawit mendominasi ekspor ke India dan negara lain di luar 4 besar.
- 2. Hasil hutan memiliki kontribusi signifikan di Uni Eropa dan Amerika Serikat.
- 3. Keduanya penting dalam diversifikasi pasar dan menjaga stabilitas perdagangan global Indonesia.
2. EUDR: Perubahan Lanskap Perdagangan Global
Dalam dua dekade terakhir, lanskap perdagangan global telah mengalami transformasi signifikan yang tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika tarif dan permintaan pasar, tetapi juga oleh peningkatan perhatian terhadap isu-isu lingkungan dan sosial dalam rantai pasok. Salah satu bentuk paling konkret dari transformasi ini adalah diberlakukannya European Union Deforestation-free Regulation (EUDR), sebuah regulasi yang dirancang untuk memastikan bahwa produk yang dipasarkan di Uni Eropa tidak berkontribusi terhadap deforestasi global.
- • Inti Regulasi dan Paradigma Baru
EUDR, yang mulai berlaku pada akhir 2024, berlaku untuk tujuh komoditas strategis: kelapa sawit, kayu, kopi, kakao, kedelai, daging sapi, dan karet. Regulasi ini menetapkan bahwa seluruh produk tersebut harus:
- 1. Tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi atau degradasi hutan setelah 31 Desember 2020;
- 2. Memiliki dokumen due diligence yang mencakup pembuktian legalitas, keberlanjutan, dan koordinat geospasial asal produksi;
- 3. Dapat ditelusuri secara penuh hingga ke lahan asal produksi melalui sistem pelacakan digital;
- 4. Melewati proses klasifikasi risiko oleh otoritas Uni Eropa—negara asal akan dikategorikan sebagai risiko tinggi, standar, atau rendah.
Paradigma baru ini menggeser fokus perdagangan dari sekadar compliance administratif menuju performance-based compliance yang mengedepankan bukti konkret atas keberlanjutan lingkungan. Ini berarti bahwa hanya negara dan pelaku usaha yang mampu menunjukkan keterlacakan dan kebebasan dari deforestasi yang dapat mempertahankan akses ke pasar Eropa.
Baca juga: Produsen Plywood Antisipasi Manuver Trump Naikkan Tarif Impor Kayu
Struktur Kepatuhan dalam Alur Due Diligence EUDR

- • Posisi Indonesia: Antara Tekanan, Diplomasi, dan Inovasi
Bagi Indonesia, EUDR adalah tantangan besar sekaligus peluang untuk membenahi tata kelola sektor kehutanan dan perkebunan. Pemerintah dan pelaku industri menilai bahwa penerapan EUDR memiliki implikasi signifikan terhadap:
- 1. Akses pasar, karena Eropa merupakan mitra dagang penting—khususnya untuk CPO, kayu olahan, dan HHBK;
- 2. Petani kecil, yang mengelola lebih dari 40% lahan sawit, namun sering terkendala legalitas lahan dan teknologi pelacakan;
- 3. Beban kepatuhan, karena sistem traceability, geolokasi, dan dokumentasi due diligence membutuhkan biaya tinggi dan kapasitas kelembagaan yang belum merata.
Namun demikian, Indonesia juga mengambil posisi progresif dan adaptif, sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa langkah strategis:
- 1. Kemenangan di WTO atas gugatan diskriminasi biodiesel sawit pada Januari 2025 memberikan legitimasi internasional bahwa standar keberlanjutan harus bersifat non-diskriminatif dan berbasis sains, bukan kepentingan dagang tersembunyi.
- 2. Penyusunan Sistem Dashboard Nasional Komoditas Strategis dan penguatan SVLK sebagai bukti bahwa Indonesia siap bertransformasi menuju sistem verifikasi dan keterlacakan berbasis yurisdiksi.
- 3. Diplomasi bilateral dan regional, termasuk pembentukan kelompok kerja teknis Indonesia–Uni Eropa untuk menyelaraskan implementasi EUDR dengan realitas struktural di negara-negara tropis.
- 4. Advokasi untuk klasifikasi risiko negara yang adil, agar Indonesia tidak digeneralisasi sebagai negara berisiko tinggi, mengingat sebagian besar deforestasi saat ini justru telah menurun signifikan berkat moratorium izin baru dan restorasi hutan gambut.
Baca juga: Pengusaha Kayu Indonesia Bidik Pasar Timteng dan Afrika Lewat Dubai, Potensinya Besar
-
- • Dilema Global dan Ketimpangan Kepatuhan
Meski secara normatif EUDR bertujuan mulia, secara praktis terdapat tantangan global yang belum terselesaikan. Pertama, beban regulasi yang berat jatuh kepada negara berkembang, padahal sebagian besar produk dari negara maju belum dihadapkan pada kewajiban yang setara. Kedua, ketimpangan teknologi dan pendanaan menyebabkan petani kecil dan UMKM menghadapi risiko eksklusi dari pasar premium. Ketiga, definisi dan parameter deforestasi sering kali tidak mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi dan dinamika hukum tenurial di negara-negara Global South.
Dengan demikian, implementasi EUDR membutuhkan pendekatan yang lebih kolaboratif dan kontekstual, termasuk pembiayaan transisi hijau, penyederhanaan prosedur kepatuhan, dan pengakuan terhadap sistem nasional yang telah berjalan seperti SVLK dan ISPO.
3. Respon Strategis Indonesia dan Peluang Perdagangan Hijau
Menghadapi tantangan besar yang ditimbulkan oleh EUDR, Indonesia tidak hanya bereaksi secara defensif, tetapi mulai membangun serangkaian strategi transformatif untuk mempertahankan daya saing komoditas strategisnya sekaligus memperkuat kredibilitas keberlanjutan di pasar global.
Pendekatan ini mencerminkan evolusi dari reaktif menjadi proaktif, dengan memperhatikan tiga pilar utama: diplomasi perdagangan, reformasi tata kelola, dan pengembangan ekonomi hijau berbasis keunggulan domestik.
- • Diplomasi Perdagangan dan Kemenangan dalam Forum Internasional
Indonesia secara aktif menggunakan forum perdagangan multilateral dan bilateral untuk memperjuangkan hak atas perdagangan yang adil dan berbasis pada prinsip kesetaraan. Kemenangan parsial Indonesia dalam gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap kebijakan diskriminatif Uni Eropa terhadap biodiesel berbasis sawit, menjadi titik balik penting dalam memperkuat posisi tawar Indonesia.
Dalam konteks EUDR, Indonesia mengadopsi pendekatan constructive engagement, yakni bukan menolak regulasi, tetapi mendorong agar implementasinya mempertimbangkan kapasitas negara berkembang, termasuk tantangan legalitas lahan, kelembagaan, dan keterlibatan petani kecil. Melalui platform dialog teknis Indonesia–EU, pemerintah mendorong mutual recognition terhadap sistem nasional seperti ISPO dan SVLK.
- • Reformasi Tata Kelola: Digitalisasi, Yuridiksi, dan Pelibatan Petani Kecil
Respon domestik terhadap EUDR ditandai dengan berbagai inisiatif reformasi tata kelola komoditas kehutanan dan perkebunan:
(1) Dashboard Nasional Komoditas Berkelanjutan dikembangkan untuk mengintegrasikan data lahan, geolokasi, legalitas, dan status sertifikasi petani kecil. Sistem ini merupakan langkah awal menuju traceability platform berbasis yurisdiksi.
(2) Jurisdictional Approach (Pendekatan Yuridiksi) diperkuat di berbagai provinsi seperti Kalimantan Barat dan Riau, guna menciptakan ekosistem keberlanjutan yang menyatukan pemerintah daerah, koperasi petani, dan sektor swasta. Pendekatan ini selaras dengan prinsip EUDR yang tidak hanya mengejar kepatuhan produk, tetapi juga sistem tata kelola wilayah.
(3) Skema pembiayaan inklusif dan inovatif, seperti pembiayaan transisi hijau, obligasi hijau (green bonds), dan dana kemitraan petani-korporasi, sedang dirancang untuk mendukung petani kecil dalam memenuhi persyaratan due diligence tanpa membebani secara finansial.
- • Peluang Ekonomi Hijau dan Diversifikasi Pasar
EUDR, meskipun menantang, membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk:
(1) Mengembangkan branding ekspor hijau seperti “Deforestation-Free Palm Oil” atau “Sustainable Forest Products from Indonesia“, yang dapat menarik premium price dan akses ke niche market yang tumbuh di Eropa, Amerika Utara, dan negara-negara Nordik.
(2) Menjadi pemimpin di pasar ekspor selatan-selatan, seperti Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Selatan, yang memiliki permintaan tinggi namun regulasi keberlanjutan yang lebih fleksibel. Strategi diversifikasi ini penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar Eropa.
(3) Mengintegrasikan sawit dan hasil hutan dalam model agroforestri, terutama di kawasan hutan produksi tidak produktif, yang memungkinkan kombinasi produksi ekonomi dengan restorasi ekologis. Inovasi ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam kerangka ekonomi sirkular dan bioekonomi global.
- • Kolaborasi Multi-Pihak: Kunci Kesuksesan Implementasi
Keberhasilan strategi nasional tidak bisa hanya bergantung pada negara. Kolaborasi dengan aktor-aktor seperti LSM, akademisi, pelaku industri, koperasi petani, dan mitra pembangunan internasional menjadi elemen kunci dalam membangun arsitektur keberlanjutan yang efektif. Program seperti LANDscale (IUCN-UNDP), Terpercaya (UNDP-Bappenas), dan IDH Landscape Program merupakan contoh inisiatif yang menghubungkan rantai pasok dengan transformasi tata kelola lokal secara partisipatif.
Dengan demikian, alih-alih melihat EUDR sebagai ancaman, Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan momen ini sebagai lompatan menuju perdagangan hijau yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis pada kekuatan lokal.
Baca juga: Puas dengan Kualitas Kayu Indonesia, Importir Inggris Sepakat Tingkatkan Impor
4. Kesimpulan dan Rekomendasi
Indonesia berada pada persimpangan strategis antara tuntutan global terhadap keberlanjutan dan kepentingan domestik dalam menjaga pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komoditas hasil hutan dan kelapa sawit, yang selama ini menjadi pilar penting dalam ekspor, penyediaan lapangan kerja, dan pengembangan wilayah, kini harus beradaptasi dengan rezim perdagangan baru yang ditandai oleh regulasi lingkungan yang ketat, seperti EUDR.
Regulasi ini tidak hanya mengubah syarat masuk pasar, tetapi juga mendorong transformasi mendalam dalam cara Indonesia mengelola sumber daya alamnya—dari aspek legalitas, tata ruang, hingga keterlibatan petani kecil dan transparansi rantai pasok. Meski diwarnai oleh tantangan seperti ketimpangan data, biaya kepatuhan, dan ancaman eksklusi pasar terhadap kelompok rentan, EUDR juga membuka peluang besar: untuk memperbaiki tata kelola, membangun sistem pelacakan nasional yang tangguh, dan memosisikan Indonesia sebagai pelopor dalam perdagangan hijau global.
Lebih dari itu, respon Indonesia terhadap EUDR merupakan cerminan dari kematangan diplomasi lingkungan dan perdagangan, dengan sikap yang tidak lagi sekadar reaktif tetapi konstruktif, mendorong pengakuan atas sistem keberlanjutan nasional yang sudah ada, seperti SVLK dan ISPO, dan membuka ruang untuk koeksistensi antara konservasi dan kesejahteraan.
Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:
- • Harmonisasi Regulasi Domestik dan Internasional
Pemerintah perlu menyelaraskan regulasi nasional—termasuk perizinan lahan, tata ruang, dan sistem verifikasi keberlanjutan—agar konsisten dengan prinsip-prinsip EUDR. Ini termasuk revisi terhadap tumpang tindih kawasan hutan dan perkebunan serta percepatan legalisasi lahan petani kecil.
- • Penguatan Infrastruktur Traceability Berbasis Digital
Perluasan dan penyempurnaan sistem digital seperti SIPERIBUN (Sawit) dan SILK (Kayu) sangat krusial. Sistem ini harus mampu menjangkau petani kecil dan menengah serta terintegrasi dengan geolokasi dan data legalitas berbasis yurisdiksi.
- • Skema Dukungan Inklusif untuk Petani Kecil
Pemerintah dan mitra internasional perlu menciptakan skema pembiayaan adaptif seperti subsidi kepatuhan, dana pendampingan, dan insentif fiskal untuk petani dan koperasi agar dapat memenuhi standar EUDR tanpa dikorbankan dari akses pasar.
- • Diplomasi Perdagangan Berbasis Bukti dan Kolaborasi Selatan-Selatan
Indonesia perlu memperkuat posisi tawar dalam forum internasional dengan pendekatan berbasis bukti (evidence-based diplomacy), sambil menjalin kemitraan dengan negara produsen lain (seperti Malaysia, Brasil, dan Kolombia) untuk membangun koalisi negara tropis dalam menyuarakan keadilan ekologi dalam perdagangan global.
- • Pengembangan Model Integratif: Agroforestri dan Bioekonomi Lokal
Menggabungkan hasil hutan dan sawit dalam model agroforestri berbasis lanskap dapat menjadi solusi hibrid yang menjawab kebutuhan ekologis dan ekonomi. Model ini sekaligus mendukung transformasi menuju ekonomi rendah karbon dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Baca juga: Menteri LH Beberkan Lima Penyebab Kebakaran Lahan, Soroti Land Clearing Perkebunan Sawit
Penutup Reflektif
EUDR bukan sekadar tantangan teknis, tetapi panggilan strategis bagi Indonesia untuk memperkuat sistem keberlanjutan domestik dan memperluas pengaruhnya dalam agenda perdagangan hijau global. Dengan kepemimpinan yang kuat, inovasi kebijakan, dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia tidak hanya bisa beradaptasi terhadap perubahan ini tetapi juga menjadi penentu arah perdagangan dunia yang adil, hijau, dan inklusif. ***
Oleh: Diah Suradiredja (Pemerhati perdagangan komoditas berkelanjutan)

