Ecobiz.asia – Pada bulan April 2025, Komisi Eropa merilis dokumen panduan terbaru beserta versi keempat dari daftar Frequently Asked Questions (FAQs) terkait European Union Deforestation-free Regulation (EUDR). Selang sebulan kemudian, tepatnya pada 22 Mei 2025, Komisi mengadopsi Peraturan Pelaksana (Implementing Regulation) yang memperkenalkan sistem klasifikasi negara berdasarkan tingkat risiko deforestasi dalam produksi tujuh komoditas utama yang tercakup dalam EUDR, yakni sapi, kakao, kopi, kelapa sawit, karet, kedelai, dan kayu.
Pasal 1 dalam peraturan pelaksana tersebut menetapkan bahwa negara-negara diklasifikasikan ke dalam kategori risiko rendah, standar, atau risiko tinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran, sementara negara yang tidak tercantum akan berada dalam kategori risiko standar. Sistem benchmarking ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat risiko produksi komoditas yang tidak memenuhi standar bebas deforestasi, sesuai cakupan EUDR.
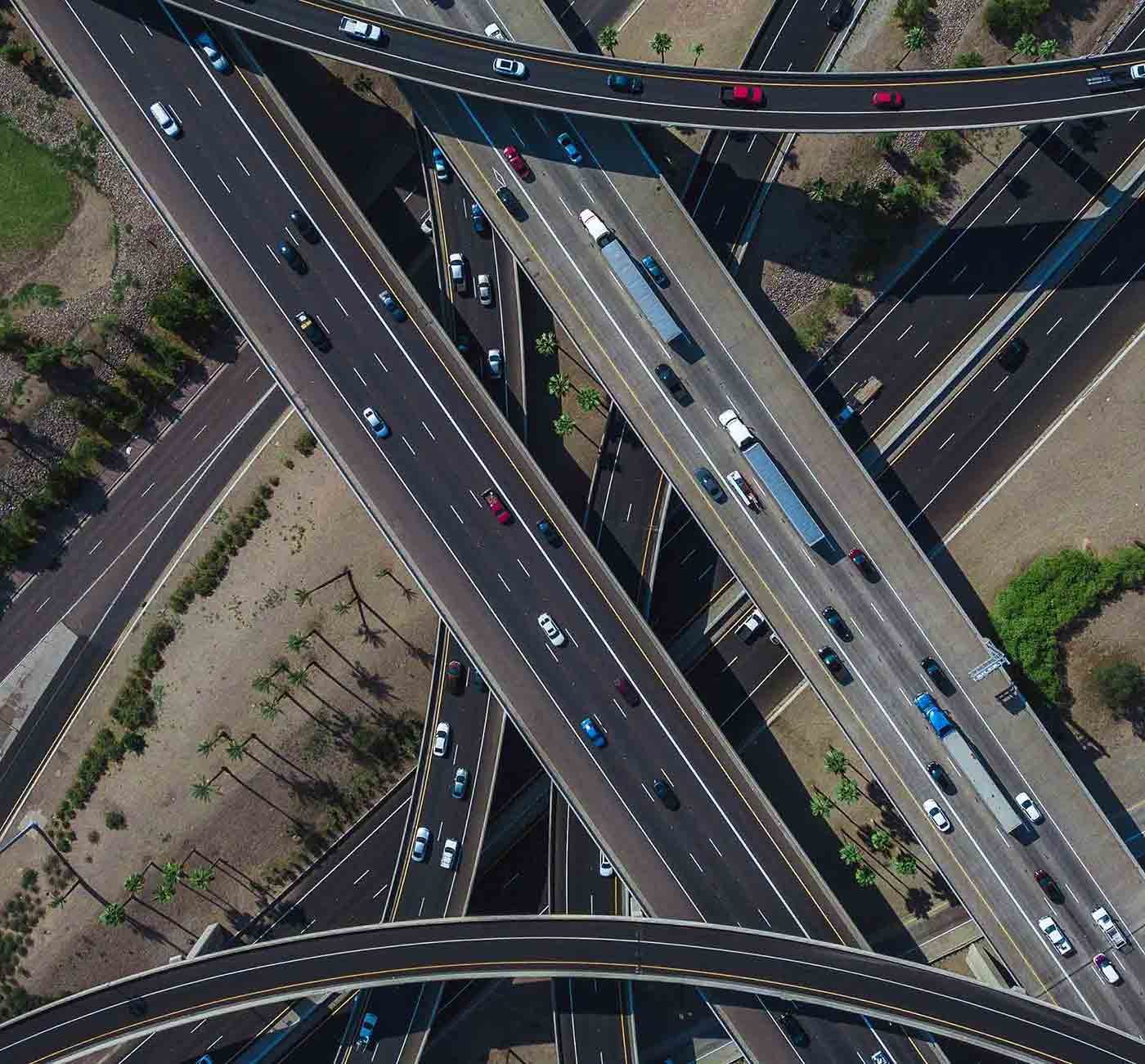
Metodologi yang digunakan oleh Komisi Eropa diklaim berlandaskan prinsip keadilan, objektivitas, dan transparansi. Adapun penilaian terhadap seluruh negara dilakukan berdasarkan kriteria kuantitatif sebagaimana tertuang dalam Pasal 29(3) EUDR, dengan mengandalkan data terkini dari Global Forest Resources Assessment yang disusun oleh Food and Agriculture Organization (FAO FRA).
Sebagai prinsip umum, Operator diwajibkan membangun dan mempertahankan sistem uji tuntas (Due Diligence System) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 EUDR. Sistem ini terdiri dari tiga tahapan utama: (1) pengumpulan informasi—meliputi data dan dokumen pembuktian produk bebas deforestasi dan legal, seperti koordinat geolokasi, jumlah produk, serta negara asal produksi; (2) penilaian risiko—operator harus menunjukkan bagaimana informasi yang dikumpulkan diverifikasi terhadap kriteria risiko yang ada; dan (3) mitigasi risiko—apabila terdapat potensi ketidaksesuaian, operator wajib mengadopsi prosedur mitigasi yang memadai agar risiko menjadi dapat diabaikan (negligible).
Sistem benchmarking ini dirancang untuk mempermudah proses uji tuntas, sekaligus memperkuat kapasitas otoritas negara anggota dalam melakukan pengawasan dan penegakan kepatuhan. Lebih dari itu, sistem ini juga diharapkan mampu mendorong negara-negara produsen untuk meningkatkan keberlanjutan dalam sistem produksi agrikultur mereka dan meminimalkan dampak terhadap deforestasi.
Tingkat klasifikasi risiko juga menentukan sejauh mana pemeriksaan kepatuhan akan dilakukan oleh otoritas negara anggota terhadap operator yang mengambil pasokan dari negara tertentu: 1% untuk negara berisiko rendah, 3% untuk risiko standar, dan 9% untuk risiko tinggi. Operator yang mengambil dari negara berisiko rendah akan mendapat kewajiban uji tuntas yang lebih sederhana—mereka cukup mengumpulkan informasi tanpa perlu melakukan penilaian dan mitigasi risiko. Sebaliknya, operator yang mengambil dari negara berisiko standar maupun tinggi tetap menjalani proses uji tuntas penuh, dengan perbedaan pada intensitas pengawasan dari otoritas. Untuk negara berisiko tinggi, pengawasan dilakukan lebih ketat dengan rasio 9%.
Perlu ditekankan bahwa klasifikasi ini tidak serta-merta menuntut perubahan drastis pada rantai pasok global. Namun, status risiko tinggi akan membuka ruang dialog antara negara yang bersangkutan dan Komisi Eropa guna mengidentifikasi akar penyebab deforestasi dan merumuskan langkah-langkah korektif, dengan tujuan menurunkan tingkat risikonya di masa mendatang.
Country Classification, Indonesia masuk Standar Risk
Setelah melalui proses yang memakan waktu hampir dua tahun dan memicu berbagai ketegangan diplomatik—terutama dari negara-negara pengekspor besar seperti Brasil, Malaysia, dan Indonesia—pada tanggal 22 Mei 2025, Komisi Eropa secara resmi menerbitkan klasifikasi negara berdasarkan sistem benchmarking risiko dalam kerangka EUDR. Langkah ini menandai tahapan krusial dalam penerapan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) sebagai fondasi pengawasan rantai pasok komoditas yang berpotensi menyebabkan deforestasi.
Sebagai bagian dari instrumen pelaksanaan EUDR, klasifikasi ini secara langsung menentukan tingkat kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh operator dan pedagang dari negara-negara produsen. Komisi membagi negara-negara ke dalam tiga kategori risiko: rendah (low risk), sedang (standard risk), dan tinggi (high risk). Setiap kategori memiliki konsekuensi yang berbeda dalam hal frekuensi pemeriksaan, kedalaman uji tuntas, serta intensitas keterlibatan dengan otoritas pengawas Uni Eropa.
Secara kuantitatif, mayoritas negara di dunia—sekitar 140 negara, termasuk seluruh negara anggota Uni Eropa—masuk dalam kategori risiko rendah. Operator dari negara-negara ini akan menghadapi beban verifikasi yang paling ringan, dengan hanya sekitar 1% pemeriksaan terhadap rantai pasoknya. Pencantuman negara-negara Uni Eropa dalam kategori ini menegaskan upaya UE dalam memposisikan diri sebagai benchmark tata kelola keberlanjutan global. Namun, posisi ini tidak lepas dari kritik, mengingat masih adanya praktik deforestasi residual di beberapa negara anggota yang belum sepenuhnya diatasi.
Berbeda halnya dengan kategori risiko sedang atau standar, yang mencakup sekitar 50 negara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Brasil—tiga aktor utama dalam perdagangan komoditas yang terdampak langsung oleh EUDR. Penempatan negara-negara ini dalam kategori standard risk merefleksikan suatu bentuk pengakuan atas kemajuan tata kelola kehutanan nasional, namun juga menunjukkan bahwa masih terdapat celah signifikan dalam hal akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum. Secara praktis, operator dari negara-negara ini wajib menjalani proses uji tuntas penuh dan akan dikenai rasio pemeriksaan sekitar 3%. Bagi Indonesia, klasifikasi ini memiliki makna strategis: meskipun tidak dikategorikan sebagai negara berisiko tinggi, status ini tetap menuntut pembenahan serius dalam pelaporan, keterlacakan, serta efektivitas sistem verifikasi.
Bagi Indonesia, klasifikasi ini memiliki makna strategis: meskipun tidak dikategorikan sebagai negara berisiko tinggi, status ini tetap menuntut pembenahan serius dalam pelaporan, keterlacakan, serta efektivitas sistem verifikasi.
Baca juga: Keadilan dalam Perdagangan Global: Refleksi Kritis atas Pembaruan Panduan EUDR dan Implikasi bagi Negara Produsen
Sementara itu, hanya empat negara yang diklasifikasikan dalam kategori risiko tinggi, yaitu Belarus, Myanmar, Korea Utara, dan Rusia. Keempat negara ini tidak hanya menunjukkan tingkat risiko deforestasi yang tinggi, tetapi juga menghadapi sanksi dari Dewan Keamanan PBB atau Dewan Uni Eropa terkait komoditas yang relevan dengan EUDR. Posisi geopolitik yang kompleks dan lemahnya tata kelola institusional menyebabkan keempat negara tersebut dinilai tidak layak dipercaya dalam hal pemenuhan prinsip keberlanjutan. Akibatnya, operator dari negara-negara ini akan menghadapi tingkat pengawasan tertinggi, dengan intensitas pemeriksaan mencapai 9% dari volume perdagangan mereka. Meskipun jumlah negara dalam kategori ini relatif kecil, klasifikasi high risk secara implisit berfungsi sebagai alat tekanan diplomatik—sekaligus menegaskan bahwa EUDR bukan hanya instrumen teknokratis, melainkan juga instrumen politik dalam mengatur ulang hubungan dagang global.
Secara keseluruhan, sistem klasifikasi ini merepresentasikan model hibrida antara teknokrasi dan politik. Di satu sisi, ia bertumpu pada indikator objektif berbasis data (seperti FAO FRA), tetapi di sisi lain tetap menyisakan ruang interpretatif untuk mempertimbangkan komitmen dan kapasitas institusional masing-masing negara. Implikasinya bagi negara seperti Indonesia bersifat ambivalen: sebagai peluang dan peringatan sekaligus. Peluang, karena Indonesia masih memiliki akses pasar Eropa tanpa stigma risiko tinggi. Namun juga sebagai peringatan, karena klasifikasi ini akan dievaluasi ulang setiap dua tahun. Artinya, kegagalan dalam memperkuat sistem keberlanjutan dapat berujung pada peningkatan risiko dan konsekuensi administratif yang lebih berat. Sebaliknya, jika Indonesia mampu menunjukkan upaya reformasi yang terukur dan sistemik—khususnya dalam hal keterlacakan berbasis geospasial dan transparansi data—maka peluang untuk menurunkan tingkat risiko dan memperkuat daya saing ekspor akan terbuka lebar.
Resistensi dan Respons: Dinamika Internasional terhadap Sitem Klasifikasi Risiko EUDR
Penerapan sistem klasifikasi negara dalam kerangka EUDR tidak hanya berdampak teknis terhadap rantai pasok global, tetapi juga memicu dinamika politik yang signifikan. Sejumlah negara dan kelompok kepentingan—baik dari dalam maupun luar Uni Eropa—menyampaikan kritik tajam dan seruan revisi terhadap aspek-aspek tertentu dalam regulasi tersebut. Setidaknya sebelas negara anggota Uni Eropa, termasuk Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Finlandia, Latvia, Portugal, Rumania, dan Slovenia, telah menandatangani permintaan resmi agar regulasi deforestasi ditinjau ulang. Keberatan mereka bukan semata-mata karena persoalan lingkungan, melainkan juga berkaitan dengan potensi gangguan terhadap keberlanjutan industri domestik dan beban uji tuntas yang dianggap memberatkan, baik bagi importir maupun eksportir dalam negeri Eropa.
Dari sisi masyarakat sipil, respons juga beragam. Sebagian aktivis lingkungan seperti Giulia Bondi dari Global Witness menekankan pentingnya menjaga integritas hukum EUDR, dengan argumen bahwa kewajiban due diligence tetap relevan bahkan bagi negara berisiko rendah. Di sisi lain, kelompok seperti Rainforest Foundation Norway (RFN) justru menilai pendekatan Komisi Eropa terlalu lunak. Mereka mempertanyakan logika di balik tidak dikategorikannya Brasil—yang menyumbang 42% kehilangan hutan tropis global pada tahun 2024—ke dalam daftar negara berisiko tinggi. Bagi RFN, hal ini mencerminkan inkonsistensi dalam penilaian risiko dan lemahnya efek jera terhadap negara-negara dengan rekam jejak deforestasi yang serius.
Respons keras juga datang dari negara-negara produsen seperti Malaysia, yang secara terbuka menyatakan ketidakpuasan atas penempatannya dalam kategori standard risk. Menteri Komoditas Malaysia, Johari Abdul Ghani, mengkritik Komisi Eropa karena mengacu pada data lama dari FAO (2020), yang menurutnya tidak mencerminkan kemajuan terkini dalam tata kelola kelapa sawit nasional. Dewan Minyak Sawit Malaysia menuding metodologi klasifikasi EUDR sebagai “sempit dan tidak lengkap,” karena hanya mempertimbangkan rerata kehilangan hutan tahunan tanpa menyesuaikan dengan konteks sektor spesifik seperti sawit. Tuduhan diskriminatif terhadap sektor minyak sawit pun mengemuka, terutama karena persepsi bahwa komoditas ini sering dijadikan kambing hitam dalam perdebatan deforestasi global.
Indonesia sendiri menunjukkan respons yang lebih kompleks dan terfragmentasi. Di satu sisi, lembaga-lembaga seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memandang EUDR sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola sektor komoditas yang selama ini rentan terhadap konflik agraria, kolusi, serta marginalisasi masyarakat adat. Inisiatif seperti Kebijakan Satu Peta, penguatan sertifikasi ISPO, dan peningkatan perlindungan kawasan hutan dipandang sebagai instrumen yang sejalan dengan semangat regulasi tersebut. Namun di sisi lain, pemerintah secara resmi mengkritik beberapa elemen fundamental dari EUDR. Tiga keberatan utama yang disuarakan mencakup: (1) ketidakpastian standar dan keamanan dalam kewajiban berbagi data sektor perkebunan, (2) ketidakjelasan metodologi klasifikasi risiko negara, dan (3) resistensi internal dari perusahaan-perusahaan Eropa sendiri, khususnya terkait isu data sharing yang bahkan telah memicu gugatan terhadap EUDR di beberapa negara seperti Jerman.
Baca juga: Masyarakat Sipil Tolak Pelemahan SVLK, Nilai Ekspor Kayu Indonesia Dipertaruhkan
Pernyataan resmi dalam rangka peringatan Hari Eropa 2025 menegaskan kembali posisi Indonesia yang berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen internasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menyatakan niatnya untuk memperkuat kerja sama strategis dengan Uni Eropa, termasuk dalam agenda keberlanjutan dan perdagangan yang adil. Pemerintah menyampaikan bahwa pendekatan terhadap regulasi seperti EUDR sebaiknya tidak didasarkan pada antagonisme, tetapi dijadikan sebagai bagian dari negosiasi yang konstruktif, seperti yang tengah berlangsung melalui forum Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Secara keseluruhan, respons terhadap sistem klasifikasi EUDR memperlihatkan bahwa kebijakan lingkungan transnasional seperti ini tak terlepas dari tarik-menarik politik, perbedaan epistemologi data, serta pertarungan legitimasi antara negara pengatur dan negara terdampak. Hal ini menegaskan kembali bahwa tata kelola keberlanjutan global tidak semata-mata soal norma dan prosedur, melainkan juga soal keadilan representasi, distribusi tanggung jawab, dan negosiasi makna atas apa yang disebut sebagai risiko deforestasi itu sendiri.
Antara Data dan Diplomasi: Menelisik Logika Sistem Klasifikasi Risiko Negara dalam EUDR
Sistem klasifikasi negara dalam EUDR diklaim oleh Komisi Eropa sebagai representasi dari pendekatan berbasis risiko yang objektif dan ilmiah. Dasar data yang digunakan merujuk pada sumber seperti FAO Global Forest Resources Assessment, yang secara teknis menyediakan indikator kuantitatif mengenai tutupan hutan, tingkat deforestasi, dan kapasitas tata kelola. Namun, ketika ditelaah lebih jauh, muncul sejumlah ketidaksesuaian antara logika teknokratik yang dikedepankan dan keputusan klasifikasi yang dihasilkan. Hal ini memunculkan ruang analisis kritis terhadap kemungkinan adanya intervensi politik atau bias strategis dalam pelaksanaan EUDR.
 Sumber: FAO, 2020.
Sumber: FAO, 2020.
Salah satu kontradiksi paling mencolok terlihat pada klasifikasi negara-negara dengan tutupan hutan luas seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan India, yang semuanya dikategorikan sebagai low risk. Padahal, berdasarkan data FAO, masing-masing dari ketiga negara ini memiliki lebih dari 300 juta, 200 juta, dan 70 juta hektare hutan—luas yang tidak jauh berbeda dengan negara-negara yang masuk kategori standard atau bahkan high risk. Jika parameter teknis seperti luasan hutan dan volume ekspor komoditas berisiko menjadi tolok ukur utama, maka logikanya negara-negara tersebut seharusnya mendapat pengawasan yang setara, atau setidaknya dikaji dengan standar yang sama.
 Sumber: Eurostat, 2025.
Sumber: Eurostat, 2025.
Namun, klasifikasi tersebut menjadi semakin kompleks ketika disandingkan dengan relasi dagang. Data Eurostat per Januari 2025 menunjukkan bahwa Amerika Serikat, Tiongkok, dan India termasuk dalam jajaran mitra dagang utama Uni Eropa. Maka muncul pertanyaan fundamental: sejauh mana kepentingan geopolitik dan ekonomi turut membentuk kebijakan yang diklaim berbasis sains ini? Ketidakkonsistenan antara profil ekologis dan perlakuan administratif menunjukkan bahwa klasifikasi dalam EUDR kemungkinan besar tidak bebas dari tekanan diplomatik dan kepentingan strategis Uni Eropa.
Baca juga: Pengusaha Mebel Tolak Pelemahan SVLK, Dorong Promosi Setara PEFC–FSC
Kasus Brasil menjadi titik perbandingan penting dalam kerangka ini. Sebagai negara dengan hutan tropis terluas kedua di dunia dan kontribusi signifikan terhadap ekspor komoditas berisiko, Brasil justru diklasifikasikan sebagai standard risk. Padahal jika menggunakan logika yang sama seperti yang diterapkan pada negara-negara Global North, Brasil—yang juga mitra dagang besar UE—dapat saja dikategorikan sebagai low risk apabila hanya mempertimbangkan indikator agregat. Fakta bahwa Brasil dikenai tingkat pemeriksaan lebih tinggi dan proses due diligence penuh mengindikasikan adanya standar ganda dalam pengklasifikasian.
Secara struktural, praktik ini membuka celah terhadap dua bentuk distorsi kebijakan: pertama, delegitimasi prinsip kehati-hatian dalam tata kelola rantai pasok global, karena kriteria yang digunakan tidak konsisten; dan kedua, reproduksi ketimpangan antara negara-negara Global North dan Global South dalam hal akses pasar dan beban regulasi. Dengan kata lain, sistem klasifikasi EUDR, alih-alih berfungsi sebagai alat untuk mendorong keberlanjutan secara merata, justru dapat memperkuat asymmetrical compliance burden—beban pembuktian yang secara tidak proporsional dijatuhkan kepada negara-negara berkembang.
Untuk memastikan kredibilitas dan legitimasi jangka panjang, sistem klasifikasi risiko negara dalam EUDR perlu dievaluasi secara berkala, tidak hanya dari segi efektivitas teknisnya, tetapi juga dari perspektif keadilan ekologis dan politik. Pengembangan indikator yang lebih granular dan transparansi dalam proses benchmarking—termasuk mekanisme keberatan atau banding antarnegara—merupakan langkah penting untuk menjaga agar EUDR tidak terjebak menjadi instrumen eco-imperialism yang hanya memperkuat ketimpangan dalam tatanan global.
Catatan Penting
Kebijakan EUDR hadir sebagai salah satu instrumen kebijakan lingkungan paling ambisius di level global, dengan klaim sebagai upaya sistematis untuk menghapus deforestasi dari rantai pasok komoditas strategis. Melalui pendekatan berbasis risiko dan sistem country classificatiton, EUDR membentuk arsitektur tata kelola yang menggabungkan sains, regulasi, dan perdagangan lintas batas. Namun, seperti yang ditunjukkan dalam analisis sebelumnya, desain dan implementasi kebijakan ini jauh dari sekadar teknokratis, melainkan juga memuat dimensi politis, ketimpangan struktural antara negara produsen dan konsumen, serta kompleksitas dinamika global antara kepentingan lingkungan dan realitas geopolitik.
Klasifikasi negara ke dalam tiga kategori risiko (rendah, sedang, tinggi) tidak hanya menghasilkan implikasi administratif bagi para pelaku usaha, tetapi juga mencerminkan bagaimana Uni Eropa menilai dan mendefinisikan legitimasi keberlanjutan di luar wilayahnya. Ketika negara-negara Global South seperti Indonesia, Malaysia, dan Brazil dikategorikan sebagai risiko sedang, sementara negara-negara Global North dengan profil kehutanan serupa justru masuk dalam kategori rendah, maka timbul pertanyaan mendasar mengenai objektivitas metodologi dan motif yang mendasarinya. Hal ini diperkuat dengan respons diplomatik, baik dari negara produsen yang mengkritik klasifikasi berbasis data usang, maupun dari sejumlah negara anggota UE sendiri yang mulai mempersoalkan efektivitas dan beban kebijakan ini.
Baca juga: Fitur Geolokasi Tegas di SVLK Plus, Ketelusuran Produk Kayu Indonesia Makin Kuat
Sementara negara produsen seperti Indonesia menghadapi tekanan untuk menunjukkan transparansi dan keterlacakan dalam rantai pasok komoditasnya pasca diterbitkannya country benchmarking dalam kerangka EUDR, dinamika reformasi internal di Uni Eropa justru menunjukkan arah yang lebih permisif. Dalam opini terbarunya, Bank Sentral Eropa (ECB) menyampaikan kekhawatiran atas proposal Komisi Eropa yang bertujuan menyederhanakan kewajiban pelaporan keberlanjutan melalui revisi Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dan Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Salah satu poin krusial adalah rencana pengurangan cakupan pelaporan hanya untuk perusahaan dengan lebih dari 1.000 karyawan, yang menurut ECB dapat mengurangi ketersediaan informasi penting seperti emisi gas rumah kaca dan data risiko ESG. ECB juga mengingatkan bahwa pengurangan ini berisiko melemahkan sistem pengawasan keuangan dan kredibilitas kebijakan transisi hijau UE sendiri. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan tentang konsistensi standar yang diberlakukan UE terhadap mitra dagangnya dengan standar yang diterapkan di dalam negerinya sendiri.
Masuk Kategori Risiko Standar: Apa Artinya bagi Indonesia dalam Regulasi Deforestasi Eropa?
Keputusan Komisi Eropa yang menetapkan Indonesia sebagai negara dengan kategori Standard Risk dalam regulasi deforestasi (EUDR) membawa sejumlah konsekuensi penting bagi arah perdagangan dan tata kelola komoditas Indonesia. Meski tidak tergolong dalam kelompok negara berisiko tinggi, status ini bukan tanpa beban. Justru sebaliknya, Indonesia kini berada di persimpangan antara peluang untuk memperbaiki sistem tata kelola dan tekanan untuk membuktikan keseriusan dalam agenda keberlanjutan.
Bagi pelaku usaha, status risiko standar berarti kewajiban melakukan uji tuntas penuh sebelum produk ekspor seperti kelapa sawit, kayu, karet, kopi, dan kakao bisa diterima di pasar Eropa. Mereka wajib menyertakan bukti legalitas dan bebas deforestasi, termasuk koordinat geolokasi titik produksi, sertifikat, dan dokumen pelengkap lainnya. Proses ini bukan sekadar formalitas, karena otoritas Eropa akan melakukan verifikasi secara acak dengan rasio 3% terhadap rantai pasok dari negara seperti Indonesia. Beban ini tentu lebih besar dibandingkan negara berisiko rendah yang hanya diwajibkan pengumpulan informasi dasar dan menghadapi pengawasan 1%. Akibatnya, pelaku usaha—terutama petani kecil dan UMKM—berpotensi tergencet oleh tuntutan administratif dan teknis yang berat jika tak didukung oleh sistem nasional yang adaptif.
Namun di balik tantangan tersebut, tersimpan peluang. Penempatan Indonesia dalam kategori risiko standar juga bisa dimaknai sebagai bentuk pengakuan atas upaya reformasi sektor kehutanan dan agrikultur, termasuk program Sertifikasi ISPO, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), dan Kebijakan Satu Peta. Bila dikelola dengan baik, Indonesia memiliki kesempatan untuk turun ke kategori Low Risk dalam evaluasi dua tahunan berikutnya. Ini tentu akan meningkatkan daya saing ekspor nasional dan memperkuat reputasi Indonesia dalam pasar global yang makin sensitif terhadap isu keberlanjutan.
Di sisi diplomasi, status ini memberi ruang strategis bagi Indonesia untuk memperjuangkan pengakuan praktik baiknya di panggung internasional. Forum negosiasi seperti IEU-CEPA dan Joint Task Force bersama Malaysia dan Uni Eropa bisa dijadikan sarana untuk menyampaikan keberatan terhadap metodologi klasifikasi risiko EUDR yang dianggap belum sepenuhnya merefleksikan kemajuan nasional.
Baca juga: RI Seeking to Ensure Forest Fires Under Control This Year
Namun demikian, tidak ada jaminan posisi Indonesia akan tetap aman jika tidak ada perbaikan sistemik. Jika data geospasial masih belum akurat, transparansi masih lemah, dan perlindungan terhadap hutan tetap kompromistis, maka bukan tidak mungkin Indonesia naik kelas menjadi negara risiko tinggi. Maka, alih-alih reaktif, Indonesia perlu memanfaatkan momen ini untuk memperkuat fondasi tata kelola komoditas lestari dan menjadikannya sebagai keunggulan diplomatik dan ekonomi.
Maka, untuk menjadikan EUDR sebagai instrumen tata kelola global yang adil dan berkelanjutan, diperlukan konsistensi prinsip di antara kebijakan eksternal dan internal Uni Eropa. Lebih dari sekadar penegakan hukum lintas batas, keberhasilan EUDR akan sangat bergantung pada kesediaan UE untuk membangun kemitraan setara, mengakui konteks lokal negara produsen, dan menjadikan keberlanjutan sebagai proyek kolaboratif, bukan kontrol sepihak. Tanpa refleksi kritis dan reformasi pada arsitektur kebijakan itu sendiri, EUDR berisiko menjadi simbol ambisi ekologis yang tidak selaras dengan kenyataan geopolitik dan keadilan lingkungan global. ***
Oleh: Diah Y. Suradiredja (Pemerhati Perdagangan Berkelanjutan)

