Ecobiz.asia – Tahun 2024 menandai momentum penting bagi Indonesia dalam menghadapi tekanan internasional yang semakin kuat terkait regulasi hijau di tingkat global (Green Global Regulation). Tahun ini juga telah membawa berbagai tantangan dan peluang baru bagi Indonesia dalam menghadapi tekanan regulasi hijau dari pasar global. Sebagai negara berkembang dengan perekonomian yang bergantung pada ekspor komoditas seperti kelapa sawit, batu bara, dan hasil hutan, Indonesia berada di garis depan perdebatan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Berbagai kebijakan hijau yang diterapkan oleh pasar global, seperti European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR). Lebih luas, terkait persyaratan karbon rendah dalam perdagangan, semakin memengaruhi posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Catatan akhir tahun ini mencoba mengeksplorasi dinamika tekanan green global regulation terhadap Indonesia, bagaimana hal ini memengaruhi sektor perdagangan dan pasar domestik, serta langkah-langkah yang telah dan harus diambil untuk menjawab tantangan tersebut. Dalam konteks perdagangan internasional, Indonesia harus menavigasi berbagai kebijakan dan regulasi yang ditujukan untuk mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi. Lalu, bagaimana Indonesia mengeksplorasi tekanan regulasi hijau dan bagaimana negara ini dapat meresponsnya melalui kebijakan perdagangan.
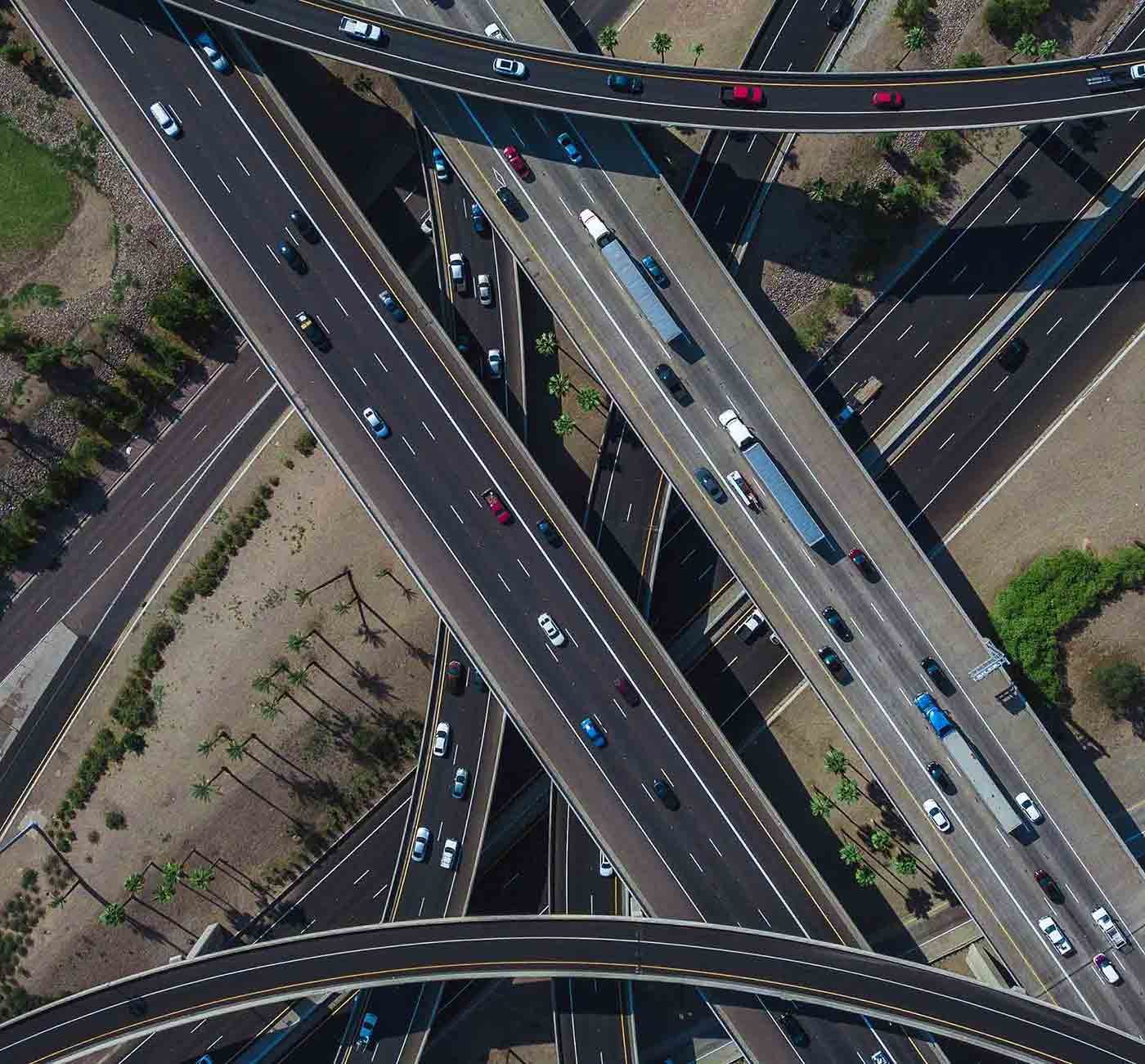
Tekanan Green Global Regulation dalam Perdagangan Internasional
Green Global Regulation adalah serangkaian kebijakan internasional yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dalam perdagangan global. Dua Regulasi yang secara langsung dihadapi oleh Indonesia di penghujung kepemimpinan Jokowi dan terus diestafetkan ke Presiden Prabowo adalah:
1. EUDR (European Union Deforestation-Free Regulation):Regulasi yang mengharuskan komoditas seperti kelapa sawit, karet, dan kakao untuk memenuhi standar bebas deforestasi.
2. Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM):Regulasi yang memberlakukan tarif karbon untuk produk dengan jejak karbon tinggi, seperti baja, aluminium, dan semen.
Indonesia, sebagai salah satu eksportir utama untuk banyak komoditas tersebut, menghadapi tantangan besar. Tekanan EUDR selama tahun 2024 sangat berpengaruh sampai di tingkat petani, dimana regulasi tersebut mengharuskan produk-produk komoditas seperti minyak kelapa sawit dan turunannya untuk memenuhi persyaratan kritis terkait dengan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Selain itu, gugatan dari Uni Eropa terhadap kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia juga menunjukkan bagaimana tekanan regulasi hijau mempengaruhi kebijakan nasional. Meskipun larangan ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon, tapi juga merintangi program hilirisasi sektor nikel yang penting bagi ekonomi nasional.
CBAM merupakan upaya UE untuk mengurangi emisi karbon dan mencapai target net-zero, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan dalam dinamika politik global. UE mengadopsi regulasi ini untuk mendorong pajak pembatasan karbon pertama di dunia untuk barang impor, yang akan diterapkan secara bertahap mulai tahun 2026. Instrumen kebijakan yang dirancang oleh UE ini untuk memastikan bahwa produk impor yang masuk ke UE telah memasukkan biaya emisi karbon yang terkait dengan produksinya. UE tengah mengkaji potensi penerapan mekanisme CBAM di bawah program pasar karbon Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atau carbon offset.
Pada tahap awal, CBAM diterapkan pada komoditas seperti besi, baja, aluminium, semen, pupuk, listrik, dan hidrogen. Komoditas ini dipilih karena memiliki intensitas emisi karbon yang tinggi dan berisiko signifikan terhadap kebocoran karbon. Pada tahap ini importir harus mengukur dan melaporkan emisi karbon yang terkandung dalam produk impor mereka dengan menggunakan metode yang sesuai dengan standar EU ETS. Data harus akurat dan transparan untuk memastikan kepatuhan dengan regulasi.
Baca juga: Bagaimana Indonesia Menghadapi Regulasi Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa
Efforts dan catatan tantangan Indonesia pada Tahun 2024
Kebijakan hijau global memiliki beberapa pengaruh terhadap harga produk di pasar Indonesia. Kebijakan seperti EUDR dapat mempengaruhi ekspor komoditas pertanian Indonesia, seperti minyak kelapa sawit. Dampak ini menjadi salah satu penyebab fluktuasi harga produk berbasis kelapa sawit di pasar domestik dan internasional. Kebijakan tersebut mempengaruhi seluruh rantai pasok perusahaan, baik internal maupun eksternal. Perubahan dalam rantai pasok ini berdampak pada struktur biaya dan akhirnya mempengaruhi harga produk akhir.
Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk menghadapi tekanan regulasi hijau melalui kebijakan perdagangan. Salah satu langkah utama adalah dengan menetapkan positive list produk impor yang memastikan bahwa barang-barang yang diimpor tidak menggantikan produk unggulan dalam negeri. Positive list ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PSME). Permendag ini bertujuan untuk mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melindungi konsumen, serta mendorong perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik.
Pemerintah juga telah menurunkan tarif pada beberapa produk ramah lingkungan dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan ekspor minyak kelapa sawit dan kayu yang lebih berkelanjutan. Kebijakan pemerintah dalam hal pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal serta konsep industri hijau secara bertahap telah meningkatkan daya saing industri. Dukungan pemerintah dalam kebijakan fiskal, non fiskal, serta dengan mendorong industri beralih ke green industri merupakan kunci dalam meningkatkan daya saing industri dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan lapangan kerja di Indonesia. Kebijakan hilirisasi industri ini juga menjadi landasan penting untuk memajukan perekonomian Indonesia dalam melakukan lompatan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara global.
Multiplier effect dari kegiatan hilirisasi industri yang terbukti nyata antara lain meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, menarik investasi masuk dalam negeri, menghasilkan devisa besar dari ekspor, dan meningkatkan jumlah serapan tenaga kerja. Namun, beberapa tantangan saat ini yang perlu mendapat perhatian agar kebijakan hilirisasi industri dapat berjalan dengan baik, antara lain ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, perluasan kerja sama internasional untuk mengisi pasar ekspor baru seperti Eropa dan Afrika, pemberian fasilitas insentif, dan memperkuat keterampilan negosiasi dan posisi di upaya menghadapi tekanan perdagangan dan diplomasi internasional.
Mulai Tahun 2023, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, telah membentuk Dasbor Nasional Informasi dan Data Komoditi Keberlanjutan Indonesia melalui Keputusan Menko Perekonomian (Kepmenko) No. 178/2024 tentang Komite Pengarah Dasbor Nasional Data dan Informasi Komoditi Berkelanjutan Indonesia sebagai respons atas kebijakan ini. Dasbor Nasional ini disiapkan untuk dapat memperbaiki tata kelola komoditas berkelanjutan dan sistem traceability untuk menjawab EUDR. Juga memastikan kepatuhan terhadap EUDR dengan mendorong praktik berkelanjutan di sektor-sektor berisiko tinggi seperti kelapa sawit dan kopi. Bukan saja kesiapan untuk EUDR, Dasbor Nasional dibangun untuk menerapkan sistem pelacakan yang kuat untuk memastikan transparansi dalam rantai pasok dan kepatuhan terhadap standar internasional.
Dalam rangka mempersiapkan diri untuk persyaratan pelaporan CBAM, yakni guna menghindari tarif tambahan pada ekspor ke Uni Eropa, Pemerintah juga mendorong adanya peralihan ke Energi Hijau, yaitu mendorong industri-industri di Indonesia beralih ke energi hijau dan bertransisi ke industri yang lebih bersih untuk mengurangi emisi karbon. Pemerintah memberikan dukungan bagi industri untuk mengadopsi teknologi dan praktik yang lebih bersih dan mengharmonisasikan standar keberlanjutan dalam produksi, pelacakan, dan transparansi karbon yang terkandung dalam rantai pasok.
Pemerintah juga sedang menyelesaikan regulasi pajak karbon untuk selaras dengan persyaratan CBAM. Regulasi ini bertujuan memberikan alternatif bagi bisnis untuk mengurangi emisi karbon dengan membayar pajak karbon atau membeli kredit karbon. Peluncuran IDXCarbon, platform bursa karbon, mendukung pencapaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) Indonesia pada tahun 2030.
Public Private Partnership menjadi platform untuk Indonesia untuk mengurangi dampak potensial dari CBAM pada ekspornya dan memastikan bahwa industrinya tetap kompetitif di pasar global sambil mendorong praktik berkelanjutan. Kemitraan Publik-Swasta dilakukan memlalui pembentukan kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi internasional untuk mendukung inisiatif keberlanjutan dan inovasi di sektor pertanian. Kemitraan ini melibatkan berbagai sektor dalam pengembangan dan implementasi kebijakan untuk menghadapi tantangan CBAM.
Program ini dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto dan standar hidup secara berkelanjutan dan adil, sekaligus mengurangi polusi, membangun infrastruktur yang bersih dan berketahanan, menggunakan sumber daya secara lebih efisien, dan menghargai aset alam yang seringkali tidak dapat diakses. ekonomi, meskipun telah memberikan keberhasilan ekonomi dan kesejahteraan bagi umat manusia selama berabad-abad.
Selain itu, program ini juga berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, investor nasional dan internasional, serta pengembang proyek, sehingga modal hijau bisa mengalir. Saat ini, beberapa UMKM lokal sudah mempraktikkan ekonomi hijau dengan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal. Dengan mendorong praktik ekonomi hijau, hal ini akan membantu pemulihan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja.
Ada beberapa manfaat yang diperoleh UMKM dalam menerapkan konsep Ekonomi Hijau, yaitu sebagai upaya pelestarian lingkungan melalui desain produk yang ramah lingkungan dan dapat menciptakan efisiensi bahan baku, meningkatkan nilai ekonomi produk, dan menangkap pasar. peluang permintaan produk ramah lingkungan. Konsep Ekonomi Hijau diukur dari beberapa indikator yaitu green input, green process, green output, green marketing, dan kebijakan pemerintah.
Meskipun langkah-langkah tersebut menunjukkan kemajuan, masih banyak tantangan yang harus diatasi, (1) Infrastruktur dan Teknologi: Banyak wilayah penghasil komoditas belum memiliki akses teknologi yang memadai untuk mendukung keberlanjutan; (2) Kapasitas Petani Kecil: Sebagian besar petani kecil tidak memiliki pengetahuan atau dana untuk menerapkan praktik berkelanjutan; (3) Harmonisasi Kebijakan: Regulasi domestik seperti ISPO perlu lebih diharmonisasikan dengan standar internasional agar diterima di pasar global.
Baca juga: Hilirisasi Nikel, Indonesia Mau Jadi Pusat Produksi Baterai Hijau untuk Pengendalian Emisi Karbon
Catatan Pinggir melihat Tahun 2025
Catatan akhir tahun ini menegaskan pentingnya aksi kolektif dan kepemimpinan yang visioner dalam menjawab tantangan keberlanjutan yang tidak hanya bersifat lokal tetapi juga global. Di tahun 2024 tercermin tantangan besar bagi Indonesia dalam menghadapi tekanan green global regulation, tantangan dalam bentuk Non-Tariff Measures dapat menambah biaya dan menghambat perdagangan. Pemerintah harus terus meninjau dan memperbaiki kebijakan perdagangan untuk memastikan bahwa Indonesia dapat tetap kompetitif di pasar global sambil memenuhi standar lingkungan yang semakin ketat.
Jika dilihat dari sisi positif, di balik tekanan tersebut terdapat peluang untuk memperkuat daya saing melalui keberlanjutan. Dengan memperkuat kebijakan domestik, mendorong kolaborasi internasional, dan memanfaatkan teknologi, Indonesia dapat menjadikan transisi hijau sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tekanan regulasi hijau dari pasar global menuntut Indonesia untuk lebih proaktif dalam merumuskan kebijakan perdagangan yang dapat mengurangi dampak lingkungan tanpa mengorbankan daya saing ekonomi. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat mengubah tantangan ini menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan hijau dan keberlanjutan ekonomi.
Dengan memperkuat kebijakan domestik, mendorong kolaborasi internasional, dan memanfaatkan teknologi, Indonesia dapat menjadikan transisi hijau sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pajak karbon menjadi sebuah tantangan baru bagi Indonesia dalam menciptakan dan meningkatkan perekonomian tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan. Kebijakan perpajakan yang perlu dibawa adalah pajak dan harga karbon yang berkontribusi untuk mengurangi emisi dan pada saat yang sama menggerakkan sumber finansial untuk perubahan iklim. Ini juga bisa menjadi mekanisme yang efektif untuk dekarbonisasi tanpa membatasi pertumbuhan ekonomi. Perundang-undangan yang belum komprehensif dan masih bersifat overlapping akan menyebabkan pajak karbon bukan memberikan dampak baik bagi Indonesia, tetapi malah sebaliknya
Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) juga dapat mendukung terwujudnya ekonomi hijau di Indonesia. Sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi, Pemerintah perlu menjadi Global Key Player di industri hilir berbasis komoditas. Indonesia berkomitmen untuk mencapai target hilirisasi SDA yang berfokus pada ekonomi hijau dan berbasis lingkungan. Pemerintah telah menetapkan strategi yang mencakup pengembangan industri berbasis SDA dengan teknologi ramah lingkungan, peningkatan efisiensi energi, dan pengurangan emisi karbon. Langkah-langkah ini termasuk implementasi praktik berkelanjutan dalam ekstraksi dan pengolahan SDA, serta pemberian insentif bagi perusahaan yang mengadopsi teknologi hijau. Hilirisasi SDA ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal dan daya saing di pasar global, tetapi juga untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, Indonesia berupaya menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan, sejalan dengan agenda global untuk pembangunan berkelanjutan
Dampak yang sebenarnya dari kebijakan hijau diperkirakan akan baik untuk jangka panjang, jika adopsi teknologi hijau dan praktik berkelanjutan oleh perusahaan. Memang dalam tahap awal, perubahan teknologi ini dapat meningkatkan biaya produksi awal, karena akan menaikkan harga produk, terutama dalam jangka pendek. Namun, produk ramah lingkungan atau “hijau” seringkali memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan produk konvensional. Karakteristik produk hijau dan harganya menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi hijau, terutama di kalangan Generasi Z.
Meskipun adopsi teknologi hijau dapat meningkatkan biaya awal, dalam jangka panjang hal ini dapat memberikan manfaat berupa penurunan dampak lingkungan dan pengurangan limbah berbahaya. Efisiensi ini berpotensi menurunkan biaya operasional dan mungkin dapat menstabilkan atau bahkan menurunkan harga produk. Namun, penting untuk dicatat bahwa pengaruh kebijakan hijau global terhadap harga produk di Indonesia bervariasi tergantung pada sektor industri, jenis produk, dan tingkat adopsi praktik berkelanjutan oleh perusahaan.
Dampak positif yang diharapkan dari kebijakan hilirisasi industri ini juga akan membuka lebih banyak lapangan kerja di Indonesia. Strategi hilirisasi ini meliputi beberapa langkah kunci yang dirancang untuk memastikan bahwa proses pemanfaatan SDA dilakukan secara berkelanjutan dan efisien, serta memberikan nilai tambah yang lebih tinggi bagi perekonomian nasional:
1. Pengembangan Teknologi Hijau, dengan mendorong industri pengolahan SDA untuk menggunakan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menurunkan emisi karbon. Strategi ini memerlukan nnvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seperti teknologi pemurnian yang mengurangi limbah dan emisi.
2. Implementasi Praktik Berkelanjutan, dengan secara tegas melalui intervensi pada perubahan kebijakan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam operasional industri untuk memastikan bahwa seluruh proses dari hulu ke hilir memenuhi standar keberlanjutan internasional. Strategi ini juga dilakukan dengan nendorong industri untuk mendapatkan sertifikasi keberlanjutan seperti ISO 14001 (Manajemen Lingkungan) dan standar internasional lainnya yang diakui global.
3. Penguatan Infrastruktur dan Sistem Logistik, melalui pembangunan kawasan industri yang didesain khusus untuk mengurangi dampak lingkungan, dengan fasilitas yang mendukung praktik produksi bersih dan daur ulang. Strategi ini dilakukan dengan mengembangkan sistem logistik dan rantai pasok yang efisien untuk mengurangi jejak karbon dan meminimalkan pemborosan sumber daya.
4. Insentif Ekonomi dan Fiskal melalui memberikan subsidi dan insentif fiskal untuk perusahaan yang mengadopsi teknologi hijau dan praktik keberlanjutan. Strategi ini dilakukan dengan menawarkan kredit pajak untuk penelitian dan pengembangan di bidang teknologi hijau guna mendorong inovasi dan peningkatan efisiensi.
5. Penguatan Kemitraan dan Kolaborasi Internasional, dengan menjalin kerjasama dengan negara-negara maju dan organisasi internasional untuk transfer teknologi hijau dan praktik terbaik dalam pengolahan SDA. Diperlukan implementasi proyek percontohan yang dapat direplikasi di daerah lain untuk mempercepat adopsi teknologi hijau dan praktik berkelanjutan.
6. Kebijakan dan Regulasi Pendukung, yaitu menerapkan regulasi yang mewajibkan industri untuk menurunkan emisi karbon dan mematuhi standar lingkungan yang ketat. Sehingga diperlukan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas.
Baca juga: Komisi Uni Eropa Usulkan Penundaan EUDR: Banyak yang Belum Siap
Dengan strategi-strategi ini, Indonesia berupaya untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dari SDA sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Hilirisasi SDA yang berkelanjutan tidak hanya meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan.
Untuk mematuhi regulasi seperti EUDR dan persiapan CBAM, produsen di Indonesia harus berinvestasi besar-besaran dalam teknologi rendah karbon, praktik pertanian berkelanjutan, dan transparansi rantai pasok. Beban ini jangan diberikan kepada petani, karena regulasi ini cenderung lebih berat bagi petani kecil yang sudah menghadapi margin keuntungan rendah. Hal yang perlu mendapat perhatian serius adalah Kompetisi Global Negara-negara yang memiliki regulasi domestik lebih ketat dan infrastruktur yang lebih baik, seperti Malaysia atau Brasil. Mereka mulai mengambil alih pangsa pasar Indonesia di sektor-sektor tertentu. Kompetisi ini menekan daya saing Indonesia di pasar internasional.
Lalu bagaimana dengan intervensi China dengan Green China? Bagaimana posisi Indonesia dalam China – ASEAN? Catatan di awal 2025 yang akan “mengintip” peta jalan negara-negara produsen di ASIA. ***
Oleh: Diah Y Suradiredja (Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam & Lingkungan IPB)

