Ecobiz.asia – Pada 15 April 2025, Komisi Eropa menerbitkan dokumen panduan terbaru, Frequently Asked Questions (FAQ) versi 4, serta proposal Delegated Act untuk memperjelas dan menyederhanakan penerapan European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR).
Pembaruan ini tidak hanya menggantikan panduan sebelumnya, tetapi juga menandai upaya strategis Uni Eropa untuk memperbaiki ambiguitas implementasi lapangan, sekaligus mengklaim akan mengurangi beban administratif hingga 30%. Namun bagi Indonesia, sebagai salah satu eksportir utama produk berbasis lahan seperti kelapa sawit, kayu, kopi, dan kakao, perubahan ini membawa konsekuensi strategis yang harus dipahami dengan sangat cermat.
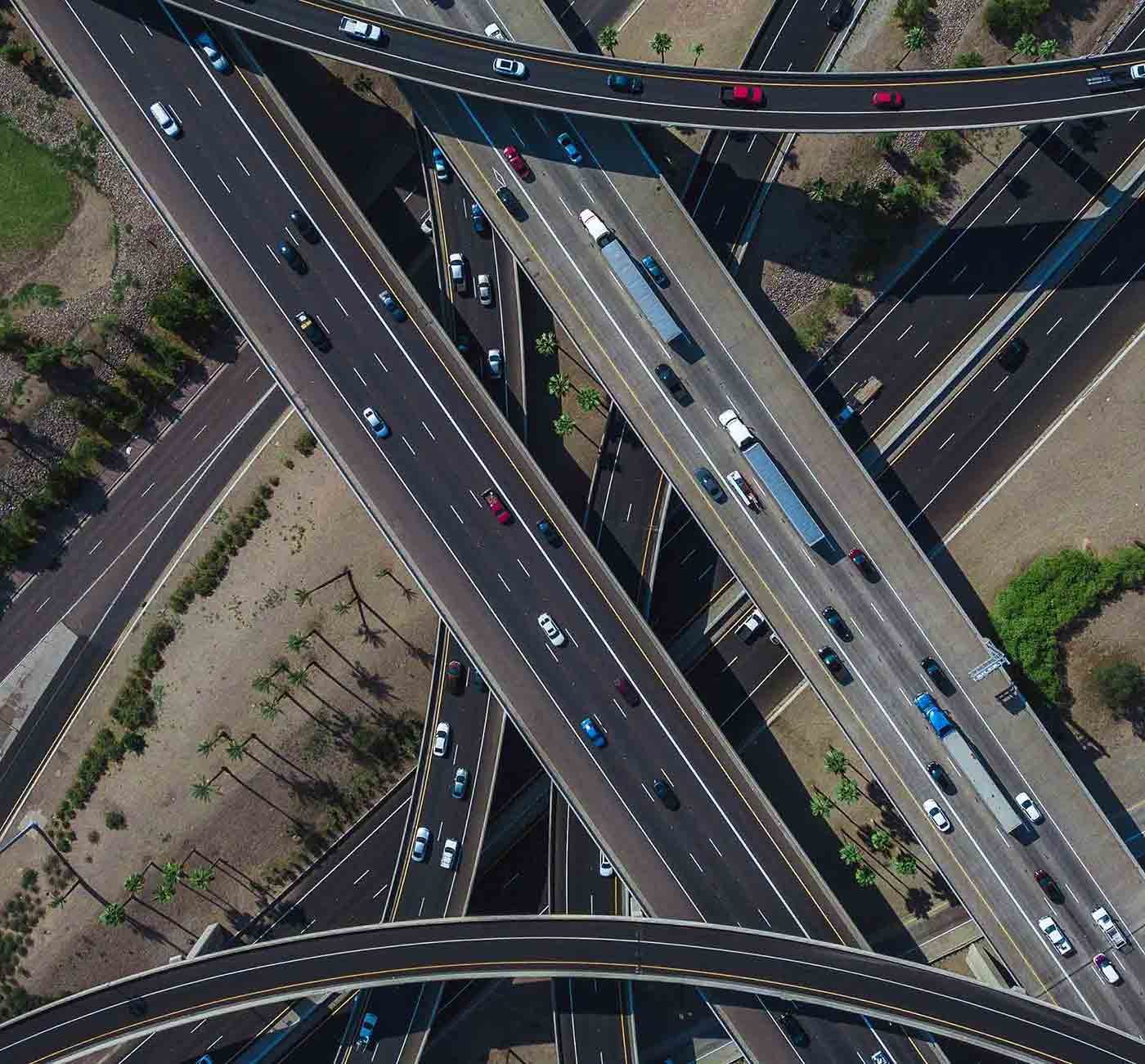
Salah satu aspek yang diklarifikasi adalah definisi aktivitas pasar, khususnya mengenai istilah placing on the market, making available on the market, dan export. Penegasan bahwa kewajiban due diligence hanya diberlakukan saat produk pertama kali ditempatkan di pasar Uni Eropa mempersempit ruang interpretasi yang sebelumnya multitafsir. Dengan demikian, eksportir Indonesia kini memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa sebelum produk dikapalkan, seluruh persyaratan bebas deforestasi, termasuk penyediaan data geolokasi presisi dan dokumentasi legalitas lahan, telah terpenuhi tanpa cela. Dalam konteks ini, setiap kelalaian bukan lagi sekadar kesalahan administratif, melainkan risiko strategis yang dapat berujung pada penolakan akses pasar atau sanksi berat dari Uni Eropa.
Baca juga: Komisi Uni Eropa Usulkan Penundaan EUDR: Banyak yang Belum Siap
Lebih jauh, pembaruan panduan ini memperjelas batas peran antara operator dan trader. Operator—yakni pihak yang menempatkan produk di pasar atau mengekspornya—memiliki tanggung jawab due diligence penuh, mencakup pengumpulan, verifikasi, hingga analisis risiko berbasis bukti. Sementara itu, trader yang sekadar mendistribusikan produk di dalam Uni Eropa memiliki beban kepatuhan yang relatif lebih ringan. Bagi Indonesia, ketentuan ini menjadi panggilan mendesak untuk memperkuat kapasitas eksportir nasional, terutama dalam membangun jejaring kemitraan strategis dengan petani kecil dan koperasi, guna memastikan konsistensi dan integritas data sepanjang rantai pasok. Tanpa konsistensi data dari hulu ke hilir, risiko ketidakpatuhan akan sulit dihindari.
Terkait dengan waktu implementasi, Komisi Eropa memperkenalkan fase transisi yang tampak memberikan sedikit kelonggaran. Perusahaan besar dan menengah diwajibkan untuk patuh sepenuhnya terhadap EUDR paling lambat 30 Desember 2025, sedangkan usaha mikro dan kecil mendapatkan waktu tambahan hingga 30 Juni 2026. Namun, di balik kelonggaran ini tersembunyi tuntutan percepatan transformasi struktural, khususnya bagi sektor perkebunan Indonesia yang masih menghadapi tantangan besar dalam digitalisasi data dan pembangunan sistem traceability berbasis lahan.
Kompleksitas rantai pasok, terutama untuk produk komposit yang mengandung berbagai bahan baku, kini mendapatkan sorotan lebih tajam. EUDR mengharuskan semua bahan, tanpa terkecuali, dapat ditelusuri hingga ke lahan produksinya. Dalam konteks Indonesia—dengan struktur rantai pasok yang tersebar dan fragmentatif—persyaratan ini menjadi tantangan teknis dan administratif yang sangat besar. Tanpa investasi besar dalam sistem pelacakan berbasis teknologi, risiko compliance gap tidak hanya mengancam eksportir besar, tetapi juga berpotensi mengguncang seluruh ekosistem produksi nasional.
Dalam aspek legalitas, Komisi Eropa mempertegas bahwa kepatuhan tidak hanya terkait aspek bebas deforestasi, tetapi juga harus mencakup pemenuhan seluruh ketentuan hukum nasional negara produksi: mulai dari hukum pertanahan, ketenagakerjaan, hingga lingkungan hidup. Panduan terbaru juga menegaskan bahwa sertifikasi pihak ketiga, meskipun dapat membantu dalam penilaian risiko, tidak membebaskan operator dari tanggung jawab utama melakukan verifikasi mandiri. Hal ini menempatkan tekanan tambahan pada eksportir Indonesia untuk tidak hanya mengandalkan sertifikasi eksternal, melainkan membangun due diligence system internal yang kuat dan kredibel.
Pada aspek cakupan produk, panduan memperjelas bahwa hanya bahan kemasan yang menjadi bagian dari produk akhir untuk konsumen yang termasuk dalam ruang lingkup EUDR. Bahan kemasan untuk transportasi, seperti palet kayu, dikecualikan, sementara limbah dan produk daur ulang mendapatkan perlakuan khusus untuk mengurangi beban kepatuhan. Bagi eksportir Indonesia, kejelasan ini membuka peluang untuk optimalisasi manajemen logistik dan penyusunan dokumentasi ekspor yang lebih efisien.
Secara keseluruhan, pembaruan panduan EUDR membawa sinyal tegas: hanya pelaku usaha yang mampu membangun rantai pasok yang transparan, legal, dan berkelanjutan yang akan mampu bertahan dan berkembang di pasar Uni Eropa. Bagi Indonesia, ini bukan semata persoalan administratif, tetapi merupakan momentum krusial untuk mendorong reformasi sektor berbasis lahan ke arah tata kelola yang lebih modern, inklusif, dan kompetitif secara global.
Baca juga: Menteri LH Peringatkan Pengusaha Sawit Jaga Kelestarian Satwa, Dari Gajah hingga Badak
Kewajiban Traceability EUDR: Instrumen Transparansi atau Beban Asimetris bagi Negara Produsen?
Pembaruan FAQ EUDR versi 4 memperjelas salah satu aspek teknis paling fundamental dalam regulasi ini: kewajiban traceability hingga ke tingkat lahan produksi. Secara normatif, ketentuan ini bertujuan memastikan bahwa komoditas yang dipasarkan di Uni Eropa benar-benar bebas dari praktik deforestasi. Dalam setiap due diligence statement (DDS) yang harus dikirimkan ke Information System EUDR sebelum produk dipasarkan atau diekspor, operator wajib melampirkan koordinat geolokasi enam digit desimal—baik dalam bentuk poligon untuk lahan di atas 4 hektare, atau satu titik untuk lahan kecil.
Secara prinsip, pendekatan ini sejalan dengan upaya memperkuat akuntabilitas rantai pasok global. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini mengabaikan kompleksitas sosial-ekonomi negara produsen seperti Indonesia. Walaupun FAQ menegaskan bahwa petani kecil tidak wajib memiliki sertifikat hak milik tanah untuk memenuhi aspek legalitas, beban compliance sepenuhnya dibebankan kepada operator. Konsekuensinya, operator secara rasional akan memilih bertransaksi hanya dengan petani atau koperasi yang mampu membuktikan legalitas dan keterlacakan lahan secara presisi.
Akibatnya, meskipun regulasi tidak secara eksplisit mendiskriminasi petani kecil, dalam praktiknya terjadi compliance bias terhadap aktor-aktor besar atau petani mapan yang memiliki dokumentasi lengkap. Di negara seperti Indonesia, di mana struktur agraria masih didominasi petani kecil dengan status lahan yang tidak sepenuhnya formal, situasi ini dapat mendorong eksklusi sistemik yang semakin melemahkan posisi tawar petani kecil dalam perdagangan internasional.
Kewajiban untuk memverifikasi keakuratan data geolokasi juga menghadirkan beban tambahan bagi operator. Verifikasi ini tidak hanya membutuhkan sumber daya teknis (misalnya teknologi pemetaan, audit lapangan, integrasi data digital), tetapi juga mekanisme pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di hadapan otoritas Uni Eropa. Biaya verifikasi, integrasi data, serta potensi risiko sanksi memperbesar cost of compliance, yang pada akhirnya dapat menggerus margin usaha, khususnya bagi eksportir menengah dari negara berkembang.
Dari perspektif geopolitik, ketentuan ini mencerminkan paradoks besar. Di satu sisi, Uni Eropa mengklaim kepemimpinan dalam agenda pembangunan berkelanjutan global; namun di sisi lain, mereka memperkenalkan standar keberlanjutan yang tidak proporsional memperhitungkan kebutuhan pembangunan kapasitas di negara-negara produsen. Alih-alih menjadi mitra transformatif, EUDR berisiko memperdalam ketergantungan negara produsen terhadap program sertifikasi, sistem teknologi, dan infrastruktur verifikasi berbasis Eropa—yang pada akhirnya memperkuat posisi tawar global Uni Eropa dalam mendefinisikan standar keberlanjutan.
Dengan demikian, meskipun tujuan makro EUDR untuk mengurangi deforestasi global patut diapresiasi, implementasinya berpotensi menciptakan tantangan struktural baru yang memberatkan negara-negara produsen seperti Indonesia. Tanpa upaya serius untuk mengatasi kesenjangan kapasitas ini—melalui skema dukungan teknis, pembiayaan, dan pengakuan terhadap realitas agraria lokal—EUDR berpotensi tidak hanya gagal mencapai tujuan lingkungan yang diharapkan, tetapi juga memperburuk ketidakadilan ekonomi global.
Baca juga: Dukung Kebijakan Biodiesel, Pemerintah Perketat Ekspor POME dan Minyak Jelantah
Kewajiban Mutlak: Patuhi atau Tinggalkan Pasar
FAQ Versi 4 semakin menegaskan pilihan bagi pelaku usaha, dimana opsinya hanya dua, yaitu patuh sepenuhnya terhadap seluruh persyaratan atau menarik diri dari pasar. Salah satu aspek paling penting dalam uji tuntas adalah pengumpulan data geolokasi lahan produksi. Operator wajib mengumpulkan dan mengunggah koordinat lokasi semua lahan yang berkontribusi terhadap produksi komoditas. Apabila data ini tidak tersedia untuk seluruh plot lahan, operator tidak diperkenankan untuk menempatkan produk tersebut di pasar Uni Eropa maupun untuk mengekspornya, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 EUDR.
Jika pemasok hulu tidak mampu atau tidak mau menyediakan informasi yang dibutuhkan, operator juga tidak diperbolehkan meneruskan produk ke pasar Uni Eropa. Dalam logika EUDR, ketidakmampuan untuk memperoleh data yang lengkap dianggap sebagai kegagalan memenuhi uji tuntas, yang berujung pada pelarangan peredaran produk.
Dalam situasi di mana komoditas diproduksi di satu negara (misalnya, negara A), kemudian diolah di negara lain (negara B), dan akhirnya dipasarkan di Uni Eropa (negara C), maka kewajiban pembuktian legalitas tetap mengacu pada negara tempat produksi awal (negara A). Artinya, sekalipun ekspor Indonesia tidak langsung menuju Uni Eropa, namun jika produk tersebut akhirnya memasuki pasar Uni Eropa, Indonesia tetap bertanggung jawab atas pembuktian legalitas dan bebas deforestasi.
Mengenai kemungkinan pembatasan nasional terhadap berbagi data geospasial, EUDR tetap mewajibkan operator untuk mengunggah data geolokasi ke sistem informasi Uni Eropa. Tidak ada pengecualian, meskipun hukum nasional melarang berbagi data. Kegagalan untuk membagikan data berarti kegagalan memenuhi uji tuntas, sehingga produk tidak dapat dipasarkan di Uni Eropa.
Di sinilah muncul dilema struktural besar dalam implementasi EUDR, terutama terhadap prinsip dalam Pasal 3(b) EUDR yang mengharuskan produk diproduksi sesuai hukum negara asal. Dalam praktiknya, hukum Indonesia justru melindungi kerahasiaan data geospasial melalui beberapa regulasi, antara lain:
- • UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang membatasi akses terhadap informasi kekayaan alam nasional.
- • UU No. 4/2011 tentang Informasi Geospasial, yang mensyaratkan izin untuk berbagi turunan data geospasial.
- • UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang memperketat perlindungan terhadap data individu termasuk data lahan.
Dengan demikian, implementasi EUDR di Indonesia menghadapi tantangan besar, yakni bagaimana memenuhi standar Uni Eropa tanpa melanggar peraturan domestik.
Baca juga: Gold Standard Usulkan Joint Labeling Sertifikat Karbon Indonesia, Wamen LH: Sudah Tektokan 10 Kali
Memperluas Jangkauan: Dari Komoditas Utama hingga Produk Turunan dan Kemasan
EUDR tidak hanya mengatur komoditas utama seperti minyak sawit, kopi, kakao, atau karet, tetapi juga memperluas cakupannya ke produk-produk turunan serta kemasan berbahan dasar kayu atau kertas yang menyertai produk hingga ke tangan konsumen akhir. Ada dua jenis kemasan yang dibedakan dalam EUDR:
- • Kemasan Standalone: yaitu kemasan yang menjadi bagian dari produk akhir (seperti kotak parfum atau label anggur). Jenis ini wajib memenuhi uji tuntas karena menjadi bagian dari produk yang dipasok ke konsumen.
- • Kemasan Transportasi: yaitu kemasan yang hanya digunakan untuk pengangkutan (seperti palet kayu atau karton ekspor kopi). Kemasan ini dikecualikan dari kewajiban EUDR karena tidak sampai ke konsumen akhir.
Kunci untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kewajiban uji tuntas ada pada konsep “supply“ atau “pasokan”. Pasokan terjadi apabila ada kesepakatan, baik tertulis maupun lisan, untuk mentransfer kepemilikan atau hak atas produk. Begitu terjadi supply, maka entitas yang terlibat otomatis menjadi operator atau trader di bawah ketentuan EUDR.
- • Pasokan terjadi ketika ada kesepakatan (tertulis atau lisan) antar entitas hukum untuk transfer kepemilikan atau hak atas produk.
- • Importasi ke UE untuk keperluan komersial, bahkan untuk penggunaan internal, otomatis menjadikan perusahaan tersebut sebagai operator dengan kewajiban uji tuntas.
- • Penggunaan internal tanpa pasokan (misal bahan baku untuk konsumsi internal) tidak memicu kewajiban EUDR, kecuali jika produk diimpor ke UE.
- • Logistik murni (seperti jasa pengiriman atau agen bea cukai) tidak dianggap sebagai operator atau trader sepanjang mereka tidak memasok atau mengekspor produk
Contoh berikut memperjelas bagaimana aturan ini diterapkan:
- • Sebuah Perusahaan Otomotif B mengimpor kulit sapi sebagai bahan produksi mobil. Karena ada transfer kepemilikan kulit sapi tersebut, perusahaan ini menjadi operator dan harus melakukan uji tuntas.
- • Sebuah Percetakan P membeli kertas, mencetaknya, dan menjual produk cetakan. Karena ada transaksi pembelian kertas dan penjualan produk, perusahaan ini juga menjadi operator dan berkewajiban melakukan uji tuntas. Namun, jika percetakan ini hanya menawarkan jasa cetak tanpa membeli atau memiliki kertasnya, maka ia tidak dianggap sebagai operator.
- • Sebuah Perusahaan A mengimpor furniture kayu untuk penggunaan internal di kantornya. Meskipun furniture tersebut tidak dijual kembali, hanya digunakan secara internal, karena ada aktivitas importasi ke Uni Eropa untuk keperluan komersial, perusahaan ini tetap wajib memenuhi ketentuan uji tuntas.
Intinya, EUDR memperluas cakupan kewajiban bukan hanya pada eksportir primer, tetapi juga seluruh rantai pasok, bahkan pengguna produk di dalam Uni Eropa, selama ada proses supply atau importasi untuk tujuan selain konsumsi pribadi.
Kompleksitas Subjek Kewajiban dalam EUDR dan Tantangannya bagi Negara Produsen
Pemberlakuan EUDR memperkenalkan seperangkat kewajiban baru yang memperluas cakupan tanggung jawab dalam rantai pasok komoditas, tidak hanya kepada pelaku awal, tetapi juga kepada seluruh aktor hilir yang mengolah dan memperdagangkan produk berbahan dasar komoditas tertentu. Jika ditelaah lebih dalam, struktur kewajiban ini mengandung dinamika kekuasaan yang berpotensi memperdalam ketimpangan antara negara konsumen dan negara produsen, khususnya negara berkembang seperti Indonesia.
Definisi “operator” dalam EUDR dirumuskan secara luas, mencakup tidak hanya perusahaan pengimpor bahan baku primer seperti minyak sawit, melainkan juga perusahaan yang mengolah produk tersebut hingga terjadi perubahan kode HS (Harmonized System). Akibatnya, seluruh aktor dalam rantai pasok, baik di hulu maupun hilir, terikat pada kewajiban melakukan due diligence secara penuh. Dari sudut pandang regulasi, langkah ini memang memperkuat integritas rantai pasok. Namun, bagi negara produsen, tuntutan ini menambah beban administrasi yang berat, khususnya bagi perusahaan kecil dan menengah yang umumnya belum memiliki sistem ketertelusuran yang memadai.
Lebih jauh, Pasal 3 EUDR mengharuskan produk mematuhi semua “relevant legislation of the country of production.” Sekilas, ketentuan ini menunjukkan penghormatan terhadap hukum nasional. Namun, dalam praktiknya, Uni Eropa tetap menjadi pihak yang menentukan akhir sah atau tidaknya sebuah produk, dengan standar legalitas yang diinterpretasikan secara luas mencakup hukum pertanahan, ketenagakerjaan, lingkungan, hingga perpajakan.
Ketentuan ini juga mengabaikan kompleksitas hukum nasional, termasuk ketentuan tentang perlindungan data pribadi atau kedaulatan atas data geospasial, yang dalam beberapa kasus melarang pengungkapan lokasi secara rinci. Dalam FAQ, secara eksplisit ditekankan bahwa operator harus menyediakan data geolokasi, meskipun hukum nasional membatasi akses data tersebut. Hal ini menunjukkan adanya fenomena legal bypass, di mana penghormatan terhadap hukum nasional hanya diakui sejauh sesuai dengan kriteria Uni Eropa, sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai kedaulatan negara produsen dan ketidakadilan struktural dalam sistem perdagangan global.
Hal ini lebih lanjut diikuti oleh kekhawatiran lainnya terkait pihak yang memiliki akses terhadap Sistem Informasi UE. Dalam hal ini, sistem informasi EUDR memungkinkan operator memilih apakah data geolokasi dapat diakses downstream. Meski bertujuan meningkatkan ketelusuran, kondisi ini membuka kerentanan baru. Kebocoran data geospasial—yang mencakup informasi rinci tentang lokasi perkebunan atau hutan— berpotensi disalahgunakan. Bagi negara-negara produsen, hal ini bukan sekadar isu teknis, melainkan soal kedaulatan data dan keamanan nasional. Informasi geospasial yang bocor dapat membuka peluang eksploitasi terhadap sumber daya alam atau memperburuk ketimpangan penguasaan informasi antara negara-negara Global North Global South.
Di sisi lain, beban tambahan dikenakan kepada operator dan trader non-UKM, terutama yang beroperasi di hilir. Mereka diwajibkan mengumpulkan dan memverifikasi informasi rantai pasok melalui sistem informasi yang ditetapkan EUDR, termasuk pengumpulan referensi Due Diligence Statement (DDS) dari seluruh pemasok mereka. Meskipun Komisi Eropa mengklaim bahwa sistem ini mengotomatisasi validasi hingga 2.000 DDS sekaligus, tetap saja tanggung jawab legal tetap berada di pundak operator dan trader tersebut, memperbesar risiko hukum dan administratif dalam praktik bisnis sehari-hari.
SME (small and medium enterprises) memang diberikan beban yang lebih ringan, namun tetap diwajibkan untuk menjaga dan menyerahkan informasi DDS jika diminta otoritas. Tidak hanya itu, baik operator SME maupun non-SME harus segera menghentikan pemasaran produk dan melapor ke otoritas jika menemukan risiko ketidakpatuhan—menciptakan sistem kewaspadaan berlapis yang rawan membebani perusahaan kecil yang kapasitas deteksi dan mitigasi risikonya terbatas.
Satu dimensi geopolitik yang penting untuk dicermati dari pendekatan EUDR ini adalah bagaimana regulasi tersebut, dengan semua kewajiban administratif dan hukum yang kompleks, dapat berfungsi sebagai hambatan teknis baru (non-tariff barrier) terhadap komoditas dari negara berkembang. Dalam jangka panjang, ini dapat mengganggu keseimbangan perdagangan internasional dan memperdalam ketimpangan antara negara produsen dan konsumen. Sementara negara-negara Uni Eropa memperkuat mekanisme pelindung terhadap ekosistem mereka, negara-negara seperti Indonesia dihadapkan pada tuntutan modernisasi sistem produksi dan verifikasi dengan sumber daya yang terbatas. Ketidakadilan struktural ini menuntut adanya dialog internasional yang lebih setara, bukan sekadar pemberlakuan standar secara sepihak.
Kewajiban Due Diligence dalam EUDR: Antara Tuntutan Kepatuhan dan Ketidakadilan Struktural
Penerapan due diligence dalam EUDR memperkenalkan kewajiban multilapis yang menuntut operator (dan trader non-UKM) untuk membangun sistem verifikasi internal yang ketat. Dalam skema ini, terdapat tiga langkah utama: pengumpulan data rinci hingga tingkat koordinat geolokasi, penilaian risiko berbasis kriteria regulasi, dan mitigasi risiko yang harus terdokumentasi.
Sekilas, pendekatan ini tampak rasional dalam upaya mencegah masuknya produk yang berkontribusi pada deforestasi. Namun, jika ditelaah lebih lanjut dapat terlihat bahwa struktur ketentuan ini memiliki dampak geopolitik yang signifikan, khususnya terhadap negara-negara produsen seperti Indonesia.
Pertama, EUDR tidak memberikan pengecualian terhadap operator yang telah memiliki sertifikasi pihak ketiga (misalnya ISPO, RSPO, atau FSC). Artinya, sertifikasi kini diposisikan hanya sebagai bahan bantu dalam risk assessment, tanpa mengurangi kewajiban penuh melakukan due diligence. Ini menggeser beban pembuktian sepenuhnya kepada negara produsen, sekaligus meremehkan standar keberlanjutan yang telah dikembangkan secara lokal.
Secara geopolitik, pendekatan ini mencerminkan bias normatif: standar keberlanjutan dan legalitas yang sah di negara produsen dianggap inferior dibandingkan standar UE. Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang prinsip equity dan common but differentiated responsibilities (CBDR) dalam perdagangan global.
Kedua, persyaratan pengumpulan data geolokasi hingga ke tingkat plot lahan memperlihatkan tuntutan teknis yang berat, terutama bagi produsen kecil di negara berkembang. EUDR Information System sendiri tidak menyediakan alat bantu pemetaan, menyerahkan sepenuhnya kepada operator untuk memperoleh dan mengelola data ini. Bagi Indonesia, yang sebagian besar produksi sawitnya berasal dari petani kecil, ketentuan ini praktis tidak realistis tanpa bantuan teknis dan keuangan eksternal.
Konsekuensinya, terdapat risiko serius terhadap exclusion petani kecil dari rantai pasok global, memperparah kesenjangan sosial-ekonomi domestik, serta menambah ketergantungan pada korporasi besar yang mampu memenuhi beban administratif dan teknis EUDR.
Ketiga, kewajiban mempertahankan dokumentasi selama lima hingga sepuluh tahun mempertegas karakteristik compliance burden dalam regulasi ini. Operator bukan hanya harus melakukan due diligence berulang, tetapi juga membuktikannya setiap saat selama bertahun-tahun. Bagi negara berkembang, ini membebani infrastruktur legal, administratif, dan teknologi yang belum selevel dengan Uni Eropa.
Implikasi besarnya adalah penguatan asymmetrical trade relations, di mana negara berkembang dipaksa untuk beradaptasi terhadap standar negara maju tanpa adanya negosiasi setara mengenai dukungan, transfer teknologi, atau akses pembiayaan transisi.
Keempat, ketentuan tentang tenggat waktu pengajuan Due Diligence Statement (DDS) sebelum pelepasan produk di pasar UE juga menyisakan problem praktis. Pelaku usaha dari negara produsen harus menyelesaikan seluruh tahapan due diligence sebelum proses ekspor selesai, termasuk pendaftaran dalam sistem Economic Operators Registration and Identification (EORI). Ini memperlihatkan bahwa EUDR tidak sekadar standar teknis, tetapi secara de facto menjadi non-tariff barrier yang menghambat akses produk dari negara berkembang ke pasar Eropa.
Kelima, integrasi DDS ke dalam EU Single Window (EU SWE-C) melalui Information System memperkenalkan dimensi kontrol data yang sensitif. Walaupun akses geolokasi dibatasi bagi otoritas yang berwenang dan supply chain members tertentu, tetap ada potensi penyalahgunaan data lahan, yang berisiko memperkuat kontrol informasi dan pengaruh geopolitik negara importir atas komoditas vital negara produsen.
Dari sudut pandang kritis, ketentuan due diligence dalam EUDR tampak mengabaikan realitas pembangunan di negara produsen. Dengan menetapkan standar tinggi tanpa mekanisme dukungan memadai, EUDR berpotensi memperparah ketidakadilan struktural dalam perdagangan global.
Sebaliknya, dari perspektif pragmatis, ketidakpatuhan terhadap EUDR akan menimbulkan risiko besar bagi negara produsen, berupa hilangnya akses pasar, sanksi dagang, dan reputasi buruk dalam rantai pasok global. Karena itu, Indonesia menghadapi dilema strategis: antara berupaya menyesuaikan diri secara progresif sambil memperjuangkan keadilan dalam forum multilateral, atau mencari diversifikasi pasar dan memperkuat posisi tawar terhadap EUDR.
Baca juga: Hutan Rakyat Simpan Karbon Tinggi, Potensial Jadi Solusi Mitigasi Perubahan Iklim
Kesimpulan
Terbitnya Updated Guidance dan FAQ Versi 4 kian menunjukkan arah Implementasi kebijakan EUDR serta memberikan kejelasan pada beberapa aspek yang sebelumnya masih abu-abu. Regulasi ini, meskipun diklaim bertujuan mulia untuk mendorong rantai pasok bebas deforestasi, secara faktual menghadirkan tantangan struktural yang kompleks bagi negara-negara produsen seperti Indonesia. EUDR tidak hanya menggeser beban kepatuhan secara sepihak kepada pelaku usaha di negara asal, tetapi juga menciptakan asimetri baru dalam tata kelola perdagangan global melalui mekanisme hukum dan administratif yang berat sebelah.
Kompleksitas definisi subjek kewajiban, perluasan tanggung jawab aktor di seluruh rantai pasok, tuntutan pengumpulan data geospasial secara rinci, serta ketentuan due diligence multilapis memperlihatkan bagaimana EUDR memperkuat kontrol atas standar keberlanjutan tanpa mempertimbangkan sepenuhnya kapasitas, konteks hukum, dan realitas sosial-ekonomi negara produsen. Di sisi lain, risiko terhadap kedaulatan data, beban administratif yang tidak proporsional, dan potensi eksklusi petani kecil menjadi masalah krusial yang dapat memperdalam ketidakadilan struktural dalam perdagangan komoditas global.
Upaya adaptasi terhadap tuntutan EUDR membutuhkan modernisasi sistem produksi dan verifikasi yang signifikan, namun di saat yang sama, penting untuk terus memperjuangkan prinsip keadilan global melalui dialog multilateral yang lebih setara.
Indonesia, sebagai salah satu negara produsen utama yang terdampak, dihadapkan pada pilihan strategis yang tidak mudah. Upaya adaptasi terhadap tuntutan EUDR membutuhkan modernisasi sistem produksi dan verifikasi yang signifikan, namun di saat yang sama, penting untuk terus memperjuangkan prinsip keadilan global melalui dialog multilateral yang lebih setara. Tanpa adanya mekanisme dukungan yang adil, EUDR berpotensi mengukuhkan ketimpangan dalam tata kelola sumber daya alam dunia, dan menghambat upaya negara-negara berkembang dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif.
Dalam menghadapi dinamika ini, perlu pendekatan yang seimbang: mendorong peningkatan kapasitas domestik untuk memenuhi standar keberlanjutan global, sekaligus memperkuat posisi tawar di forum internasional untuk memastikan bahwa prinsip equity, kedaulatan, dan keadilan struktural tetap menjadi bagian integral dalam diskursus keberlanjutan global di masa depan. ***

