Ecobiz.asia – Mengetahui sejarah komoditas Karet (Karet Rakyat dan Karet Alam) di Indonesia adalah cara untuk memahami bagaimana komoditas ini pernah menjadi bagian penting dari perkembangan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Sejak akhir abad ke-19, karet tumbuh menjadi komoditas unggulan yang mengantarkan Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar di dunia. Tidak hanya menyumbang devisa negara, karet juga menjadi tumpuan hidup bagi jutaan petani kecil di daerah seperti Sumatra dan Kalimantan. Dengan memahami perjalanan karet, mulai dari masa kejayaan, berbagai tantangan yang muncul, hingga upaya modernisasi yang terus dilakukan, kita dapat menemukan pelajaran berharga untuk membangun kembali sektor ini. Sejarah karet mengajarkan kita bahwa komoditas ini bukan sekadar hasil bumi, tetapi juga bagian dari cerita besar Bangsa Indonesia.
Indonesia Pernah Berjaya di Pasar Global
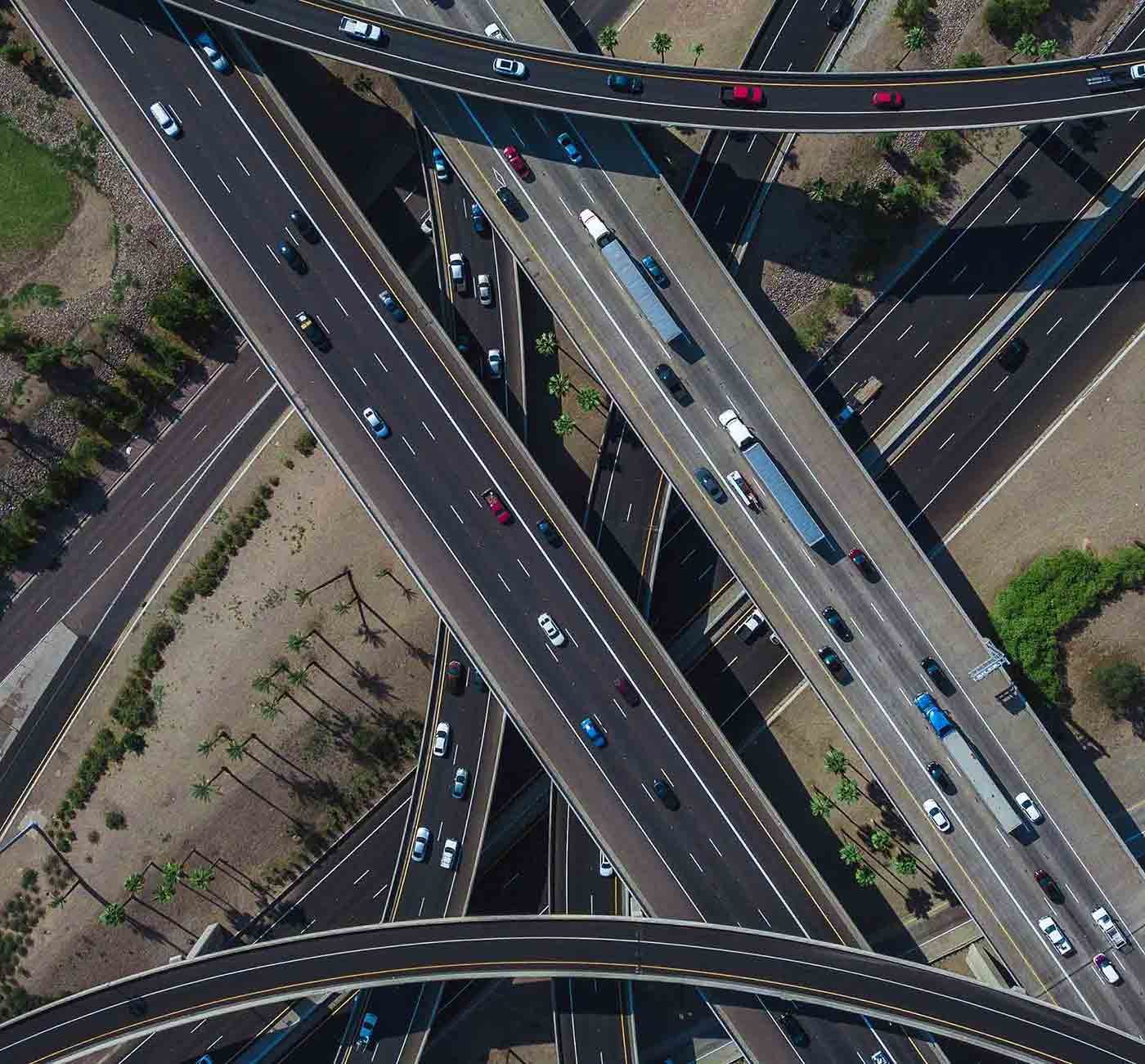
Masa kejayaan karet rakyat di Indonesia, yang berlangsung dari awal 1900-an hingga 1980-an, merupakan periode ketika karet menjadi komoditas utama yang mendukung ekonomi nasional dan kehidupan masyarakat pedesaan. Pada awal abad ke-20, permintaan karet meningkat pesat, didorong oleh perkembangan industri otomotif global yang membutuhkan karet alami untuk produksi ban. Indonesia, dengan Sumatra dan Kalimantan sebagai pusat utama, menjadi salah satu produsen karet terbesar di dunia. Pada era kolonial, perkebunan besar milik Belanda seperti Deli Maatschappij menguasai produksi karet dengan skala industri, dan pada saat yang bersamaan petani kecil mulai menanam karet sebagai sumber pendapatan tambahan. Pada 1920-an, lebih dari 75% produksi karet dunia berasal dari Asia Tenggara, dengan Indonesia sebagai pemain utama.
Sejarah karet mengajarkan kita bahwa komoditas ini bukan sekadar hasil bumi, tetapi juga bagian dari cerita besar Bangsa Indonesia.
Baca juga: Puas dengan Kualitas Kayu Indonesia, Importir Inggris Sepakat Tingkatkan Impor
Setelah Indonesia merdeka, Pemerintah mulai mendorong sektor perkebunan rakyat untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Pada 1950-an hingga 1970-an, karet rakyat berkembang pesat dengan dukungan program replanting (penanaman kembali) dan pembukaan lahan baru oleh pemerintah. Data menunjukkan bahwa pada 1960, luas perkebunan karet rakyat di Indonesia mencapai sekitar 2 juta hektar, menghasilkan lebih dari 1 juta ton karet per tahun. Pemerintah juga memanfaatkan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP), yang kemudian menjadi Perusahaan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN), untuk mengelola perkebunan besar dan mendukung pengembangan karet rakyat. Harga karet pada masa ini cukup stabil di pasar internasional, memberikan penghidupan yang layak bagi jutaan keluarga petani kecil. Pada 1960-an, harga karet dunia cukup stabil, berkisar di antara USD 0,30–0,50 per kilogram (FAO, World Rubber Statistics). Stabilitas ini memberikan pendapatan yang cukup bagi petani kecil, meskipun mereka tetap menghadapi tantangan efisiensi produksi.
Kejayaan ini juga didukung oleh peran petani sebagai aktor utama dalam produksi karet rakyat. Tradisi bertani karet diwariskan secara turun-temurun, dengan metode tradisional seperti penyadapan manual yang dilakukan secara kolektif di tingkat komunitas. Karet menjadi bagian penting dari budaya lokal di wilayah penghasil, seperti di Sumatra Selatan, Jambi, dan Kalimantan. Pada saat itu para tengkulak dan koperasi juga memainkan peran dalam menghubungkan petani dengan pasar. Secara keseluruhan, masa kejayaan karet rakyat ini tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi yang besar, tetapi juga membangun identitas sosial dan budaya masyarakat pedesaan Indonesia sebagai produsen karet alam terbesar di dunia.
Pada tahun 2000an, kunjungan saya ke Kalimantan melihat karet rakyat yang dikelola oleh masyarakat Suku Dayak, dan saat itu masih mendapat cerita tentang masa kejayaan karet mereka. Di Kalimantan, luas perkebunan karet rakyat mencapai lebih dari 700.000 hektar, dengan produktivitas rata-rata sekitar 1,2 ton per hektar per tahun. Pada masa itu, karet menjadi salah satu komoditas utama yang mengangkat perekonomian pedesaan, menyediakan pendapatan stabil bagi ribuan keluarga Suku Dayak. Tradisi pengelolaan karet yang diwariskan turun-temurun memungkinkan masyarakat Suku Dayak memanfaatkan sumber daya alam mereka secara efisien, sambil menjaga keseimbangan lingkungan melalui praktik-praktik berkelanjutan. Masa kejayaan ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu produsen utama karet alam dunia, dengan Kalimantan menjadi salah satu penyumbang penting dalam rantai pasok global.
Outlook Karet 2023, Statistik Karet Indonesia 2022, menuliskan bahwa Indonesia pernah menjadi produsen karet alam terbesar di dunia, terutama pada awal hingga pertengahan abad ke-20. Namun, sejak 1990-an, posisi tersebut diambil alih oleh Thailand. Data dari Outlook Karet 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa pada tahun 2021, pangsa produksi karet alam Thailand mencapai 31,44%, sedangkan Indonesia berada di posisi kedua dengan 21,13%. Produksi karet alam Indonesia mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Menurut publikasi Statistik Karet Indonesia 2022 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), produksi karet Indonesia pada tahun 2021 tercatat sebesar 3,12 juta ton, meningkat 8,2% dibanding tahun sebelumnya. Namun, data dari Industri Karet Alam di Indonesia: Analisis Produksi, Perkebunan menunjukkan bahwa produksi karet alam Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan menurun menjadi 2,24 juta ton.
Baca juga: Hancurnya Komoditas Kelapa di Indonesia: Catatan Sejarah dan Pelajaran Berharga Bagi Komoditas Sawit
Awal Penurunan (1980-an)
Pada 1980-an, industri karet rakyat mulai menghadapi tekanan serius dari pasar global. Salah satu penyebab utamanya adalah overproduksi karet alami di dunia, terutama dari negara-negara pesaing seperti Thailand dan Malaysia, yang memiliki efisiensi produksi lebih baik. Kelebihan pasokan ini menekan harga karet di pasar internasional, sehingga pendapatan petani rakyat di Indonesia mulai menurun. Selain itu, perkembangan teknologi menciptakan karet sintetis berbahan dasar minyak bumi yang lebih murah dan memiliki kualitas tertentu yang mengungguli karet alami dalam beberapa aplikasi industri. Kompetisi ini membuat permintaan terhadap karet alami berkurang, terutama di pasar negara-negara maju. Harga karet dunia pada dekade ini berkisar antara USD 0,80 hingga USD 1,20 per kilogram, yang tidak cukup untuk menutupi biaya produksi bagi banyak petani kecil.
Pada 1990-an, kondisi semakin memburuk dengan munculnya krisis ekonomi Asia pada 1997-1998, yang berdampak besar pada sektor perkebunan di Indonesia. Krisis ini memicu inflasi yang tinggi, melemahnya nilai tukar rupiah, dan berkurangnya investasi di sektor agraris, termasuk karet. Banyak petani menghadapi kenaikan biaya produksi akibat mahalnya harga pupuk dan alat pertanian yang bergantung pada impor. Pada saat yang sama, daya beli masyarakat menurun drastis, sehingga sektor industri yang bergantung pada karet alami pun ikut lesu. Harga karet rakyat di tingkat petani jatuh hingga Rp 1.000-1.500 per kilogram, membuat banyak petani kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Situasi ini memicu migrasi tenaga kerja dari desa ke kota, yang semakin memperburuk kondisi sosial-ekonomi di wilayah pedesaan penghasil karet.
Kondisi Karet Rakyat dan Transformasi Struktur Pasar
Selain dampak ekonomi global dan krisis regional, perubahan struktur pasar domestik juga memperparah kondisi karet rakyat. Petani karet menghadapi rantai distribusi yang panjang dan tidak efisien, sehingga harga yang diterima di tingkat petani jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar internasional. Banyak petani kecil bergantung pada tengkulak yang memberikan harga jauh di bawah standar. Di sisi lain, minimnya dukungan teknologi dan pelatihan dari pemerintah membuat produktivitas kebun karet rakyat stagnan, sehingga mereka tidak mampu bersaing dengan perkebunan besar yang menggunakan teknologi modern. Faktor-faktor ini menandai awal penurunan komoditas karet rakyat yang sebelumnya menjadi salah satu tulang punggung ekonomi pedesaan di Indonesia.
Krisis dan hancurnya karet rakyat pada periode 2000-2015 mencerminkan tantangan besar yang dihadapi sektor ini akibat dinamika pasar global, perubahan struktur ekonomi, dan rendahnya dukungan domestik. Walaupun pada awal 2000-an sebenarnya menunjukkan secercah harapan ketika permintaan global terhadap karet alami meningkat, terutama dari negara-negara berkembang seperti Cina dan India yang mempercepat pembangunan infrastruktur dan industri otomotif.
Harga karet dunia sempat mencapai puncaknya pada 2011, yaitu USD 5,90 per kilogram, didorong oleh tingginya konsumsi global. Namun, di tingkat petani rakyat, keuntungan dari lonjakan harga ini tidak maksimal karena biaya produksi yang tinggi dan panjangnya rantai distribusi dan dominasi tengkulak yang memberikan harga jauh lebih rendah. Petani rakyat kerap menjual hasil panen mereka kepada tengkulak dengan harga jauh di bawah harga pasar. Di beberapa wilayah, petani hanya menerima Rp 10.000-12.000 per kilogram, dan pada 2015, harga karet rakyat di tingkat petani hanya berkisar Rp 5.000-7.000 per kilogram, jauh di bawah harga internasional.
Pada 2012-2015, situasi memburuk ketika harga karet dunia mulai jatuh tajam akibat melimpahnya pasokan karet sintetis dan perlambatan ekonomi global, khususnya di Cina sebagai konsumen terbesar. Harga karet rakyat di tingkat petani turun drastis, berkisar Rp 5.000-7.000 per kilogram, membuat banyak petani kehilangan pendapatan utama mereka. Pelaku besar seperti perusahaan perkebunan besar masih mampu bertahan berkat skala ekonomi dan efisiensi teknologi, tetapi petani kecil yang masih menggunakan metode tradisional kesulitan bersaing. Di sisi lain, biaya produksi terus meningkat akibat kenaikan harga pupuk, alat produksi, dan ongkos kerja, sehingga keuntungan yang diperoleh petani semakin tipis.
Krisis ini tidak hanya berdampak pada ekonomi tetapi juga mengubah dinamika sosial di wilayah penghasil karet. Banyak petani terpaksa beralih ke komoditas lain seperti kelapa sawit, yang dianggap lebih stabil dan menguntungkan, meskipun alih fungsi lahan sering memicu konflik agraria. Generasi muda di desa-desa penghasil karet mulai meninggalkan tradisi bertani karet dan bermigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan lain. Pemerintah mencoba merespons situasi ini dengan program replanting dan diversifikasi produk karet lokal, tetapi dampaknya dirasa lambat dan tidak merata. Krisis ini menandai periode hancurnya sektor karet rakyat yang pernah menjadi andalan ekonomi pedesaan di Indonesia, sekaligus memunculkan tantangan baru dalam menjaga keberlanjutan komoditas ini.
Penurunan produksi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk penurunan luas areal perkebunan karet dan tantangan dalam meningkatkan produktivitas. Meskipun demikian, Indonesia tetap menjadi salah satu produsen karet alam terbesar di dunia, dengan kontribusi signifikan terhadap pasar global.
Hancurnya komoditas karet rakyat tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi yang luas dalam aspek sosial dan budaya. Perubahan yang terjadi pada industri karet telah mengguncang kehidupan petani kecil di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang bergantung pada karet sebagai sumber penghidupan utama.
Baca juga: Kemenperin Dorong Pemanfaatkan Tankos Kelapa Sawit Jadi Produk Biokimia, Bisa Subtitusi Produk Impor
Pada aspek sosial, penurunan industri karet rakyat membawa dampak serius terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan. Petani kecil yang sebelumnya bergantung pada karet sebagai sumber pendapatan utama mengalami penurunan standar hidup. Banyak keluarga petani menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Ketidakstabilan pendapatan juga memicu migrasi tenaga kerja dari daerah pedesaan ke kota, meninggalkan desa-desa penghasil karet dengan populasi yang semakin menurun.
Di beberapa wilayah, penurunan harga karet memicu konflik sosial. Persaingan antar petani untuk mendapatkan pasar dan tekanan ekonomi sering kali menyebabkan ketegangan di tingkat komunitas. Selain itu, muncul fenomena peralihan lahan secara masif. Banyak petani yang menjual atau mengalihfungsikan lahan karet mereka ke tanaman lain yang dianggap lebih menguntungkan, seperti sawit, meskipun hal ini sering kali menimbulkan konflik agraria.
Pada Aspek Budaya, budaya agraris yang telah berakar kuat di masyarakat penghasil karet juga mengalami perubahan signifikan. Di banyak daerah, karet bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Tradisi bertani karet diwariskan dari generasi ke generasi, mencerminkan hubungan erat antara masyarakat dan alam.
Dengan merosotnya harga karet, nilai budaya ini mulai tergerus. Generasi muda semakin enggan melanjutkan tradisi bertani karet karena dianggap tidak lagi memberikan penghidupan yang layak. Mereka cenderung mencari pekerjaan di sektor lain, seperti industri atau jasa di kota. Akibatnya, tradisi dan kearifan lokal yang terkait dengan pengelolaan kebun karet mulai dilupakan. Perubahan ini juga mengakibatkan erosi hubungan sosial dalam komunitas, karena pola kerja kolektif yang sebelumnya umum dalam pengelolaan kebun karet semakin jarang dilakukan.
 Kebun karet
Kebun karet
Pemain dari Hulu sampai hilir
Industri karet alam melibatkan berbagai pemain utama yang berperan dari hulu hingga hilir, mencakup petani, perusahaan besar, pengolah, hingga produsen barang jadi. Di sektor hulu, petani rakyat merupakan aktor dominan, menguasai lebih dari 85% total luas perkebunan karet di Indonesia, yang mencapai sekitar 3,3 juta hektar pada 2021 (BPS). Namun, produktivitas petani rakyat relatif rendah, hanya 1-1,2 ton per hektar per tahun. Di sisi lain, perusahaan perkebunan besar seperti PTPN III dan PTPN IV mengelola sekitar 10% dari luas area dengan produktivitas lebih tinggi, mencapai 1,5-2 ton per hektar. Organisasi seperti GAPKINDO (Gabungan Perusahaan Karet Indonesia) dan IRCo (International Rubber Consortium) juga berperan mendukung petani dan mengoordinasikan ekspor karet.
Pada tahap tengah, pengolahan karet dilakukan oleh perusahaan seperti PT Kirana Megatara, salah satu produsen karet remah terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi lebih dari 800.000 ton per tahun. Perusahaan lain seperti Halcyon Agri Corporation dan Sri Trang Agro-Industry dari Thailand juga berkontribusi dalam pengolahan karet alam Indonesia untuk kebutuhan ekspor. Sebagian besar karet alam Indonesia diproses menjadi Standard Indonesian Rubber (SIR), yang diekspor ke pasar global. Pada 2021, lebih dari 2,5 juta ton karet alam Indonesia diekspor, dengan Cina sebagai pasar utama (41% dari total ekspor), diikuti Amerika Serikat (12%) dan Jepang (9%).
Di sektor hilir, produsen barang jadi internasional memainkan peran penting. Perusahaan seperti Michelin, Bridgestone, dan Goodyear menggunakan karet alam Indonesia untuk memproduksi ban kendaraan. Selain itu, Top Glove Corporation dari Malaysia memimpin produksi sarung tangan medis berbasis lateks, sementara Semperit AG Holding dari Austria memanfaatkan karet alam untuk produk teknis seperti selang dan conveyor belt. Dengan lebih dari 80% karet alam Indonesia diekspor, perusahaan internasional ini menjadi konsumen utama. Dominasi mereka dalam rantai nilai global juga diperkuat oleh peran organisasi seperti GPSNR (Global Platform for Sustainable Natural Rubber), yang bekerja sama dengan perusahaan dan produsen untuk mempromosikan keberlanjutan di seluruh industri. Kombinasi aktor dari hulu hingga hilir ini menunjukkan bahwa keberhasilan industri karet alam Indonesia sangat bergantung pada kolaborasi antara petani lokal, perusahaan pengolah, dan pasar internasional.
Beberapa pemain internasional memiliki peran penting dalam industri karet alam Indonesia, baik di sektor hulu, tengah, maupun hilir. Di sektor hulu, perusahaan seperti Bridgestone Corporation dari Jepang mengoperasikan perkebunan karet di Sumatra dan Kalimantan, memproduksi bahan baku untuk memenuhi kebutuhan internal produksi ban mereka. Michelin Group dari Prancis juga terlibat langsung dalam kemitraan dengan petani karet untuk meningkatkan keberlanjutan produksi, serta berinvestasi dalam alat pelacakan rantai pasok seperti Rubberway. Selain itu, Halcyon Agri Corporation yang berbasis di Singapura, salah satu pemain terbesar dalam perdagangan karet alam, memiliki aset di Indonesia melalui anak perusahaan seperti PT Hok Tong.
Di sektor pengolahan karet, perusahaan seperti Halcyon Agri Corporation memainkan peran kunci dalam memproses karet mentah menjadi karet remah (crumb rubber) yang diekspor ke berbagai negara. Von Bundit Co. Ltd. dan Sri Trang Agro-Industry, keduanya dari Thailand, juga merupakan pemain besar yang aktif di pasar karet global, termasuk mengolah dan mendistribusikan karet dari Indonesia. Produk yang dihasilkan, seperti karet remah dan lateks pekat, digunakan sebagai bahan baku utama dalam industri otomotif, kesehatan, dan barang karet teknis.
Pada sektor hilir, produsen barang jadi seperti Michelin Group, Bridgestone Corporation, dan Goodyear Tire & Rubber Company adalah konsumen utama karet alam dari Indonesia untuk produksi ban otomotif. Sementara itu, Top Glove Corporation dari Malaysia memimpin pasar global dalam produksi sarung tangan medis yang berbasis lateks. Selain itu, perusahaan seperti Semperit AG Holding dari Austria menggunakan karet alam Indonesia untuk memproduksi barang karet teknis, seperti selang dan conveyor belt. Dominasi perusahaan-perusahaan internasional ini juga terlihat di pasar ekspor, dengan Cina, Amerika Serikat, dan Jepang sebagai tujuan utama karet alam Indonesia pada tahun 2021, menyerap lebih dari 60% produksi untuk kebutuhan industri global.
Selain pemain individu, organisasi internasional seperti IRCo dan Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR) berperan dalam mengatur pasokan dan mempromosikan keberlanjutan di industri karet alam. IRCo, yang melibatkan Indonesia, Thailand, dan Malaysia, bekerja untuk menjaga stabilitas harga global, sementara GPSNR mengintegrasikan perusahaan besar seperti Michelin dan Bridgestone untuk meningkatkan praktik keberlanjutan. Kolaborasi pemain internasional ini dengan negara produsen seperti Indonesia sangat penting untuk menjaga pasokan, daya saing, dan keberlanjutan industri karet alam di pasar global.
Baca juga: Menhut Melantik 55 Pejabat Eselon II Kementerian Kehutanan, Berikut Daftarnya
Masih Ada Harapan Pemulihan?
Hancurnya komoditas karet rakyat merupakan isu kompleks yang memerlukan solusi berkelanjutan. Tanpa dukungan yang memadai, banyak petani kecil yang beralih ke komoditas lain atau bahkan meninggalkan sektor perkebunan, yang dapat mengancam keberlanjutan ekonomi pedesaan di Indonesia.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal. Upaya seperti diversifikasi produk, investasi dalam teknologi, dan penguatan pasar domestik harus diiringi dengan perlindungan terhadap nilai sosial dan budaya masyarakat penghasil karet. Hanya dengan cara ini, sektor karet rakyat dapat kembali menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan sekaligus menjaga harmoni sosial dan budaya masyarakat.
Peningkatan produktivitas karet rakyat dapat dilakukan melalui implementasi program replanting dan penerapan teknologi pertanian cerdas. Dalam program replanting, pemerintah dan perusahaan besar seperti PTPN dan Kirana Megatara dapat bekerja sama untuk mempercepat penanaman kembali dengan bibit unggul yang lebih produktif dan tahan terhadap penyakit. Bibit unggul ini memiliki potensi untuk meningkatkan hasil panen petani rakyat dari rata-rata 1-1,2 ton per hektar menjadi 2-3 ton per hektar, sehingga mampu mendongkrak total produksi karet nasional.
Selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti sistem monitoring berbasis satelit, aplikasi pendampingan petani, dan data pelacakan produksi dapat membantu petani mengelola kebun mereka dengan lebih efisien. Teknologi ini tidak hanya memastikan hasil panen sesuai dengan standar pasar internasional, tetapi juga memberikan data akurat untuk mendukung keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan perkebunan. Dengan kombinasi program replanting dan teknologi pertanian cerdas, produktivitas karet rakyat dapat ditingkatkan secara signifikan, mendukung keberlanjutan sektor karet di Indonesia.
Diversifikasi produk dan pengembangan industri hilir menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah karet rakyat sekaligus mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Salah satu langkah utama adalah mendorong investasi dalam industri hilir yang memproduksi barang jadi berbasis karet, seperti ban, sarung tangan medis, alas lantai, dan komponen karet teknis. Pengembangan sektor ini tidak hanya menciptakan nilai tambah, tetapi juga memperluas lapangan kerja di dalam negeri.
Kolaborasi dengan pemain utama seperti Bridgestone, Michelin, dan Gajah Tunggal juga sangat penting untuk memperkuat ekosistem industri hilir di Indonesia. Dengan menggunakan karet rakyat sebagai bahan baku utama, perusahaan-perusahaan besar ini dapat membantu menciptakan pasar domestik yang lebih stabil, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui harga yang lebih kompetitif. Upaya ini akan memberikan dorongan signifikan bagi sektor karet nasional untuk berkembang lebih berkelanjutan dan kompetitif di pasar global.
Peningkatan kesejahteraan petani karet dapat dicapai dengan menciptakan rantai pasok yang lebih adil melalui pemangkasan rantai distribusi dan pemberian dukungan finansial. Salah satu langkah utamanya adalah memperkuat koperasi petani atau menjalin kemitraan dengan perusahaan besar untuk memotong rantai distribusi yang selama ini terlalu panjang. Dengan cara ini, petani dapat menjual karet mereka secara langsung dengan harga yang lebih kompetitif dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Selain itu, pemerintah dapat mendukung petani kecil melalui akses pembiayaan mikro dengan bunga rendah serta subsidi pupuk untuk meringankan beban biaya produksi. Kombinasi dari langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga memberikan kestabilan ekonomi bagi mereka, sehingga mendorong keberlanjutan sektor karet rakyat dalam jangka panjang.
Baca juga: Produksi Kayu Hutan Rakyat, KLHK Dorong Pengaturan Rotasi Panen Demi Keberlanjutan
Peningkatan akses pasar dan keberlanjutan merupakan langkah penting untuk mendukung sektor karet rakyat. Salah satu strategi utamanya adalah memperluas pasar domestik melalui proyek infrastruktur berbasis karet, seperti pembangunan jalan karet yang tahan cuaca. Proyek ini tidak hanya memberikan manfaat jangka panjang dalam infrastruktur, tetapi juga menciptakan permintaan lokal yang lebih stabil untuk karet rakyat, sehingga mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor. Selain itu, keberlanjutan harus menjadi prioritas dengan mendorong petani mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan, seperti agroforestri, yang tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga menjaga ekosistem.
Dukungan dari organisasi seperti GAPKINDO dan GPSNR dapat mempercepat adopsi ini melalui pelatihan dan pendanaan. Sertifikasi keberlanjutan juga menjadi kunci untuk membuka akses ke pasar premium di Eropa dan Amerika Serikat, di mana permintaan terhadap produk yang ramah lingkungan semakin meningkat. Dengan kombinasi langkah-langkah ini, sektor karet rakyat dapat menjadi lebih kompetitif sekaligus berkontribusi pada perlindungan lingkungan.
Keberlanjutan juga harus menjadi prioritas dalam pemulihan industri karet. Praktik-praktik regeneratif seperti agroforestri dapat diterapkan untuk meningkatkan kesehatan tanah dan keanekaragaman hayati, sekaligus menjaga produktivitas kebun karet. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi internasional juga penting untuk menciptakan kebijakan yang mendukung petani kecil, termasuk akses kepada pasar global yang lebih adil. Dengan langkah-langkah ini, industri karet alam dan karet rakyat dapat kembali menjadi sektor yang kuat, berkelanjutan, dan berkontribusi signifikan terhadap ekonomi pedesaan serta nasional. ***
Oleh: Diah Y. Suradiredja (Pemerhati Komoditas Berkelanjutan)

