Ecobiz.asia – Salah satu wacana yang mengemuka dalam debat kebijakan publik saat ini adalah Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah dan ibu hamil. Program ini dirancang sebagai intervensi besar-besaran terhadap masalah stunting yang masih tinggi di Indonesia. Namun, efektivitas program ini sangat bergantung pada bagaimana ia dipadukan dengan rekayasa sosial yang sensitif terhadap konteks lokal dan berakar pada kebutuhan komunitas.
Stunting merupakan salah satu indikator kegagalan pembangunan manusia. Dengan prevalensi tinggi di berbagai wilayah Indonesia, stunting telah menjadi isu prioritas nasional pada era Presiden Joko Widodo. Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Dalam konteks ini, rekayasa sosial menjadi pendekatan yang digunakan untuk mengubah perilaku individu dan kolektif, serta membangun sistem pendukung yang mampu menciptakan lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang anak. Rekayasa sosial tidak sekadar intervensi teknokratis, tetapi merupakan proses menciptakan perubahan sosial secara terencana dan berkelanjutan yang melibatkan relasi kekuasaan, struktur sosial, serta aktor-aktor lokal.
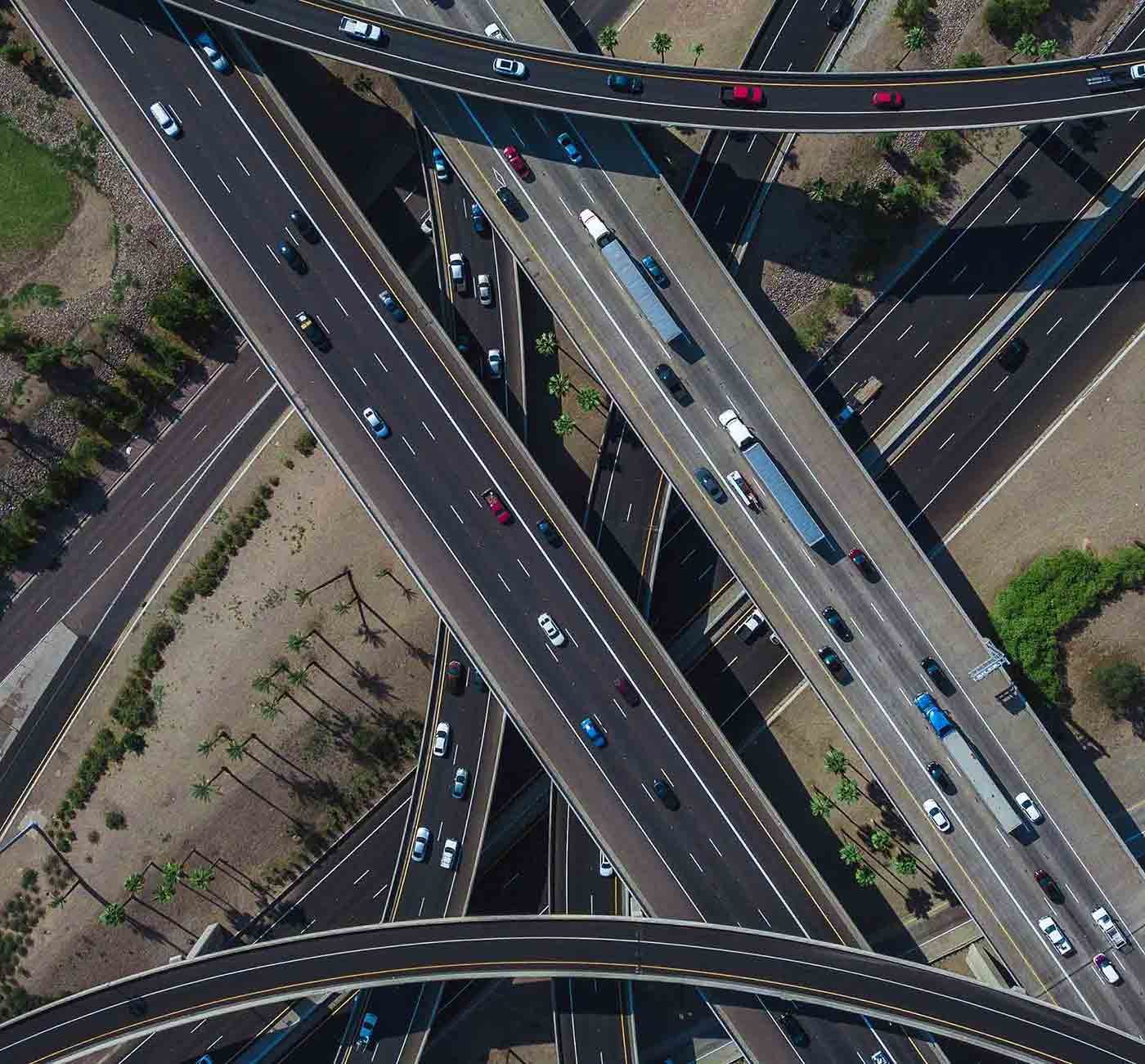
Untuk memahami dinamika rekayasa sosial dalam penanggulangan stunting, penting untuk memetakan terlebih dahulu unsur-unsur utama yang membentuk intervensi sosial ini. Peta rekayasa sosial (social engineering map) mencakup lima komponen utama: (1) aktor pelaksana (pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, tokoh masyarakat, kader kesehatan), (2) sasaran perubahan (ibu hamil, balita, keluarga miskin, komunitas adat), (3) instrumen intervensi (kebijakan publik, kampanye gizi, bantuan pangan, insentif tunai), (4) perubahan yang diharapkan (pola makan sehat, sanitasi layak, pemantauan pertumbuhan anak, kesadaran kolektif), dan (5) lingkungan pendukung (infrastruktur dasar, nilai budaya, sistem informasi gizi). Peta ini membantu menguraikan bagaimana relasi antaraktor dan konteks sosial dapat memperkuat atau justru menghambat efektivitas intervensi stunting berbasis sosial. Selain itu, pendekatan ini mengedepankan strategi jangka panjang yang berpijak pada penguatan komunitas dan pemihakan terhadap kelompok rentan, termasuk ibu hamil dan anak-anak dari keluarga miskin. Stunting merupakan salah satu indikator kegagalan pembangunan manusia.

Stunting sebagai Masalah Struktural dan Sosial
Stunting tidak hanya disebabkan oleh kekurangan gizi semata, melainkan oleh kompleksitas faktor sosial seperti kemiskinan, keterbatasan akses layanan kesehatan, rendahnya pendidikan ibu, dan norma budaya. Sebagai contoh, di Kabupaten Nias Utara, angka stunting masih tinggi karena akses terhadap air bersih dan sanitasi yang buruk, serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya asupan protein hewani. Oleh karena itu, penyelesaiannya membutuhkan intervensi lintas sektor dan perubahan sosial. Kampanye gizi harus mempertimbangkan konteks lokal, bahasa ibu, dan nilai budaya masyarakat setempat. Stunting mencerminkan ketimpangan sosial dan ketidakadilan struktural yang mewujud dalam tubuh anak-anak. Oleh karena itu, setiap strategi penanganannya harus bertumpu pada pemahaman mendalam terhadap determinan sosial yang membentuk kondisi tersebut. Hal ini menuntut penguatan sistem kesehatan masyarakat berbasis komunitas serta kolaborasi lintas lembaga, baik di tingkat desa maupun nasional.
Dalam pendekatan rekayasa sosial, stunting dilihat sebagai dampak dari struktur sosial yang tidak adil dan sistem reproduksi sosial yang mempertahankan kemiskinan antargenerasi. Keluarga miskin dengan akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan akan cenderung melahirkan anak-anak yang mengalami kekurangan gizi, yang kemudian tumbuh menjadi individu dewasa yang juga memiliki keterbatasan akses, melanjutkan siklus ketimpangan. Oleh karena itu, intervensi tidak cukup hanya pada level individu atau keluarga, tetapi harus menyasar transformasi sosial yang bersifat kolektif dan struktural.
Rekayasa sosial dalam konteks ini perlu mencakup reformasi layanan dasar, integrasi kebijakan pembangunan desa, dan penguatan sistem perlindungan sosial. Misalnya, intervensi berbasis keluarga harus dikaitkan dengan kebijakan ketenagakerjaan ibu, peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini, serta jaminan kesehatan yang proaktif. Di sisi lain, penting pula membangun struktur sosial baru yang mendorong perubahan nilai—seperti partisipasi ayah dalam pengasuhan atau pengakuan atas pentingnya protein hewani dalam menu harian keluarga.
Analisis rekayasa sosial juga menyoroti pentingnya penggunaan pendekatan berbasis komunitas untuk mengidentifikasi akar masalah. Dalam banyak kasus, peran kader dan tokoh lokal menjadi krusial dalam menjembatani antara program nasional dan realitas lokal. Kekuatan sosial komunitas dapat diarahkan sebagai modal sosial untuk membentuk norma baru yang mendukung perbaikan gizi dan kesehatan anak. Strategi ini perlu dirancang sedemikian rupa agar tidak hanya memindahkan tanggung jawab ke masyarakat, tetapi justru memperkuat daya dukung struktural mereka.
Dengan demikian, pendekatan terhadap stunting sebagai masalah struktural dan sosial melalui rekayasa sosial mensyaratkan kombinasi antara intervensi teknis dan transformasi relasi sosial yang lebih mendasar. Upaya ini memerlukan kemauan politik, pemihakan terhadap kelompok miskin, serta inovasi sosial yang menjangkau perubahan nilai, perilaku, dan sistem pendukung dalam jangka Panjang.
Stunting tidak hanya disebabkan oleh kekurangan gizi semata, melainkan oleh kompleksitas faktor sosial seperti kemiskinan, keterbatasan akses layanan kesehatan, rendahnya pendidikan ibu, dan norma budaya.
Rekayasa Sosial dalam Kebijakan dan Program Publik
Berbagai program pemerintah seperti Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Program Keluarga Harapan (PKH), dan intervensi spesifik gizi di Posyandu merupakan bentuk rekayasa sosial yang bertujuan untuk mengubah pola asuh, meningkatkan pengetahuan ibu, serta memperbaiki praktik makan dan sanitasi. Di Kabupaten Sumedang, program “Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting” berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan melalui intervensi lintas aktor, termasuk dunia usaha, TNI/Polri, dan tokoh masyarakat yang menjadi pengasuh bagi anak-anak berisiko stunting. Rekayasa sosial melalui program publik ini bukan hanya soal penyediaan layanan, melainkan juga mempengaruhi norma sosial dan persepsi masyarakat terhadap kesehatan, peran orang tua, dan pentingnya investasi pada masa awal kehidupan. Selain itu, kebijakan yang berbasis data mikro dan pelibatan komunitas dalam perencanaan serta pelaksanaan program terbukti lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.
Namun demikian, dalam praktiknya, rekayasa sosial dalam kebijakan dan program publik tidak selalu berlangsung secara ideal. Terdapat pula bentuk-bentuk penyimpangan rekayasa sosial yang menjauh dari prinsip partisipatif dan keadilan sosial. Salah satu contohnya adalah penggunaan data stunting sebagai alat politisasi bantuan sosial. Di beberapa daerah, distribusi intervensi gizi tambahan disalurkan secara diskriminatif kepada kelompok yang dianggap loyal terhadap kepala daerah tertentu, mengabaikan kebutuhan objektif berdasarkan kondisi gizi anak. Hal ini menunjukkan bagaimana rekayasa sosial dapat dimanipulasi sebagai alat legitimasi kekuasaan, bukan untuk menciptakan perubahan sosial yang substansial.
Selain itu, penyimpangan terjadi ketika program penanggulangan stunting direduksi menjadi kegiatan formalistik tanpa makna transformasi sosial. Misalnya, di beberapa kabupaten, pelaksanaan pelatihan gizi atau edukasi parenting hanya menjadi agenda seremonial untuk menyerap anggaran, tanpa ada evaluasi efektivitas atau pelibatan komunitas secara nyata. Rekayasa sosial yang seharusnya menjadi proses pembelajaran kolektif justru berubah menjadi rutinitas administratif tanpa dampak pada perilaku atau kesadaran masyarakat.
Dengan demikian, analisis kritis terhadap rekayasa sosial dalam kebijakan dan program publik perlu dilakukan secara terus-menerus. Pemantauan independen, partisipasi warga dalam perumusan kebijakan, dan transparansi pelaksanaan program adalah pilar penting untuk menjaga agar rekayasa sosial tetap berada pada jalur etis dan transformasional. Penanggulangan stunting hanya akan efektif jika rekayasa sosial benar-benar berpihak pada perubahan struktur sosial yang adil, bukan sekadar melayani kepentingan politik atau agenda jangka pendek para pengambil kebijakan.
Kesenjangan antara Intervensi dan Realitas Sosial
Kesenjangan antara desain dan implementasi program juga tercermin dalam perdebatan awal mengenai rencana implementasi Program MBG. Meskipun secara normatif program ini bertujuan mulia untuk mengatasi masalah gizi pada anak sekolah dan ibu hamil, pelaksanaannya berisiko menimbulkan distorsi jika tidak disesuaikan dengan realitas sosial lokal. Di beberapa wilayah percontohan, terdapat keluhan bahwa makanan yang dibagikan tidak sesuai dengan preferensi budaya setempat, atau malah tidak dikonsumsi oleh anak-anak karena kualitasnya tidak dijaga. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi teknis seperti MBG membutuhkan mekanisme partisipasi yang kuat sejak tahap perencanaan.
Lebih jauh lagi, kasus di beberapa daerah menunjukkan bahwa pengadaan makanan dalam program MBG justru menjadi celah bagi praktik rente dan penguasaan oleh segelintir penyedia jasa tertentu. Di satu sisi, program ini mengalirkan anggaran besar; di sisi lain, tidak ada jaminan bahwa distribusinya adil dan menyasar kelompok yang paling membutuhkan. Situasi ini memperkuat pentingnya rekayasa sosial yang transparan dan berbasis komunitas dalam setiap tahap implementasi. Tanpa akuntabilitas sosial yang kuat, MBG berisiko mengalami kegagalan seperti program-program populis lainnya yang semata menjadi komoditas politik tanpa perubahan struktural yang berarti.
Dari banyak program sudah banyak diluncurkan, tidak sedikit yang tidak efektif karena tidak sesuai dengan kondisi sosial di lapangan. Kader posyandu, misalnya, seringkali kurang mendapat pelatihan berkelanjutan. Di sisi lain, kampanye digital sering tidak menyentuh masyarakat di daerah terpencil karena keterbatasan infrastruktur. Di Papua, banyak kampung tidak memiliki sinyal telekomunikasi, sehingga edukasi berbasis aplikasi menjadi tidak relevan. Ini menunjukkan perlunya rekayasa sosial yang berbasis pada realitas lokal dan pengalaman hidup masyarakat. Ketika intervensi gagal membaca kebutuhan lokal, maka program kehilangan relevansi dan legitimasi sosialnya. Oleh karena itu, pendekatan kontekstual sangat penting untuk menjembatani kebijakan dengan dinamika kehidupan nyata masyarakat. Pembelajaran ini menekankan pentingnya penerapan prinsip keadilan spasial dan sosial dalam penanganan masalah gizi kronis.
Lebih jauh, kesenjangan ini dapat dijelaskan melalui lensa “tragedy of the commons“. Dalam konteks penanggulangan stunting, sumber daya seperti layanan posyandu, bantuan gizi, dan pelatihan kader merupakan sumber daya publik yang semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan kolektif. Namun dalam kenyataannya, sumber daya ini seringkali diklaim atau dikuasai oleh aktor tertentu demi kepentingan terbatas, mengabaikan kepentingan umum. Misalnya, program bantuan makanan tambahan yang hanya diberikan kepada kelompok yang dekat dengan pemangku kepentingan lokal, atau fasilitas posyandu yang difungsikan hanya pada saat kunjungan pejabat untuk pencitraan.
Tragedi ini muncul karena tidak adanya tata kelola sosial yang kuat dalam memastikan distribusi adil dan penggunaan kolektif atas intervensi. Rekayasa sosial yang idealnya menjadi jalan untuk menciptakan tanggung jawab bersama dalam menanggulangi stunting justru berbalik menjadi arena konflik kepentingan. Alih-alih memperkuat solidaritas sosial, intervensi yang tidak sensitif terhadap relasi kuasa dan dinamika lokal justru memperparah ketimpangan. Oleh karena itu, rekayasa sosial perlu dirancang tidak hanya sebagai alat teknokratis, tetapi sebagai proses membangun institusi sosial bersama yang adil, transparan, dan akuntabel.
Untuk menghindari jebakan ini, dibutuhkan mekanisme partisipatif yang menjamin pengawasan sosial terhadap pelaksanaan program. Keterlibatan warga dalam pemantauan distribusi bantuan, pelibatan tokoh lokal dalam verifikasi data, serta ruang dialog antar pemangku kepentingan merupakan strategi penting untuk mengurangi risiko penyalahgunaan sumber daya bersama. Dalam jangka panjang, penguatan etika kolektif dan budaya gotong royong akan menjadi fondasi keberhasilan rekayasa sosial dalam menghadapi tragedi kepentingan sempit dalam penanggulangan stunting.
Baca juga: Kemenhut Kembangkan Agroforestri Tanaman Pangan di 1,1 Juta Hektare, Gandeng Kementan
Ketimpangan Kuasa dan Elitisasi Intervensi
Sebagian besar kebijakan masih bersifat top-down, sehingga program cenderung tidak membumi. Misalnya, aplikasi pemantauan gizi anak berbasis daring jarang digunakan oleh keluarga miskin karena keterbatasan akses internet. Di Kota Kupang, penggunaan aplikasi e-PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) masih terbatas karena rendahnya literasi digital di kalangan kader dan keluarga miskin. Rekayasa sosial harus diarahkan untuk membangun kepercayaan dan dialog antara pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai subjek aktif. Ketimpangan dalam proses perumusan dan pelaksanaan program dapat memperkuat ketidaksetaraan sosial yang menjadi akar dari stunting itu sendiri. Oleh karena itu, demokratisasi proses pengambilan keputusan sangat krusial dalam menjamin keberhasilan intervensi sosial. Pendekatan ini juga mensyaratkan desentralisasi yang bermakna agar daerah memiliki keleluasaan dalam merancang solusi sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayahnya.
Publik melihat adanya ketimpangan dalam wacana dan perumusan Program MBG, yakni bagaimana elit politik mendominasi narasi dan desain kebijakan publik. Dalam banyak kasus, MBG dirancang dan diputuskan secara sentralistik tanpa keterlibatan nyata dari pemerintah daerah atau komunitas penerima manfaat. Hal ini menyebabkan munculnya resistensi diam-diam di lapangan, di mana sekolah atau tenaga kesehatan hanya menjalankan instruksi tanpa memiliki ruang untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal. Relasi kuasa yang timpang ini menunjukkan bahwa MBG, jika tidak dikawal dengan prinsip partisipasi sejajar, hanya akan menjadi simbol kehadiran negara yang top-down.
Analisis ketimpangan kuasa ini dapat diperdalam dengan pendekatan power relation (relasi kuasa), yang menunjukkan bahwa dalam proses intervensi sosial, terdapat distribusi kekuasaan yang tidak merata antara aktor pusat, aktor lokal, dan komunitas sasaran. Relasi kuasa ini menciptakan kondisi di mana masyarakat tidak memiliki ruang deliberatif untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka. Intervensi yang berasal dari pusat kekuasaan sering kali mengabaikan realitas lokal dan menjadikan masyarakat sekadar objek, bukan subjek perubahan. Ketika relasi kuasa ini bersifat hierarkis dan eksklusif, maka rekayasa sosial justru memperkuat dominasi birokrasi atas warga, alih-alih menciptakan pemberdayaan.
Sebagai contoh, dalam sejumlah kasus, keputusan tentang program intervensi stunting diambil sepenuhnya oleh elite teknokratik tanpa konsultasi yang berarti dengan masyarakat lokal. Kader kesehatan di lapangan hanya menjadi pelaksana teknis yang tidak memiliki kewenangan untuk menyesuaikan pendekatan dengan konteks sosial budaya setempat. Hal ini menciptakan keterputusan antara desain program dan kebutuhan nyata komunitas, serta memunculkan resistensi pasif dari masyarakat karena merasa tidak dilibatkan dalam proses perubahan.
Untuk mengatasi hal ini, penting untuk mendorong redistribusi kekuasaan dalam rekayasa sosial, dengan membuka ruang kolaboratif antara aktor negara dan masyarakat sipil. Pelibatan komunitas secara sejajar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program menjadi langkah penting dalam membangun keadilan sosial. Intervensi yang inklusif dan berbasis kesetaraan kuasa tidak hanya meningkatkan legitimasi program, tetapi juga memperkuat keberlanjutan perubahan sosial yang diinginkan.
Baca juga: PGN-BGN Kerja Sama Penyediaan Pasokan Gas Bumi untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Negosiasi Identitas dan Perubahan Nilai Sosial
Upaya penanggulangan stunting juga berhadapan dengan nilai-nilai tradisional, seperti pantangan makanan tertentu bagi ibu hamil atau pembatasan peran ayah dalam pengasuhan. Di beberapa komunitas adat di Kalimantan Barat, masih terdapat larangan mengonsumsi telur dan ikan tertentu selama kehamilan. Oleh karena itu, rekayasa sosial harus melibatkan pendekatan yang sensitif terhadap budaya, serta memfasilitasi negosiasi identitas dan peran dalam rumah tangga melalui pendekatan yang dialogis dan inklusif. Perubahan sosial bukan sekadar menghapus praktik lama, tetapi mengelola transisi nilai dengan menghormati identitas dan sejarah komunitas. Intervensi yang menghargai martabat budaya lokal lebih cenderung diterima dan bertahan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pelibatan pemuka adat, tokoh agama, serta tokoh perempuan lokal menjadi bagian penting dalam memfasilitasi transformasi sosial yang berkelanjutan.
Analisis teori perubahan sosial memberikan kerangka penting dalam memahami dinamika ini. Dalam kerangka struktural-fungsionalisme sebagaimana dijelaskan oleh Talcott Parsons (1951), perubahan sosial sering dilihat sebagai proses adaptif terhadap tekanan eksternal yang memerlukan integrasi agar sistem tetap stabil. Namun dalam konteks stunting, perubahan tidak selalu terjadi secara otomatis, melainkan perlu dipicu oleh intervensi yang disengaja dan terarah—sebagaimana yang dilakukan dalam rekayasa sosial.
Perubahan nilai sosial dalam hal konsumsi makanan, pengasuhan anak, dan peran gender harus difasilitasi secara bertahap dan partisipatif agar tidak menimbulkan resistensi budaya. Dalam konteks ini, pendekatan teori konflik juga relevan sebagaimana diperkenalkan oleh Karl Marx dan diperluas dalam studi kontemporer. Teori ini melihat bahwa nilai-nilai dominan yang dikampanyekan oleh negara seringkali berbenturan dengan nilai lokal yang telah mengakar, menciptakan ruang konflik antara kepentingan negara dan masyarakat (Giddens, 1984).
Pendekatan teori konflik juga relevan ketika melihat bagaimana nilai-nilai dominan yang dikampanyekan oleh negara seringkali berbenturan dengan nilai lokal yang telah mengakar. Dalam hal ini, rekayasa sosial berperan sebagai arena negosiasi antara nilai yang dipaksakan dari atas dengan nilai-nilai yang tumbuh dari bawah. Proses transformasi ini membutuhkan mediasi yang adil, komunikasi dua arah, dan upaya menciptakan ruang deliberatif di mana komunitas dapat mendefinisikan sendiri makna perubahan yang sesuai dengan identitas mereka.
Dengan demikian, rekayasa sosial dalam isu stunting harus didesain tidak sekadar sebagai penyuluhan normatif, melainkan sebagai proses ko-konstruktif antara negara dan masyarakat. Negosiasi nilai dan identitas bukanlah proses linier, tetapi merupakan ruang konflik dan konsensus yang memerlukan pendekatan lintas budaya dan lintas generasi. Ketika perubahan nilai sosial disusun bersama dengan komunitas, maka transformasi yang terjadi lebih autentik, inklusif, dan berkelanjutan.
Baca juga: Dukung Peningkatan Kesehatan Masyarakat, Pertamina EP Bunyu Field Serahkan Bantuan Makanan Bergizi
Partisipasi dan Kepemilikan Program
Lebih lanjut, keberhasilan program sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat. Namun, partisipasi sering kali bersifat seremonial. Di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, program “Gerakan Cegah Stunting” berhasil karena mengaktifkan kembali kelompok dasawisma dan arisan kader yang memiliki jaringan sosial kuat di komunitas. Agar efektif, rekayasa sosial perlu memperkuat kapasitas komunitas, memberikan ruang partisipasi yang bermakna, dan menjadikan masyarakat sebagai agen perubahan. Program berbasis komunitas seperti “Dapur Sehat Atasi Stunting” menunjukkan bahwa ketika masyarakat merasa memiliki program, keberlanjutan menjadi lebih mungkin. Partisipasi yang otentik bukan hanya tentang kehadiran fisik, tetapi keterlibatan dalam perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan yang berujung pada peningkatan efektivitas dan keberlanjutan intervensi. Pendekatan ini juga memperkuat jejaring sosial lokal dan mendorong inovasi komunitas dalam merespon persoalan gizi secara kolektif.
Namun demikian, dalam banyak kasus, partisipasi yang ditampilkan dalam program penanggulangan stunting bersifat semu. Kegiatan musyawarah desa atau forum diskusi publik seringkali hanya menjadi formalitas administratif yang tidak menghasilkan keputusan substantif. Warga diundang hanya untuk menyetujui rancangan program yang sudah disusun oleh pihak eksternal, tanpa ruang untuk menyampaikan kebutuhan riil atau alternatif lokal. Akibatnya, program berjalan tanpa rasa memiliki dari masyarakat, yang pada akhirnya berimplikasi pada rendahnya komitmen dan keberlanjutan.
Ketiadaan kepemilikan terhadap program juga dipengaruhi oleh lemahnya pengakuan terhadap kapasitas lokal. Banyak program stunting yang tidak membangun dari praktik baik komunitas, tetapi justru menggantikannya dengan pendekatan baru yang bersifat top-down. Alih-alih memperkuat apa yang sudah ada, intervensi dari luar sering kali mendeligitimasi inisiatif lokal dan memperlemah kepercayaan diri masyarakat. Dalam konteks ini, rekayasa sosial gagal menjadi alat pemberdayaan, dan justru memperkuat ketergantungan masyarakat terhadap bantuan eksternal.
Untuk membalik situasi ini, diperlukan perubahan paradigma dalam desain intervensi. Partisipasi harus dimaknai sebagai keterlibatan sejajar sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Program perlu memberi ruang bagi inisiatif lokal, mengakui kapasitas pengetahuan masyarakat, dan mendorong praktik berbasis pengalaman. Kepemilikan tidak bisa dibentuk secara instan, melainkan dibangun melalui proses dialog, kepercayaan, dan penghormatan atas peran warga sebagai pemangku kepentingan utama.
Dengan demikian, rekayasa sosial yang berhasil dalam konteks stunting mensyaratkan rekonstruksi hubungan antara negara dan masyarakat, di mana intervensi tidak datang dari luar, tetapi tumbuh dari dalam komunitas itu sendiri. Ketika masyarakat merasa menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar objek kebijakan, maka perubahan sosial yang dihasilkan menjadi lebih tahan lama, kontekstual, dan berakar.
Baca juga: Dukung Peningkatan Kesehatan Masyarakat, Pertamina EP Bunyu Field Serahkan Bantuan Makanan Bergizi
Catatan dari Dapur
Penanggulangan stunting menuntut intervensi sosial yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga partisipatif, kontekstual, dan sensitif budaya. Rekayasa sosial yang efektif perlu melampaui sekadar perubahan perilaku individu, dengan menciptakan transformasi dalam struktur sosial dan relasi kuasa yang mendasari kerentanan gizi.
Dari paparan sebelumnya, terlihat bahwa stunting adalah cermin dari ketidakadilan struktural dan reproduksi ketimpangan sosial antar generasi. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak bisa hanya berbentuk proyek pelayanan jangka pendek, tetapi harus bersifat transformatif, dengan menargetkan perubahan sistemik. Intervensi perlu menyasar pada reformasi layanan dasar, pembentukan norma baru, pengakuan atas kapasitas lokal, serta perubahan nilai sosial dalam keluarga dan komunitas.
Kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas di lapangan mengindikasikan pentingnya memahami konteks sosial dan menghindari jebakan ‘tragedy of the commons‘ dalam pengelolaan sumber daya program. Ketika kepentingan elit mendominasi ruang kebijakan, rekayasa sosial kehilangan kekuatannya sebagai alat perubahan kolektif. Di sinilah pentingnya mengedepankan transparansi, pengawasan sosial, dan distribusi kekuasaan yang setara.
Relasi kuasa yang timpang serta minimnya ruang deliberatif telah menghambat partisipasi bermakna. Analisis power relation menegaskan bahwa tanpa redistribusi kekuasaan, program hanya menjadi alat reproduksi dominasi, bukan sarana pemberdayaan. Hal ini sejalan dengan temuan tentang partisipasi semu dan ketiadaan kepemilikan masyarakat terhadap program, yang berujung pada rendahnya keberlanjutan intervensi.
Transformasi nilai sosial pun menjadi elemen krusial. Perubahan sosial bukan hanya soal mengganti norma lama, melainkan menegosiasikan ulang identitas dan nilai secara kolektif. Pendekatan ko-konstruktif antara negara dan komunitas lokal merupakan jalan menuju perubahan yang autentik dan berkelanjutan.
Dengan demikian, strategi rekayasa sosial untuk menanggulangi stunting harus didasarkan pada prinsip keadilan sosial, penguatan kelembagaan lokal, serta penciptaan sistem sosial yang reflektif, kolaboratif, dan berakar pada kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, Program Makanan Bergizi Gratis hanya akan menjadi solusi jangka panjang apabila ia mampu disinergikan dengan strategi rekayasa sosial yang partisipatif dan adil secara struktural. Tanpa integrasi tersebut, program ini berisiko menjadi intervensi sepihak yang tidak menyentuh akar masalah stunting di Indonesia. ***

