Ecobiz.asia – Kota adalah istilah yang merujuk pada wilayah geografis atau kawasan yang memiliki karakteristik tertentu yang tentunya berbeda dengan wilayah pedesaan. Karakteristik perkotaan umumnya dicirikan dengan kepadatan penduduk yang tinggi, dominasi kegiatan ekonomi non-agraris, infrastruktur yang maju, serta pola hidup masyarakat yang lebih modern dan heterogen. Kegiatan ekonomi utama di perkotaan meliputi sektor industri, perdagangan, jasa, dan teknologi yang tentunya dilengkapi infrastruktur fisik seperti jalan raya, gedung bertingkat, fasilitas kesehatan, dan jaringan transportasi yang pesat. Infrastruktur digital, seperti akses internet dan teknologi komunikasi, juga lebih maju dibandingkan pedesaan.
United Nations (2018), menyatakan bahwa isu permasalahan perkotaan global yang saat ini banyak mempengaruhi kualitas hidup masyarakat adalah: a) Urbanisasi dan populasi, kota-kota hanya dapat menampung 55% populasi dunia saat ini, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 70% pada tahun 2050. Pertumbuhan populasi ini akan menambah tekanan pada infrastruktur, timbulan volume sampah dan layanan kota, b) Kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan masalah kemacetan lalu lintas, kekurangan perumahan, peningkatan permintaan layanan dasar seperti air dan listrik serta jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya; c) Dampak lingkungan seperti emisi Gas Rumah Kaca (GRK), kota-kota bertanggung jawab atas 70% emisi GRK global yang berkontribusi pada perubahan iklim dan polusi udara, limbah: kota-kota menghasilkan 50% dari limbah global seperti: limbah padat, limbah cair, dan limbah bahan berbahaya beracun.
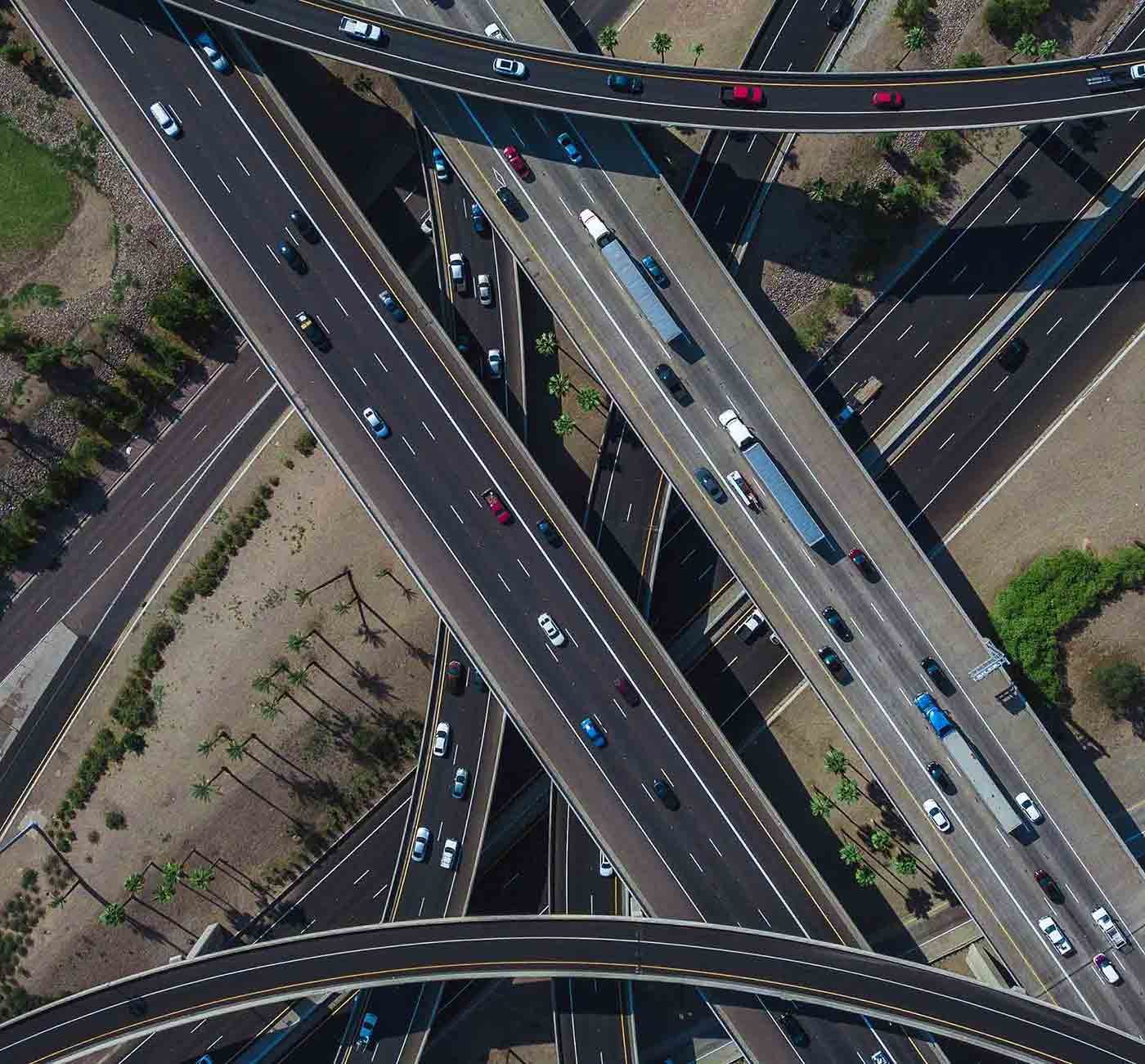
Sampah plastik merupakan salah satu masalah lingkungan yang lagi banyak dihadapi banyak negara didunia saat ini. Dengan meningkatnya produksi dan konsumsi plastik khususnya dalam bentuk kemasan sekali pakai ketika paska konsumsi tidak dikelola dengan bijak akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Setiap tahun, diperkirakan lebih dari 300 juta ton plastik diproduksi secara global, dengan sebagian besar digunakan untuk kemasan sekali pakai. Sebagian besar dari plastik ini akhirnya menjadi sampah dan hanya sebagian kecil yang didaur ulang. Plastik yang tidak terkelola dengan baik sering kali berakhir di lautan, sungai, dan tempat pembuangan sampah yang menyebabkan polusi. Plastik membutuhkan waktu puluhan, ratusan hingga ribuan tahun untuk terurai, sehingga dampaknya terhadap lingkungan bersifat jangka panjang. Mikroplastik, partikel plastik berukuran kurang dari lima milimeter, telah menjadi perhatian global karena dampaknya terhadap lingkungan dan flora fauna dalam rantai makanan. Mikroplastik ditemukan di berbagai ekosistem, termasuk air tawar, laut, dan tanah. Mikroplastik dapat menyerap polutan organik dan logam berat, yang kemudian dilepaskan ke lingkungan dan menyebabkan pencemaran yang lebih luas. Mikroplastik dapat menyebabkan kerusakan fisik, kimia, dan biologis pada organisme laut. Partikel mikroplastik yang kecil dapat terperangkap dalam jaringan organisme atau dimakan oleh biota laut, menyebabkan cedera fisik dan bahkan kematian. Mikroplastik dapat masuk ke rantai makanan manusia melalui konsumsi ikan, kerang, dan produk pangan lainnya yang terkontaminasi. Paparan mikroplastik pada manusia dapat merusak jaringan dan membawa bahan kimia serta mikroorganisme beracun lainnya (Mamun, A. A., et al., 2022).
Pentingnya bagi kita, anak-anak dan keluarga agar dapat memahami pemakaian plastik sekali pakai yang bijak yang harus kita tumbuhkan dalam mindset pola pikir, pola tindakan dan pembiasaan-pembiasaan dalam kehidupan dan beraktivitas kita sehari-hari. Meningkatnya penggunaan plastik tanpa pengelolaan yang bijak pasca konsumsi akan berdampak terhadap lingkungan, kebersihan dan kesehatan yang dapat merugikan kita sendiri, sehingga hal ini menjadi tantangan yang perlu disikapi dengan serius.
Umumnya peningkatan penggunaan plastik dalam kehidupan ini tidak bisa kita pungkiri, karakter plastik yang bersifat ringan, praktis, ekonomis dan dapat menggantikan fungsi dari berbagai barang-barang lain. Sifat praktis dan ekonomis ini menyebabkan plastik sering dijadikan barang sekali pakai, sehingga ini jika dibuang sembarangan ke lingkungan akan berkontribusi terhadap penambahan jumlah sampah plastik yang terus meningkat. Studi bertajuk Plastic Waste Associated with Disease Coral Reefs yang dilakukan Lamb et al. (2018) memaparkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang paling banyak menebarkan sampah plastik ke laut dalam proyeksi waktu antara 2010-2025. Plastik dikategorikan sebagai salah satu hasil signifikan dari kegiatan antropogenik melalui pembuatan, pemanfaatan dan pembuangan plastik. Bahan sintetis ini tersebar luas ke seluruh lingkungan sehingga plastik sekarang dianggap sebagai penanda geologi Antroposen – zaman yang muncul di mana aktivitas manusia memiliki pengaruh yang menentukan suatu keadaan, dinamika, dan masa depan sistem bumi (Zalasiewicz et al. 2016). Plastik juga merupakan salah satu dari lima sektor usaha yang paling berkontribusi pada output manufaktur di Indonesia. Konsumsi plastik di Indonesia juga cukup tinggi sebagaimana tercermin dari nilai impor yang jauh lebih besar dibandingkan nilai ekspor.
Laporan UNEP (2021), total jumlah produksi plastik di seluruh dunia pada tahun 2017 mencapai 438 juta ton. Ironisnya, hanya sekitar 12% dari total plastik yang diproduksi kemudian dibakar dan hanya sekitar 9% didaur ulang. Sisanya berakhir di tempat pembuangan sampah, di TPA atau bocor ke media lingkungan termasuk lautan. Tanpa tindakan yang berarti, maka plastik yang masuk ke dalam ekosistem perairan diperkirakan meningkat menjadi hampir tiga kali lipat, dari yang sebelumnya sekitar 11 juta ton pada tahun 2016 akan menjadi sekitar 29 juta ton pada tahun 2040. Pencemaran plastik telah mengubah habitat dan proses alami, mengurangi kemampuan ekosistem untuk beradaptasi dengan perubahan iklim, yang secara langsung mempengaruhi mata pencaharian jutaan orang, kemampuan produksi pangan, dan kesejahteraan sosial. Bagi negara-negara dengan sistem pengelolaan sampah yang buruk, seperti kantong plastik sekali pakai, dapat ditemukan menyumbat saluran pembuangan sehingga menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk dan hama. Akibatnya adalah penyakit yang ditularkan melalui vektor, seperti malaria turut meningkat.
Pengelolaan sampah termasuk sampah plastik telah diatur melalui beberapa instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Undang-undang ini mengamanatkan perlunya pembentukan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Sebagian besar konsumsi plastik di Indonesia digunakan untuk kemasan, sedangkan penggunaan plastik untuk automotif dan konstruksi relatif rendah. Penggunaan plastik untuk kemasan di Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan penggunaan plastik untuk kemasan secara global (31,26%) (OECD, 2020). Penggunaan plastik untuk kemasan di Indonesia terus meningkat setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai sekitar 4,65% (BPS, 2023). Konsumsi plastik yang besar serta produksi plastik yang terus meningkat berkontribusi terhadap besarnya jumlah timbulan sampah plastik yang dihasilkan. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Kementerian LHK Tahun 2023, komposisi sampah plastik merupakan kontributor terbesar kedua (18,71%) dari jumlah sampah di Indonesia setelah sampah organik/sisa makanan (41,60%). Komposisi sampah plastik meningkat signifikan dari 11% pada 2010 menjadi hampir 18,71% pada 2023.
 Komposisi Prosentase Sampah Plastik dan Prosentase Sampah Berdasarkan Sumber Sampah, (SIPSN-KLHK, 2023)
Komposisi Prosentase Sampah Plastik dan Prosentase Sampah Berdasarkan Sumber Sampah, (SIPSN-KLHK, 2023)
Plastik juga merupakan kontributor emisi gas rumah kaca. Dimana sekitar 98 persen produk plastik sekali pakai dihasilkan dari bahan bakar fosil. Tingkat emisi gas rumah kaca yang terkait dengan produksi, penggunaan, dan pembuangan plastik berbasis bahan bakar fosil konvensional diperkirakan akan tumbuh hingga 19 persen dari anggaran karbon global pada tahun 2040. Sampah plastik telah menyebar mencemari sumber-sumber air, seperti sungai dan danau. Secara global, tak kurang dari 1.000 sungai menjadi penampungan sampah plastik, dan menjadi penyumbang utama pencemaran lautan (UNEP, 2021).
Tantangan Menuju Global Plastic Treaty untuk Mengakhiri Polusi Sampah Plastik
Indonesia bersama negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat ini sedang aktif berpartisipasi dalam International Negotiating Committee (INC) untuk mengakhiri dan menyelesaikan permasalahan pencemaran sampah plastik termasuk di laut melalui pengembangan perjanjian yang mengikat secara hukum. Memperhatikan bahwa tingkat polusi plastik yang tinggi dan meningkat pesat merupakan masalah lingkungan yang serius dalam skala global, yang akan berdampak negatif terhadap dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam kerangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. United Nations Environment Programme (UNEP) menyatakan jumlah sampah plastik yang masuk ke ekosistem akuatik dapat meningkat hampir menjadi tiga kali lipat pada tahun 2040 apabila tidak ada upaya-upaya pencegahan dan pengendalian. Jumlah polusi sampah plastik sekitar 9-14 juta ton pada 2016 berpotensi menjadi 23-27 juta ton pada 2040. Ancaman polusi sampah plastik tersebut menjadi perhatian global dengan disepakatinya United Nations Environment Assembly (UNEA) Resolution 5/14 End plastic pollution: Towards International Legally Binding Instrument. Resolusi 5/14 UNEP ini memberi mandat untuk melaksanakan INC yang saat ini sudah mencapai putaran ke-5 yang dihadiri oleh para delegasi petinggi pemerintahan di berbagai negara di dunia. Putaran ke-5 (INC-5) sedang berlangsung di Busan, Korea Selatan, dari tanggal 25 November hingga 1 Desember 2024, guna menyusun international legally binding instrument (ILBI) on plastic pollution dalam menyiapkan suatu ratifikasi konvensi baru kedepannya.
Resolusi tersebut juga membahas siklus hidup plastik secara keseluruhan, termasuk produksi, desain, dan pembuangannya. Produksi dan pencemaran sampah plastik berkontribusi terhadap tiga penyebab krisis bumi (triple planetary crisis), yaitu perubahan iklim, kerusakan alam dan pencemaran, yang disebabkan: (1) Paparan plastik yang membahayakan kesehatan manusia, berpotensi mempengaruhi kesuburan, hormonal, metabolisme dan aktivitas neurologis, dan pembakaran plastik secara terbuka berkontribusi terhadap pencemaran udara, (2) Perkiraan yang kemungkinan akan terjadi pada tahun 2050, emisi gas rumah kaca yang terkait dengan produksi, penggunaan, dan pembuangan plastik akan mencapai 15 persen dari emisi yang diizinkan, dengan tujuan membatasi pemanasan global hingga 1,5°C (34,7°F). Resolusi sampah plastik juga menekankan perlunya langkah tranformasi menuju ekonomi sirkular, yang diyakini dapat mengurangi volume sampah plastik yang memasuki lautan hingga lebih dari 80 persen pada tahun 2040; mengurangi produksi plastik murni sebesar 55 persen; menghemat US$70 miliar pemerintah pada tahun 2040; mengurangi emisi GRK sebesar 25 persen; dan menciptakan 700.000 pekerjaan tambahan, terutama di belahan bumi selatan.
Baca juga: Tingkatkan Daya Saing Industri Kehutanan, KLHK Bedah Kinerja PBPHH di Kalimantan Tengah
Resolusi plastik ini sesungguhnya selaras dengan langkah Indonesia untuk mengatasi permasalahan sampah plastik. Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut dengan tujuan untuk dapat mengurangi 70% sampah plastik di laut pada tahun 2025. UNEP telah menekankan, bahwa Pemerintah adalah aktor kunci dalam permasalahan plastik, karena berwenang menetapkan aturan main untuk semua pemangku kepentingan. UNEP memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah di berbagai negara dalam rangka mengatasi permasalahan polusi plastik, antara lain:
- Pemerintah dapat mulai menghilangkan produk plastik yang tidak dibutuhkan dan menjadi sumber permasalahan, misalnya melalui larangan atau pengurangan penggunaan plastik sekali pakai yang diikuti dengan langkah promosi untuk alternatif yang lebih berkelanjutan, seperti alternatif plastik yang dapat digunakan kembali atau lebih ramah lingkungan;
- Mempromosikan inovasi sehingga plastik yang kita butuhkan dirancang dan dibawa ke dalam perekonomian dengan cara yang memungkinkan peredarannya. Ini termasuk memungkinkan sistem penggunaan kembali sebagai norma daripada pengecualian. Di beberapa negara, skema penggunaan kembali terhambat karena wadah kosong dianggap sampah, dan oleh karena itu perlu penanganan khusus;
- Mulai mengimplementasikan konsep Extended Producer Responsibility(EPR) untuk memastikan insentif yang tepat diberikan agar plastik dan bahan lainnya tetap ekonomis. Industri atau produsen dapat didorong agar menghilangkan kemasan atau produk plastik yang bermasalah atau tidak perlu dengan mendesain ulang produk untuk meningkatkan keberlanjutan dan menginovasi model bisnis mereka untuk beralih dari produk plastik sekali pakai ke produk plastik yang dapat digunakan kembali. Perusahaan harus memberikan informasi keberlanjutan yang andal dan transparan sehingga konsumen dapat melakukan pembelian berdasarkan informasi. Perusahaan juga dapat meningkatkan penggunaan konten daur ulang dalam produk baru untuk mengedarkan plastik dalam perekonomian;
- Pemerintah perlu memastikan agar sampah plastik dapat di daur ulang dan di guna ulang serta dipergunakan selama mungkin. Ini membutuhkan infrastruktur pengumpulan sampah dan daur ulang material yang diperlukan, serta mekanisme pembiayaan yang memastikan keberlanjutannya.
- Pentingnya instrumen insentif kepada produk terbaik secara ekonomi dan lingkungan, seperti opsi yang dapat dipergunakan kembali atau di daur ulang. Harapannya adalah sektor industri mulai berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur pengumpulan dan pemilahan untuk meningkatkan tingkat pengumpulan dan daur ulang sampah plastik. Industri dan Produsen (Hotel, Restoran, Café/HORECA) juga dapat didorong untuk memastikan tanggung jawab dalam upaya pengumpulan dan pemrosesan kemasan/produk plastik setelah digunakan.
- Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan kampanye kesadaran publik, dan mendorong perubahan perilaku dengan menawarkan insentif untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, sebaliknya juga memberlakukan disinsentif atau pungutan bagi yang tidak melakukannya.
Penutup
Untuk menyongsong Global Plastic Treaty dan mengatasi polusi sampah plastik secara efektif, diperlukan sinergi dan kolaborasi multi pihak dari hulu ke hilir.
1. Pendekatan Holistik dan Kolaboratif
- Kolaborasi Nona Helix: Melibatkan seluruh pemangku kepentingan di sepanjang rantai nilai plastik, termasuk pelaku usaha, pemerintah, akademisi, pemuka agama, pemuka masyarakat, media, dan masyarakat dilengkapi dukungan modal sosial.
- Pendekatan Komprehensif: Mengintegrasikan upaya dari berbagai sektor pemerintah maupun pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap tahap dalam siklus hidup plastik dikelola dengan baik.
2. Kebijakan dan Regulasi yang Mengikat
- Perjanjian Plastik Global: Menerapkan perjanjian yang mengikat secara hukum dan mencakup siklus hidup produk plastik sebagai peluang terbaik untuk mengatasi polusi plastik.
- Extended Producer Responsibility (EPR) (PerMenLHK P.75 Tahun 2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen). Memperluas tanggung jawab produsen untuk mengelola limbah plastik yang dihasilkan dari produk mereka. Adopsi konsep EPR di Indonesia telah dimuat dalam UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Pasal 15), menyatakan bahwa produsen bertanggung jawab atas pembuangan kemasan dan produk yang tidak dapat dikomposkan atau sulit untuk dijadikan kompos. Melalui PP 81/2012, (Pasal 1, angka 5), Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Bentuk pengaturan tanggung jawab Produsen secara konkrit sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut adalah produsen wajib membatasi timbulan sampah, mendaur ulang sampah dan melalui penarikan kembali (take-back), serta memanfaatkan kembali sampah. Peraturan tersebut juga mewajibkan produsen sektor bidang usaha manufaktur pemegang merek, bidang usaha ritel, dan bidang usaha jasa makanan dan minuman untuk mengurangi sampah yang berasal dari produk dan kemasan produk yang mereka hasilkan dan pasarkan dengan cara 3R. Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen ini disusun untuk waktu 10 tahun dimulai sejak 2020 sampai dengan 2029 dengan target pengurangan sampah barang dan kemasan barang serta wadah berbahan plastik, kertas, kaca, dan aluminium sebesar 30% dari jumlah produk dan/atau kemasan produk yang dihasilkan dan dipasarkan di tahun 2029.
- Bank sampah (PerMenLHK No. 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah) memainkan peran penting dalam menerapkan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan edukasi penyadaran dalam komunitas berbasis masyarakat untuk mengatasi polusi sampah plastik dan mendukung tujuan Global Plastic Treaty.
- Mendorong Pemerintah Daerah dalam penerbitan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pembatasan dan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai (single use plastic).
- Mengembangkan instrumen standarisasi pengelolaan sampah kemasan dan sertifikasi Ekolabel nasional.
3. Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi
- Pengembangan Infrastruktur Daur Ulang: Meningkatkan fasilitas daur ulang dan teknologi pengolahan limbah untuk mengurangi kebocoran plastik ke lingkungan.
- Pemanfaatan teknologi berbasis Internet of Things (IoT) dan Kecerdasan Buatan (AI) menawarkan solusi inovatif untuk mendeteksi dan mengelola limbah plastik secara lebih efisien.
4. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat
- Kampanye Kesadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak polusi plastik dan pentingnya pengelolaan sampah yang baik.
- Edukasi di Tingkat Komunitas: Melibatkan masyarakat dalam program edukasi dan pemberdayaan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan meningkatkan partisipasi dalam program daur ulang.
5. Kolaborasi dengan Sektor Swasta
- Kemitraan dengan Perusahaan: Mendorong perusahaan untuk terlibat aktif dalam upaya pengurangan sampah plastik melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan inisiatif keberlanjutan serta skema pembiayaan dalam pengembangan infrastruktur daur ulang dan pemanfaatan sampah plastik;
- Inovasi Produk: Mengembangkan produk yang lebih ramah lingkungan dan mudah didaur ulang
6. Mengembangkan sistem monitoring, evaluasi dan pengawasan termasuk kebijakan penerapan insentif dan dis-insentif;
7. Penerapan praktek sirkular ekonomi dengan target semua lini termasuk optimalisasi mekanisme kemitraan dalam penarikan kembali (take-back) sampah kemasan produsen pasca konsumsi dengan Bank Sampah, TPST3R, Pusat Daur Ulang, Start-up platform digital, dan lainnya. ***

