Ecobiz.asia – Saat ini, Indonesia sebagai Negara Produsen sedang mendapat tekanan oleh regulasi Negara Tujuan Ekspor terkait dengan persyaratan free-deforestration atau Green Regulation untuk semua komoditi yang berasal dari hutan dan perkebunan. Artikel ini agar bisa memahami sejarah jelas rujukan masing masing negara di dunia dalam menetapkan regulasi hijau mereka, serta dapat melihat kesepakatan negara negara di dunia terkait dengan hal tersebut.
Konferensi Stockholm pada tahun 1972
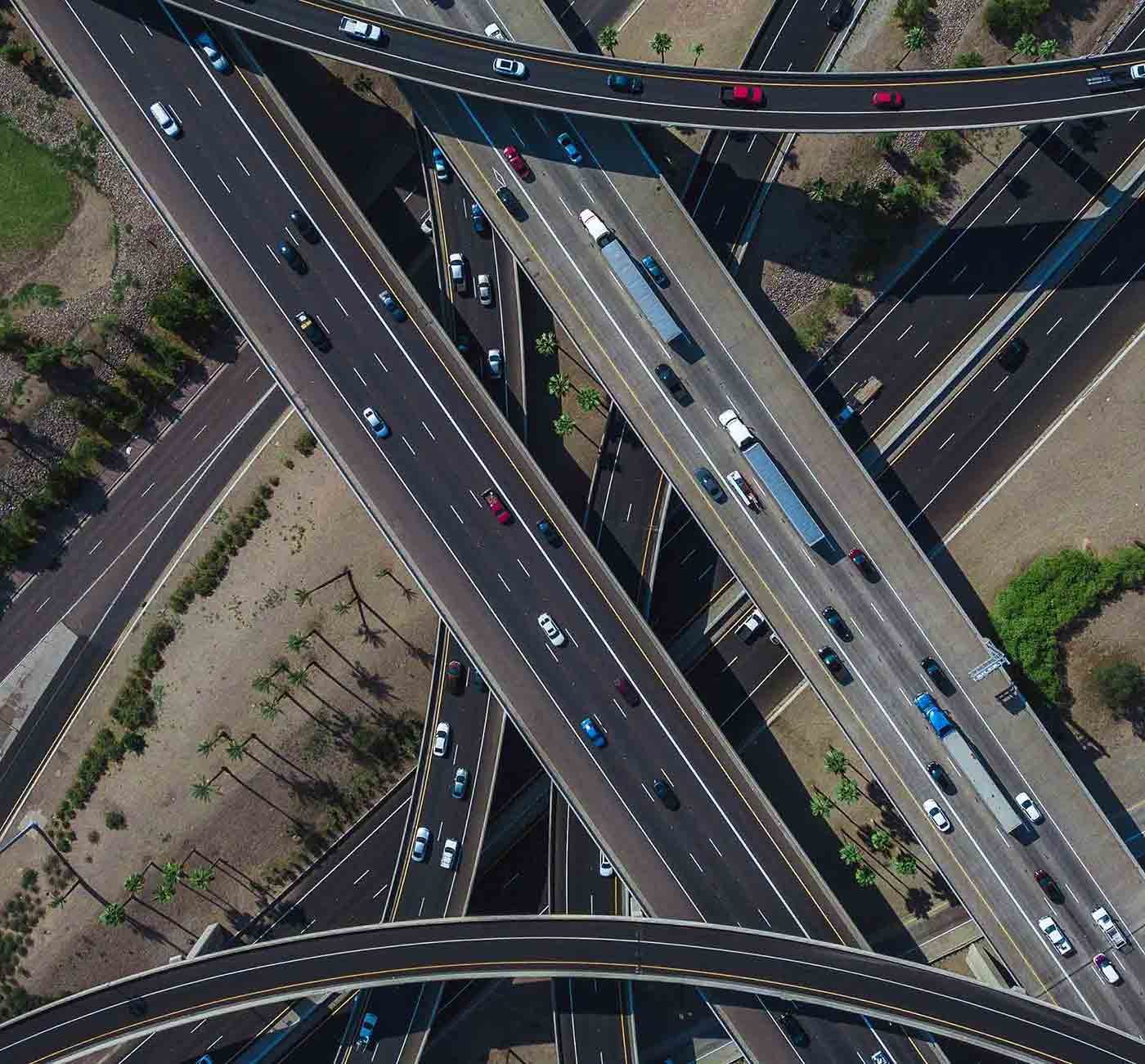
Perkembangan regulasi global yang berfokus pada lingkungan ditandai sejak berlangsungnya UN Conference on the Human Environment, atau biasa disebut Konferensi Stockholm pada tahun 1972, yang merupakan konferensi tingkat dunia pertama dengan isu lingkungan hidup sebagai fokus utamanya. Dihadiri perwakilan dari 114 negara dan beberapa organisasi internasional, salah satu pencapaian besar konferensi ini adalah didirikannya United Nations Environment Programme (UNEP) sebagai Lembaga Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) yang bertujuan untuk mengatasi berbagai ancaman terhadap lingkungan hidup.
Selain itu, Konferensi Stockholm juga menghasilkan tiga keputusan utama. Pertama, Deklarasi Stockholm yang berisi 26 prinsip untuk pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik. Kedua, Rencana Aksi Stockholm yang berisi 109 rekomendasi untuk pemerintah dan organisasi internasional mengenai langkah-langkah internasional untuk mengatasi degradasi lingkungan. Ketiga, lima resolusi yang terdiri dari seruan untuk pelarangan uji coba senjata nuklir yang dapat menyebabkan dampak radioaktif, bank data internasional tentang data lingkungan, kebutuhan untuk menangani tindakan yang terkait dengan pembangunan dan lingkungan, perubahan organisasi internasional, dan pembentukan dana lingkungan.
Pengadopsian Deklarasi Stockholm lah yang kemudian menjadi awal ditempatkannya isu lingkungan hidup sebagai perhatian dunia internasional, serta dimulainya pembahasan antar negara maju dan negara berkembang mengenai pertumbuhan ekonomi, polusi udara, air, dan laut serta kaitannya dengan kesejahteraan umat manusia ke depannya. Secara keseluruhan, Prinsip 1 dalam Deklarasi Stockholm menegaskan hak asasi manusia terhadap kebebasan, kesetaraan, dan kondisi lingkungan hidup yang layak, serta menekankan tanggung jawab setiap individu untuk merawat lingkungan demi kepentingan generasi saat ini dan masa depan.
Prinsip 2, 3, dan 5 memaparkan pedoman dasar untuk melindungi berbagai sumber daya alam bumi –termasuk udara, air, tanah, serta flora dan fauna– serta untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan bagi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Selanjutnya, Prinsip 4, 6, dan 7 mengidentifikasi ancaman terhadap lingkungan serta menegaskan pentingnya melindungi warisan satwa liar dan habitatnya, mengurangi pelepasan racun, dan mencegah pencemaran laut, dengan penekanan pada tanggung jawab negara dalam mencegah kerusakan terhadap sumber daya laut dan hayati.
Sementara itu, Prinsip 8 hingga 15 membahas keterkaitan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, beserta penekanan pada perlunya pendekatan terpadu dalam perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan perlindungan lingkungan serta dukungan finansial dan teknologi. Sedangkan dalam Prinsip 16 hingga 20 menyoroti perlunya pembentukan lembaga khusus untuk pengelolaan sumber daya alam, mengadvokasi penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mempromosikan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmiah.
Lebih lanjut, Prinsip 21 hingga 24 Deklarasi Stockholm merupakan prinsip yang paling erat kaitannya dengan hak dan kewajiban negara, baik secara hukum lingkungan maupun hukum internasional. Prinsip ke 21 menegaskan terkait tanggung jawab Negara untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan di wilayahnya tidak akan menimbulkan kerusakan lingkungan bagi negara lain. Kemudian, Prinsip 22 menyatakan kewajiban negara untuk saling bekerja sama dalam mengembangkan hukum lingkungan internasional, khususnya mengenai pertanggungjawaban bagi korban pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya. Prinsip 23 mengatur mengenai keterbatasan peran regulasi internasional, sehingga dibutuhkan adanya standar lingkungan tertentu yang harus ditetapkan secara nasional berdasarkan karakteristik dan nilai yang berlaku di negaranya masing-masing. Sedangkan Prinsip 24 menyebutkan perlu adanya kerja sama internasional antar negara dan organisasi agar dapat mengendalikan, mencegah, dan mengurangi kerusakan lingkungan secara efektif. Sementara itu, Prinsip 25 menegaskan peran dinamis organisasi internasional dan Prinsip 26 menekankan perlunya perlindungan terhadap manusia dan lingkungan dari senjata nuklir dan alat pemusnah massal lainnya.
Konferensi Tingkat Tinggi Bumi atau Earth Summit Tahun 1992
Dua puluh tahun kemudian, Rio Earth Summit di Rio de Janeiro merupakan perkembangan lanjutan dari kesadaran global tentang isu lingkungan. Konferensi ini juga, sebagai tindak lanjut dan peringatan 20 tahun UN Conference on the Human Environment, menyoroti keterkaitan antara faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta pentingnya tindakan lintas-sektor untuk menjaga keberhasilan dari waktu ke waktu.
Pada intinya, konsep pembangunan berkelanjutan yang menjadi isu utama dalam Rio Earth Summit dipahami sebagai pembangunan yang dilakukan dengan memenuhi kebutuhan saat ini tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Adapun tujuan pembangunan ini merupakan hal yang dapat dicapai oleh semua orang di dunia, terlepas dari apakah mereka berada di tingkat lokal, nasional, regional, atau internasional. Beberapa pencapaian yang dihasilkan dari Rio Earth Summit antara lain, diadopsinya Deklarasi Rio yang berisi 27 prinsip pembangunan berkelanjutan, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), serta Deklarasi tentang prinsip-prinsip pengelolaan hutan.
Konsep pembangunan berkelanjutan yang menjadi isu utama dalam Rio Earth Summit dipahami sebagai pembangunan yang dilakukan dengan memenuhi kebutuhan saat ini tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi mendatang
Lebih lanjut, Deklarasi Rio, yang diadopsi oleh 178 negara anggota ini berisi 27 prinsip yang mengatur manusia sebagai pusat perhatian dalam pembangunan berkelanjutan (Prinsip 1); keutamaan pemberantasan kemiskinan (Prinsip 5); pentingnya lingkungan untuk generasi sekarang dan masa depan dan kesetaraannya dengan pembangunan (Prinsip 3 dan 4); pertimbangan khusus untuk negara-negara berkembang (Prinsip 6); dan prinsip tanggung jawab yang sama tetapi berbeda atau common but differentiated responsibilities (Prinsip 7).
Deklarasi ini juga mengabadikan dua prinsip ekonomi yang sangat penting, yaitu prinsip pencemar membayar (Prinsip 16) dan pendekatan kehati-hatian (Prinsip 15). Selain itu, deklarasi ini juga memperkenalkan prinsip-prinsip tentang partisipasi dan pentingnya kelompok-kelompok tertentu untuk pembangunan berkelanjutan (Prinsip 10, 20, 21, 22) serta meminta Negara-negara Anggota untuk mengembangkan hukum lingkungan nasional yang memadai, termasuk standar lingkungan, kompensasi dan penilaian dampak lingkungan.
Declaration on the Environmental Rule of Law
Seiring dengan berjalannya waktu sejak Rio Earth Summit, kesadaran akan isu lingkungan semakin meningkat secara global. Banyak negara yang telah memperkuat undang-undang lingkungan mereka dan mendirikan lembaga kementerian khusus untuk pengelolaan lingkungan. Per tahun 2017, terdapat 176 negara di seluruh dunia yang telah memiliki undang-undang lingkungannya sendiri yang dijalankan oleh ratusan lembaga dan kementerian terkait Tidak hanya itu, pada tahun 2017 setidaknya 187 negara telah memberlakukan penilaian lingkungan sebagai instrumen yang digunakan saat terdapat proyek-proyek yang berpotensi berdampak negatif pada lingkungan.
Dalam mendukung upaya negara-negara untuk memenuhi kewajiban internasional mereka secara domestik, Dewan Pengurus UNEP mengadopsi dokumen internasional pertama yang menetapkan konsep “Environmental Rule of Law” pada bulan Februari 2013. Keputusan tersebut, yang berjudul “Memajukan Keadilan, Tata Kelola, dan Hukum untuk Keberlanjutan Lingkungan”, menyoroti bahwa aturan hukum, disertai dengan institusi yang kuat, menjadi kunci bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin meningkat dengan cara yang memperhatikan hak-hak dasar dan prinsip-prinsip keadilan, termasuk bagi generasi mendatang.
Dalam konteks keputusan tersebut, negara-negara anggota juga mengakui pentingnya supremasi hukum dan tata kelola yang efektif dalam lingkup lingkungan hidup untuk mengurangi pelanggaran hukum lingkungan dan mencapai pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. Berdasarkan resolusi tersebut, UNEP kemudian terus mengembangkan kerangka kerja EROL dan mendorong implementasinya di semua tingkatan untuk memastikan mekanisme pelaksanaan yang tepat waktu, tidak bias, dan independen.
Pada tahun 2016, UNEP bersama International Union for Conservation of Nature (IUCN) mengeluarkan “IUCN World Declaration on the Environmental Rule of Law“, yang memaparkan 13 prinsip sebagai landasan bagi pembangunan dan implementasi pembangunan berkelanjutan secara ekologis. Deklarasi ini menegaskan pentingnya supremasi hukum dalam melindungi nilai-nilai lingkungan, sosial, dan budaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan secara ekologis. Oleh karena itu, tanpa aturan hukum lingkungan yang ditegakkan secara efektif, tata kelola, konservasi, dan perlindungan lingkungan dapat menjadi subyektif, tidak dapat diprediksi, dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.
Lebih lanjut, deklarasi ini terbagi menjadi empat bagian. Bagian awal menjelaskan landasan EROL, yang didefinisikan sebagai kerangka hukum yang memasukkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara ekologis ke dalam negara hukum. Bagian kedua menjelaskan 13 prinsip lingkungan yang penting untuk mencapai keadilan ekologis. Secara garis besar, prinsip-prinsip yang termuat dalam deklarasi ini mengatur mengenai kewajiban setiap pihak, baik negara, organisasi, maupun individu, untuk senantiasa menjaga kelestarian lingkungan dan membatasi penggunaan serta eksploitasinya. Deklarasi ini juga menjamin adanya peran atau partisipasi masyarakat baik dalam pemeliharaan lingkungan, konservasi dan restorasi, maupun pengambilan keputusan.
Kemudian, bagian ketiga fokus pada unsur-unsur yang mendukung implementasi EROL yang efektif, seperti misalnya mekanisme pengawasan dan tata kelola kolaboratif. Bagian terakhir, sebagai penutup, mendorong kontribusi dari semua sektor sebagai tanggung jawab bersama untuk melakukan pembangunan dan pemeliharaan EROL demi generasi masa kini dan masa depan.
Terkait 13 prinsip lingkungan dalam deklarasi IUCN, prinsip tersebut merupakan landasan untuk mencapai keadilan lingkungan melalui EROL, dengan menekankan hak manusia atas lingkungan dan kewajiban menjaga keutuhan ekosistem. Prinsip pertama dalam deklarasi IUCN menegaskan kewajiban setiap negara dan individu untuk menjaga lingkungan dan mengendalikan penggunaannya. Prinsip kedua dan ketiga menjamin hak manusia terhadap alam dan lingkungan, memastikan bahwa setiap individu memiliki hak atas konservasi, perlindungan, dan pemulihan ekosistem. Setiap orang, saat ini maupun di masa mendatang, memiliki hak atas lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan lestari.
Prinsip keempat berfokus pada ketahanan sistem sosial-ekologis, prinsip ini memastikan bahwa lingkungan alam yang sehat harus selalu menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan, legislasi, dan pengambilan keputusan. Prinsip kelima, yang diperkenalkan dalam deklarasi, adalah prinsip “In Dubio Pro Natura“, yang menegaskan bahwa keputusan harus diambil tanpa membahayakan lingkungan saat terdapat keraguan. Sedangkan prinsip keenam mengatur kewajiban pemilik properti untuk menjaga fungsi lingkungan dan menghindari kegiatan yang dapat merusaknya.
Deklarasi ini juga mengakui prinsip keadilan antar bangsa (intragenerational equity) dan antar generasi (intergenerational equity). Prinsip ketujuh menekankan perlunya akses dan pemanfaatan alam secara adil, merata, dan berkelanjutan. Prinsip delapan menegaskan tanggung jawab generasi saat ini untuk memastikan bahwa kesehatan, keanekaragaman, dan keindahan lingkungan yang dirasakannya sekarang dapat dipertahankan atau dipulihkan agar dapat memberikan akses terhadap lingkungan yang sama dan adil kepada generasi yang akan datang.
Sementara itu, prinsip kesembilan hingga sebelas menjamin kesetaraan gender dan hak bagi kelompok minoritas dan masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Prinsip kedua belas melarang negara untuk melakukan tindakan yang merugikan perlindungan dan keadilan terhadap lingkungan. Adapun prinsip ketiga belas menekankan perlunya pembaharuan dan perbaikan undang-undang lingkungan sesuai dengan perkembangan ilmiah dan kebijakan terkini untuk memajukan EROL.
 Ilustrasi perubahan tutupan hutan
Ilustrasi perubahan tutupan hutan
Perkembangan Green Regulation terkait Indirect Land Use Change (ILUC)
Konsep perubahan penggunaan lahan tidak langsung (ILUC) pertama kali diperkenalkan oleh Searchinger pada tahun 2008 sebagai respons terhadap pelepasan emisi gas rumah kaca yang tidak disengaja karena perluasan lahan pertanian untuk produksi bahan bakar nabati (biofuels). Landasan utama dari konsep ILUC adalah asumsi bahwa penggunaan komoditas pertanian sebagai bahan baku biofuels akan meningkatkan permintaan lahan tambahan di luar penggunaan yang sudah ada (seperti untuk pangan, pakan ternak, serat, dan bahkan kawasan hutan). Untuk memenuhi permintaan tambahan ini, komoditas asli harus dipindahkan ke lahan lain, yang mungkin tidak sesuai, atau kawasan hutan harus dikonversi menjadi kawasan pertanian bahan baku biofuels, sehingga menyebabkan perubahan penggunaan lahan.
Dampak yang ditimbulkan dari ILUC dapat bersifat lintas batas (kabupaten, provinsi, bahkan negara). Adapun dampak negatif nya mencakup potensi pengurangan emisi GRK yang terganggu oleh penggunaan lahan yang tidak sesuai dan risiko terhadap ketahanan pangan. Perubahan penggunaan lahan menjadi perkebunan atau hutan tanaman industri menjadi lahan baku biofuels juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, serta mengancam kelestarian alam.
Lebih lanjut, Penelitian Searchinger juga mengulas dampak emisi dari konversi lahan pertanian menjadi lahan biofuels sebagai tanggapan terhadap pengalihan lahan dari pertanian ke produksi biofuels. Pada akhirnya, dampak negatif terhadap emisi yang ditemukan menimbulkan kekhawatiran di kalangan komunitas LSM mengenai target biofuels. Temuan Searchinger kemudian mendorong para pembuat kebijakan untuk mengatasi ILUC dalam konsumsi biofuels, memastikan bahwa kebijakan tersebut menghasilkan pengurangan emisi GRK bersih.
Sementara itu, perkembangan pengaturan ILUC di AS sendiri sudah dimulai sejak tahun 2005, tepatnya dalam Energy Policy Act tahun 2005 yang memperkenalkan Standar Bahan Bakar Terbarukan (Renewable Fuel Standard/RFS), yang meningkatkan peran biofuels sebagai pengganti bahan bakar fosil di sektor transportasi dengan bahan bakar terbarukan seperti etanol dan biodiesel. Energy Independence and Security Act (EISA) tahun 2007 kemudian memodifikasi RFS dengan menetapkan target konsumsi biofuels sebesar 140 juta meter kubik pada tahun 2022 yang harus menghasilkan pengurangan emisi GRK siklus hidup sebesar 20 persen, baik dari emisi langsung maupun tidak langsung – termasuk dari ILUC.
Selain upaya federal untuk mengatasi ILUC, beberapa negara bagian juga memasukkannya ke dalam undang-undang mereka. Dewan Sumber Daya Udara California memasukkan pertimbangan pengurangan risiko ILUC dalam Standar Bahan Bakar Rendah Karbon (Low-Carbon Fuel Standard atau LCFS) California yang diadopsi pada tahun 2009. Pendekatan yang digunakan oleh LCFS kemudian mengakibatkan etanol berbasis jagung Midwest gagal menghasilkan pengurangan emisi GRK ketika memperhitungkan risiko ILUC, sementara etanol tebu Brasil lolos. Meskipun peraturan ini menimbulkan perlawanan karena kekhawatiran akan membahayakan pasar etanol nasional, perhatian terhadap ILUC terus berkembang, mendorong diskusi lebih lanjut tentang dampak biofuel terhadap lingkungan.
Sedangkan di Eropa, EU Renewable Energy Directive tahun 2009 mengatur kriteria keberlanjutan untuk biofuels, berfokus pada penghematan emisi GRK dan perubahan penggunaan lahan langsung. Namun, bukti-bukti dari komunitas NGO dan Komisi Eropa menunjukkan dampak negatif ILUC terhadap ketahanan pangan, kemiskinan, dan emisi GRK. Kekhawatiran juga muncul terhadap kriteria keberlanjutan yang diatur dalam EU Renewable Energy Directive tidak dapat menangani ILUC secara efektif.
Berdasarkan perkembangan terbaru, Uni Eropa telah merancang kembali Renewable Energy Directive untuk tahun 2030 (RED II) dengan target energi terbarukan 14% dalam transportasi. Arahan ini mencakup ketentuan untuk membatasi kontribusi bahan baku biofuels yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung (ILUC), yang terjadi ketika peningkatan permintaan bahan baku mengarah pada perluasan pertanian dan konversi lahan alami. Kontribusi biofuels yang menyebabkan ILUC ini dibatasi pada tingkat konsumsi tahun 2019 di setiap Negara Anggota UE, dan secara bertahap dikurangi hingga nol pada tahun 2030. Biofuels yang disertifikasi sebagai bahan baku yang diproduksi dari bahan baku dengan “ILUC rendah” dikecualikan dari batasan ini. Lebih lanjut, RED II mendefinisikan biofuels “ILUC tinggi” sebagai biofuel yang diproduksi dari bahan baku yang memiliki ekspansi yang signifikan ke lahan dengan cadangan karbon yang tinggi. Sedangkan biofuels “ILUC rendah” didefinisikan sebagai biofuel yang diproduksi dari bahan baku yang menghindari perpindahan tanaman pangan dan tanaman pakan melalui praktik pertanian yang lebih baik atau melalui penanaman di area yang sebelumnya tidak digunakan untuk produksi tanaman.
Green Regulation dan Konsep Ekonomi Hijau
“Green Regulation” adalah wujud dari Konsep Ekonomi Hijau, yang diterapkan di banyak negara dan dalam skala yang semakin besar. Pertumbuhan ekonomi hijau merupakan suatu gerakan terkoordinir yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, penurunan tingkat kemiskinan dan keterlibatan sosial yang didorong oleh pengembangan dan pemanfaatan sumber daya global secara berkelanjutan.
Berdasarkan kacamata ekonomi, penyalahgunaan pemanfaatan sumber milik bersama timbul karena tidak adanya mekanisme keseimbangan yang timbul secara sendiri yang dapat membatasi eksploitasi. Ketika sudah terjadi eksploitasi secara berlebihan tentu dapat menimbulkan berbagai masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan di tingkat global dan lokal.
Muaranya sesungguhnya ada pada tekanan upaya negara-negara untuk memenuhi kewajiban internasional mereka secara domestik. Dewan Pengurus UNEP mengadopsi dokumen internasional pertama yang menetapkan konsep EROL pada bulan Februari 2013. Indonesia sebagai negara produsen harus memenuhi kesepakatan dunia untuk “Memajukan Keadilan, Tata Kelola, dan Hukum untuk Keberlanjutan Lingkungan”, sehingga aturan hukum, disertai dengan institusi yang kuat, menjadi kunci bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin meningkat dengan cara yang memperhatikan hak-hak dasar dan prinsip-prinsip keadilan, termasuk bagi generasi mendatang.
Deklarasi EROL terbagi menjadi empat bagian. Bagian awal menjelaskan landasan EROL, yang didefinisikan sebagai kerangka hukum yang memasukkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara ekologis ke dalam negara hukum. Bagian kedua menjelaskan 13 prinsip lingkungan yang penting untuk mencapai keadilan ekologis. Secara garis besar, prinsip-prinsip yang termuat dalam deklarasi ini mengatur mengenai kewajiban setiap pihak, baik negara, organisasi, maupun individu, untuk senantiasa menjaga kelestarian lingkungan dan membatasi penggunaan serta eksploitasinya. Deklarasi ini juga menjamin adanya peran atau partisipasi masyarakat baik dalam pemeliharaan lingkungan, konservasi dan restorasi, maupun pengambilan keputusan. Sehingga kesimpulan sementara, regulasi hijau dari negara negara maju saat ini seperti EUDR, sesungguhnya merupakan implementasi untuk pemenuhan Deklarasi EROL. ***
Oleh: Ir. Diah. Y. Suradiredja, M.H (Mahasiswa Program Doktoral, IPB University)

